Rabu, 12 Juli 2023
Home »
penjajahan di indonesia
» penjajahan di indonesia
penjajahan di indonesia
By Lampux.blogspot.com Juli 12, 2023
membawa cukup banyak rempah-rempah ke negeri Belanda. Sejak saat itu
banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang melakukan ekspedisi untuk
mencari rempah-rempah Indonesia. Pada tahun 1601 empat belas buah
ekspedisi yang berbeda diberangkatkan dari Belanda setelah armada dibawah
pimpinan Jacob van Neck berhasil memperoleh keuntungan sebanyak 400
persen pada tahun 1599.1
Banyaknya kedatangan para pedagang Eropa ke Indonesia menyebabkan
persaingan yang sangat ketat antar pedagang dan perusahaan. Persaingan
ketat antara perusahaan pelayaran niaga dalam mengklaim monopoli
perdagangan di Asia, khususnya Nusantara menyebabkan keuntungan yang
diperoleh merosot. Untuk mengatasi hal itu pihak pemerintah Belanda
memutuskan untuk menyatukan semua perusahaan pelayaran niaga tersebut
dalam satu perusahaan saja. Pada tanggal 20 Maret 1602 dengan bantuan
pemerintah masing-masing, dan intervensi keluarga Oranye (Pangeran
Mauritz), Staten General mengeluarkan sebuah surat izin (Octrooi) pada
Hal ini membuktikan bahwa wilayah Indonesia
sudah mulai menjadi tujuan utama dan incaran tokoh imperialisme yang
mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi industri negerinyasebuah perusahaan yang dinamakan Verenigde Oostindische Compagnie
(Serikat Perusahaan Perdagangan di Asia Timur).2
Perkembangannya, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) tidak
hanya menciptakan jabatan Gubernur Jenderal untuk menangani secara lebih
tegas lagi urusan-urusan VOC di Asia, tetapi juga mempunyai sebuah markas
besar yang tetap yaitu di Jayakarta. Nama Jayakarta sendiri kemudian diubah
menjadi Batavia3
2 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah
Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (1700-1900).
Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 29.
3 Batavia diambil dari nama suku bangsa Jerman Kuno di negeri
Belanda, lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam
Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia (1700-
1900). Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 45.
setelah Jenderal Jan Pieterszoon Coen merebut Jayakarta
dari Pangeran Wijayakrama. Pangeran Wijayakrama adalah seorang pangeran
beragama islam yang memerintah Jayakarta sebagai wakil dari kerajaan
Banten.
Coen kemudian membangun benteng-benteng pertahanan dan
membangun sebuah kota baru yang memiliki pola dan tata letak meniru kotakota di negeri Belanda di kota Batavia. Sejak saat itu Batavia menjadi pusat
persekutuan dagang VOC untuk wilayah Hindia bagian timur. Pembangunan
pusat pemerintahan Belanda di wilayah koloni ini menyebabkan mulai
berdatangannya bangsa Belanda untuk mengadu nasib di negeri jajahan
Nusantara.
Perkembangan VOC sejalan dengan pembangunan kota Batavia. VOC
yang dibekali dengan hak istimewa4
, menjelma menjadi sebuah pemerintahan
yang mempunyai struktur yang rapi bak sebuah negara bagian dari Kerajaan
Belanda. Padahal pada awal pembentukannya, VOC hanyalah sebuah
perusahaan yang dirancang untuk melakukan perdagangan secara monopoli
antara Asia dan negeri Belanda. Pembangunan kota Batavia berjalan dengan
sangat pesat. Jumlah penduduk kota Batavia meningkat sampai tiga kali lipat
dalam jangka waktu delapan tahun, meskipun pembangunan kota baru selesai
pada tahun 1650.5
Penduduk yang terdapat di kota Batavia pada masa itu pun semata-mata
terkait dengan kegiatan VOC yang monopolistik. Menurut R. Z. Leirissa
penduduk kota Batavia pasa masa itu dapat dibagi menjadi enam katagori,
yaitu:6
1. Pegawai dan tentara VOC;
2. Vrijburger atau bekas pegawai atau tentara VOC yang tidak mau
kembali ke tanah airnya;
3. Mestizo atau orang yang berdarah campuran Belanda-Asia;
4. Mardijker atau bekas budak yang telah dibebaskan;
5. Orang-orang Asia (sebagian besar adalah orang Cina);
6. Berbagai etnis lain dari Nusantara.Kedatangan sejumlah pegawai-pegawai VOC ke Hindia Belanda inilah
yang mempengaruhi lahirnya sistem pernyaian di Hindia Belanda khususnya
di Pulau Jawa. Kebanyakan dari pegawai-pegawai Eropa itu datang ke Hindia
Belanda sebagai perjaka. Alasannya adalah adanya peraturan yang tidak
memperbolehkan untuk menikah, selain itu juga karena pegawai-pegawai
Eropa baru tersebut belum mempunyai pendapatan yang memadai untuk
menanggung sebuah keluarga Eropa. Mereka memang bermaksud untuk
menikah dengan seorang wanita Eropa begitu mereka kembali ke tanah
airnya. Karena itu perkawinan dengan wanita pribumi tidak biasa terjadi,
walaupun bukan tidak pernah terdengar.7
The more well-to-do officials and estate-owners could have more than
one concubine, at least at the beginning of the nineteenth century: Van
Reede tot de Parkeler, Governor og Java’s Northeast Coast had
twenty ‘favourites’, Van Bronckhorst, Resident of Juwana, had a
‘serail’, and Van Lawick van Pabst, Commissioner of Native Affairs in
Buitenzorg and the Priangan, was reported to have inspected his
district with his concubines in attendance (all examples between 1800
and 1810)
Diantara pegawai-pegawai Eropa
tersebut memilih untuk tinggal dengan nyai pribumi sebagai gundikPernyataan Peter Boomgard diatas membuktikan bahwa pengambilan
seorang nyai oleh para pegawai Eropa sangat digemari, mereka tidak hanya
akan mengambil seorang nyai saja, tetapi bahkan lebih dari satu. Hal ini
dipicu pemikiran bahwa memelihara seorang nyai dianggap lebih bermanfaat
dan menguntungkan. Tidak semua orang Jawa bisa menganggap bentuk pernyaian ini sebagai hal yang tepat, tetapi perilaku ini tidak mengalami
perlawanan secara terang-terangan.
Nyai merupakan lambang romantisme seksual yang memberi kunci
suksesnya kolonialisme. Sampai abad ke 20, menurut dongeng orang-orang
kaya Belanda yang menetap atau bertugas ke Hindia Belanda dinasehatkan
selekas mungkin memelihara Nyai sehingga si “majikan” dapat mempelajari
bahasa, adat istiadat, dan misteri di “Timur” dengan cepat.9
Politik Pintu Terbuka juga turut andil dalam mempengaruhi jumlah
pegawai-pegawai Eropa yang datang ke Hindia Belanda. Pembangunan
ekonomi dalam bentuk perkebunan-perkebunan, industri-industri manufaktur,
maupun industri pertambangan mengakibatkan dibutuhkan lebih banyak lagi
tenaga kerja. Dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 mendukung migrasi
para pegawai Eropa ke Hindia Belanda menjadi semakin mudah. Awalnya
sebagian besar imigran Eropa terdiri atas golongan militer, yang besar kecil
jumlahnya tergantung pada keadaan peperangan yang terjadi di Hindia
Negeri “Timur”
adalah sebutan untuk wilayah koloni di Asia Timur yang jaraknya sangat jauh
dari negeri Belanda, memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat
sampai ke sana. Selain menghabiskan banyak waktu dalam perjalanannya,
kondisi wilayah koloni juga masih sangat jauh terbelakang bagi bangsa
Belanda. Berbagai fasilitas publik yang sudah ada di Belanda tidak dapat
dijumpai di sanaBelanda. Akan tetapi semenjak perdagangan, perkebunan, dan industri di
Hindia Belanda mengalami pertumbuhan pesat di akhir abad 19 dan awal
abad 20, maka kehadiran imigran para kapitalis dan profesional sipil Eropa
semakin banyak jumlahnya.10
Sebenarnya praktik pernyaian sudah banyak terjadi di kalangan para
pedagang Asia dan Portugis ketika jumlah kaum pria Belanda atau Eropa
tidak sebanding dengan jumlah kaum wanita Belanda atau Eropa yang ada.
Meningkatnya arus kedatangan orang-orang
Eropa ke Jawa baik sebagai pejabat pemerintah kolonial maupun sebagai
pengusaha swasta penenaman modal pada industri perkebunan, telah
menimbulkan derasnya arus modernisasi gaya hidup.
B. Kondisi Jawa pada Tahun 1870-1942
Jumlah kaum wanita Belanda atau Eropa yang jauh lebih sedikit
mengakibatkan semakin maraknya praktik pernyaian pada masa
pemerintahan Belanda di Hindia Belanda sejak dibentuknya VOC di Batavia.
Memang harus diakui bahwa kebutuhan seksual menghadirkan nyai di daerah
perkebunan, di dunia sipil, maupun dalam tangsi-tangsi militer.
Pada tahun 1870 hingga 1942 terjadi beberapa tahap peristiwa yang
penting bagi negara Indonesia. Walaupun Negara Kesatuan Republik
Indonesia belum terbentuk, namun pada sekitaran tahun inilah mulai terjadi
perubahan besar bagi rakyat pribumi. Peristiwa awal adalah dihapuskannya cultuurstelsel12
1. Politik Kolonial Liberal
(Sistem Tanam Paksa) dan digantikan dengan politik kolonial
Liberal. Politik kolonial Liberal ditandai dengan dikeluarkannya UndangUndang Agraria pada tahun 1870, kemudian disusul politik Ethis dan
berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada 1942.
Tahun 1870 menjadi masa yang penting dalam perjalanan sejarah
bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pada tahun ini menjadi tonggak
awal modernisasi di Hindia Belanda khususnya di Jawa. Masa antara 1870
sampai dengan 1900 dalam sejarah kolonial dilihat sebagai masa Liberal.
Artinya masa dimana pemerintah melepaskan peranan-peranan
ekonominya (Tanam Paksa, Monopoli rempah-rempah) dan menyerahkan
eksploitasi ekonomi kepada modal swasta. Pemerintah hanya bertindak
sebagai wasit atau penjaga keamanan yang dilakukan melalui birokrasi dan
tentaranya.
Rakyat mengalami masa penderitaan sangat berat akibat
Cultuurstelsel hingga tahun 1870, yang banyak merenggut nyawa rakyat
Dimulai dari tahun inilah Hindia Belanda mengalami
perubahan yang sangat besar, banyaknya pihak swasta yang datang ke
Hindia Belanda membawa pengaruh modernisme dari berbagai negara. pribumi. Permasalahan yang timbul akibat Cutuurstelsel ini
mengakibatkan munculnya pertentangan di negeri Belanda. Melalui sistem
ini Belanda mengalami surplus keuangan tetapi ini tidak dibenarkan
karena dianggap melakukan penindasan terhadap orang-orang Jawa dan
Sunda. Penindasan ini dianggap tidak manusiawi karena mempekerjakan
rakyat pribumi tanpa memberikan upah, rakyat pribumi diharuskan terus
bekerja tanpa imbalan yang setimpal.
Tahun 1860, seorang mantan pejabat kolonial, Eduard Douwes
Dekker menerbitkan sebuah novel yang berjudul Max Havelaar dengan
nama samaran ‘Multatuli’.
Perdebatan yang terjadi antara kaum liberal yang menginginkan
dihapuskannya sistem Tanam Paksa dan kaum Konservatif, akhirnya
mencapai kesepakatan yaitu dengan dihapuskannya sistem Tanam Paksa
ini sedikit demi sedikit. Kaum Konservatif merupakan kelompok yang
tetap ingin mempertahankan sistem Tanam Paksa karena telah berhasil
Buku ini mengisahkan tentang keadaan
pemerintah kolonial atas penindasannya terhadap rakyat pribumi melalui
sistem Tanam Paksa di Jawa. Ternyata buku ini menjadi senjata ampuh
dalam menentang rezim penjajahan pada abad ke-19 di Jawa. Munculnya
novel yang berlatar keadaan nyata rakyat Hindia Belanda telah
memberikan opini masyarakat dunia khususnya kaum liberal. Tanam
Paksa ini dianggap perbuatan yang telah melanggar hak-hak asasi
manusia, hingga banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak.memberikan keuntungan yang besar kepada negeri Belanda. Penghapusan
dilakukan mulai dari komoditi yang paling sedikit mendatangkan
keuntungan atau yang tidak menguntungkan sama sekali.
Perubahan besar terjadi dalam masyarakat pribumi setelah golongan
liberal yang didukung oleh orang-orang borjuis menduduki posisi ekonomi
dan politik yang kuat sampai dengan tahun 1880-an. kerja paksa kemudian
dihapus dan digantikan dengan kerja bebas. Kepentingan politik golongan
liberal membawa dampak ekonomi di wilayah koloni dengan didirikannya
infrastruktur kolonial seperti jalan kereta api dan trem, dinas pos, bank,
dan perusahaan swasta. Usaha golongan liberal berjalan lancar dan
keuntungan juga diperoleh dengan mudah.15
Usaha golongan liberal mendapat jalan setelah pemerintah Hindia
Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870.
Undang-undang ini pada dasarnya melarang penjualan tanah kepada orang
asing tetapi mereka hanya diperkenankan menyewanya dalam waktu 75
tahun.
Seiring dengan pembangunan
yang dilakukan di Hindia Belanda, modernisasi mulai terasa di wilayah
koloni. Modernisasi ini didukung dengan kedatangan para pegawai Eropa
dalam jumlah banyak ke Hindia Belanda setelah dibukanya terusan Suez
pada tahun 1869.
Setelah itu pihak-pihak swasta berbondong-bondong datang ke
Hindia Belanda untuk membangun berbagai pusat ekonomi seperti perusahaan-perusahaan perkebunan (onderneming), industri-industri
manufaktur, industri pertambangan, serta jaringan distribusi perdagangan.
Sejak diterapkannya Undang-undang Agraria, terjadilah proses
swastanisasi dan modernisasi perekonomian dalam masyarakat di Hindia
Belanda.
Perkembangan sejak tahun 1870 menimbulkan banyak perubahan
berikutnya. Jaringan komunikasi (jalan) lebih mendekatkan desa dengan
pusat-pusat administrasi. Akibat sistem komunikasi ini adalah timbulnya
interaksi yang lebih banyak antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan.
Selain itu timbul pula interaksi antara pulau yang satu dengan pulau
lainnya, terutama antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Manusia
dan barang dapat diangkut dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif
singkat dibanding dengan zaman-zaman sebelumnya.
Maka semakin kuatlah peranan pengusaha ataupun investor
swasta dalam perekonomian kolonial di Hindia Belanda.
Pulu Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda
menjadi wilayah yang mengalami perubahan yang sangat besar. Hutanhutan dibabat dan digantikan dengan perkebunan-perkebunan yang
didirikan di beberapa wilayah Jawa. Pabrik-pabrik gula dibangun dengan
megah, rel kereta api, dan jalan raya yang menghubungkan antar kota
semakin banyak hingga mobilisasi menjadi lebih mudah. Seiring dengan
pembangunannya yang sangat pesat, Pulau Jawa berubah menjadi pusat
kegiatan pemerintah Belanda di Hindia Belanda.
Sejak saat itu masyarakat kesukuan mulai membaur terutama di
daerah-daerah perkotaan. Perpindahan penduduk dari pulau lainnya
menuju pulau Jawa atau dari desa ke pusat-pusat perekonomian seperti
perkebunan dan pabrik mengalami kenaikan tajam. Perpindahan penduduk
ini dilakukan sebagian besar oleh laki-laki lajang yang bertekad ingin
mendapatkan pekerjaan. Jumlah laki-laki lajang di perkebunan-perkebunan
inilah yang menimbulkan adanya praktik pernyaian di perkebunan swasta.
Orang-orang Belanda juga makin banyak dan makin sering dilihat di
lingkungan pedesaan, jaringan administrasi makin diperluas ke daerah
pedesaan. Ini berarti cara-cara pemerintahan Barat berangsur-angsur
menggantikan segi-segi tertentu dari cara-cara pemerintahan tradisional.
Tampak secara jelas bahwa sejak tahun 1870 modernisasi dan kemajuan di
dalam kehidupan ekonomi merupakan akibat yang nyata,
2. Politik Ethis
Fase penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah
dicetuskannya politik Ethis yang berdampak besar dalam pergerakan
nasional Indonesia. Politik ini juga sering dinamakan Politik Etika, yang
dicanangkan pada tahun 1901 oleh Van Deventer
Orang sering mengaitkan timbulnya sistem Politik Etis dengan tulisan
Van Deventer dalam majalah De Gids (Nomor 63, tahun 1899) yang berjudul Een
Eereschuld atau “Hutang Budi”, lihat Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah
Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai
setelah Ratu Belanda
melontarkan pernyataan bahwa negeri Belanda mempunyai kewajiban
untuk mengusahakan kemakmuran serta pengembangan sosial dan
ekonomi penduduk pribumi.
Politik Ethis menggunakan tiga sila sebagai slogannya, yaitu Irigasi,
Edukasi, dan Emigrasi.
Politik Ethis mencoba mengubah sistem
liberal menjadi sebuah sistem yang dapat dijadikan media pemerintah agar
dapat turut campur urusan-urusan masyarakat.
Perkebunan tebu menghendaki irigasi yang
intensif. Pabrik-pabrik yang banyak jumlahnya, kantor-kantor dagang, dan
cabang-cabang perusahaan lainnya menyebabkan timbulnya kebutuhan
manusia dan tenaga kerja yang lebih murah. Tenaga kerja ini dibutuhkan
tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di propinsi-propinsi luar Jawa, sebagai
daerah-daerah baru yang dibuka untuk perkebunan modern. Perluasan dan
pembesaran birokrasi pemerintah kolonial membutuhkan adanya lapisan
pegawai-pegawai rendahan dalam lembaga pangreh praja (Binnenlands
Bestuur) atau Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Kolonial Hindia
Belanda. Kebutuhan dan desakan kuat golongan Liberal dan Kaum Ethis
mempercepat pemerintah kolonial untuk mendirikan sekolah-sekolah yang
berderajat rendah bagi masyarakat pribumi.
Tersedia pada
Pada akhir abad 19 mulai
bermunculan sekolah pribumi atau sekolah desa, dan baru pada awal abad
20 dibuka sekolah-sekolah tingkat menengah serta tingkat tinggi.Penerapan sistem pendidikan Barat semakin mempercepat laju proses
modernisasi yang merubah secara struktural lapisan-lapisan sosial tertentu
di masyarakat Jawa pada masa itu. Terbentuklah pola-pola hubungan
sosial dalam jaringan yang baru karena proses industrialisasi,
komersialisasi pertanian dan perkebunan, perubahan sistem birokrasi,
urbanisasi, perluasan infra struktur, maupun mobilisasi sosial. Akhirnya
stratifikasi tidak hanya terjadi dalam hubungan sosial, tetapi juga dalam
lapangan pekerjaan. Pada jabatan-jabatan tertinggi dalam birokrasi
pemerintahan diduduki oleh golongan masyarakat Eropa, sedangkan
masyarakat pribumi terkonsentrasi pada jabatan-jabatan yang lebih rendah.
Pada awal abad ke-20, tingkat interaksi antara warga kulit putih
dengan masyarakat pribumi yang semakin tinggi menyebabkan munculnya
golongan Indo Eropa. Golongan tersebut merupakan hasil keturunan dari
perkawinan campuran antara Belanda/Eropa asli dengan wanita pribumi
yang berstatus gundik atau nyai.
Golongan Indo secara yuridis formal
termasuk dalam status golongan Eropa, akan tetapi pada kenyataannya
golongan Eropa totok tidak mau dipersamakan statusnya dengan golongan
mestizo ini. Masyarakat Indo sendiri dalam kehidupannya lebih
berorientasi kepada budaya Eropa. Mereka berusaha mengingkari garis
asal keturunan dari ibunya yang berasal dari masyarakat pribumi.Munculnya Pernyaian di Jawa
Praktik pernyaian pada masa penjajahan sudah bukan menjadi hal tabu
lagi, status nyai bahkan menjadi idaman para gadis-gadis pribumi agar dapat
merubah status sosialnya menjadi lebih tinggi. Walaupun masih ada
sekelompok masyarakat dari kalangan pribumi maupun kalangan kolonial
yang menentangnya. Terutama dalam masyarakat desa yang menganggap
perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat yang tertata baik,
harmonis, dan produktif. Seperti yang diungkapkan oleh Peteer Boomgard;In such a society concubinage, at least among the indigenous
population, was taboo. Erlier writers do not mention it all, either
because it was too absurd a notion, or because it had escaped their
attention. Later no a number of authors stated that concubinage was not
permitted, but other sources suggest that it was much in evidence. It
could be that concubinage was restricted to specific groups: Poensen,
whose material came from Kediri, mentioned it as a typical urban
phenomenon, and Krawang, where the Resident reported the frequent
occurrence of unlawful unions, had a large proportion of people
engaged in fishing, slat-making, industry, commerce and trade.
Concubinage, no doubt as much a source of trouble as the presence of
many bachelors, may indeed have been virtually absent from most
villages.
Masyarakat desa menginginkan suatu masyarakat yang harmonis seperti
yang dijelaskan sebelumnya, memelihara seorang selir atau gundik dianggap
sesuatu yang tabu. Sejumlah pengarang menyatakan bahwa memelihara selir
atau gundik tidak diperbolehkan, tetapi sumber lain menunjukkan bahwa
ternyata banyak yang melakukannya. Bahwa memelihara seorang nyai hanya
terbatas pada kelompok tertentu. Di daerah perkotaan dan sejumlah tempat indutri, memelihara seorang gundik tidak dapat disangkal lagi, yang
merupakan sumber keresahan bagi banyak laki-laki lajang.
Sejak awal abad 17 banyak pejabat-pejabat kolonial bahkan memelihara
lebih dari satu nyai. Seorang gubernur pesisir laut Jawa dikatakan memiliki
dua puluh orang perempuan “kesayangan” bangsa pribumi. Kemudian
disebut-sebut pula nama pejabat lain yang memelihara nyai, yaitu Van Reed,
Residen Juwana, Van Lawick, dan seorang pejabat Komisi Urusan Bumiputra
di Buitenzorg. Semua contoh ini diambil dari tahun 1800-1810.
1. Jumlah Laki-laki Eropa atau Belanda Lebih Banyak Dibandingkan
Jumlah Perempuan Eropa atau Belanda.
Terdapat beberapa penyebab mengapa praktik pernyaian tumbuh begitu
kuat di tanah jajahan, antara lain;
Pada awalnya sistem pernyaian mulai marak di Batavia pada masa
pemerintahan VOC meskipun sesungguhnya jauh sebelum Belanda
tampil di Asia. Praktik pergundikan sudah banyak terjadi di kalangan para
pedagang Asia dan Portugis ketika jumlah kaum pria Belanda atau Eropa
tidak sebanding dengan jumlah kaum wanita Belanda atau Eropa yang
ada.
Hal tersebut menjelaskan bahwa kaum pendatang dari Eropa adalah
laki-laki, baik laki-laki yang masih bujangan atau laki-laki yang sudah
berkeluarga tetapi tidak menyertakan istri dan anak-anaknya untuk ikut ke
negeri jajahan. Menyertakan seorang istri Eropa dianggap akan menimbulkan kesulitan ekonomi maupun sosial bagi mereka nantinya di
tanah koloni. Anggapan ini semakin memberikan alasan pegawaipegawai Belanda atau Eropa memilih berangkat sendiri ke daerah koloni
tanpa didampingi oleh istri atau keluarganya. Mereka hanya ingin
mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, sehingga apabila pulang
kembali ke negeri asal kelak dapat menikmati sisa-sisa umur mereka
dengan berleha-leha bersama istri Eropa yang mereka dambakan.
Alasan lain para lelaki Eropa enggan membawa keluarga mereka ke
daerah koloni adalah perbedaan iklim Eropa dengan daerah tropis seperti
Indonesia yang mencolok. Selain itu, perjalanan melalui laut yang
memakan waktu sangat lama, sekitar 7-10 bulan, dan melelahkan, bahkan
terkadang disertai cuaca yang tidak baik dan penuh bahaya. Perjalanan
seperti ini tentunya sangat berbahaya bagi seorang perempuan, apalagi
perempuan Eropa yang sangat rentan dan tidak terbiasa dengan iklim
tropis.
Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, pemerintahan diambil
alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sistem eksploitasi dan monopoli
peninggalan VOC tetap diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda
dengan penyempurnaan kekuasaan di Nusantara. Perluasan tersebut baik
dalam bidang ekonomi, politik, militer, maupun penyebaran agama
Nasrani. Untuk kepentingan tersebut, maka dibutuhkan personil tambahan
dalam militer dan pegawai sipil baik yang didatangkan dari negeri
Belanda, Eropa lainnya, atau pun dengan jalan perekrutan tenaga pribumi.Pada abad ke-19, kota pelabuhan Batavia menyambut para pendatang
dengan iklim kota yang buruk, kabut menggelantung rendah yang
beracun, parit yang tercemar, dan penyakit-penyakit aneh dengan nama
seram, seperti remitterende rotkoortsen (demam maut), roode loop
(berak-berak merah), febre ardentes, malignae et putridae, dan mort de
chien (demam parah, jahat dan busuk, dan mati mendadak).26 Karena itu,
pendatang Eropa yang datang ke Batavia mayoritas adalah kaum lakilaki, walaupun sudah ada peningkatan jumlah pendatang kaum
perempuan Eropa dari sebelumnya.
Jumlah wanita asing yang tidak sebanding dengan jumlah lelaki
asing di Hindia Belanda dapat dilihat dari sensus penduduk yang
dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Berikut ini
merupakan tabel sensus penduduk pada tahun 1860 hingga 1930.
Sensus penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda
di Hindia Belanda pada tahun 1920 dan 1930 juga masih menunjukkan
bahwa jumlah laki-laki Eropa lebih banyak dibanding perempuan Eropa.
Meskipun jumlah perempuan Eropa yang datang ke Hindia telah
mengalami peningkatan, tetapi dalam hal jumlah laki-laki Eropa d Hindia
Belanda lebih banyak. Dari tiga buku sensus penduduk Hindia Belanda
oleh pemerintah Belanda dapat disimpulkan sebagai berikut.Batavia merupakan wilayah penting dalam pertumbuhan penduduk
Eropa di Hindia Belanda. Kota yang yang menjadi pusat pemerintahan
Belanda di wilayah koloni Hindia Belanda ini menjadi basis pertumbuhan
penduduk Eropa. Terbukti jumlah penduduk Eropa di wilayah Jawa
Barat, hampir 50 persen penduduk Eropa berada di Batavia. Batavia
bukan hanya menjadi tempat peristirahatan bangsa Eropa yang datang ke
Hindia Belanda, tetapi juga menjadi tempat menetap para kulit putih
tersebut.
Jumlah perempuan di Batavia dari tahun 1920 sampai tahun 1930
mengalami meningkatan, karena memang sejak dibukanya terusan Suez perempuan Eropa lebih banyak dikirim ke wilayah koloni. Dalam kurun
waktu 10 tahun, jumlah perempuan meningkat tajam, dari 11.290 hingga
15.243. Peningkatan jumlah perempuan Eropa yang datang ke Hindia
Belanda ternyata masih belum bisa mengimbangi jumlah laki-laki Eropa.
Jumlah kaum perempuan Eropa tetap lebih sedikit diantara jumlah lakilaki Eropa.
Perbandingan jumlah perempuan Eropa dan laki-laki Eropa di Jawa
Barat pada sensus penduduk tahun 1930 adalah sebagai berikut.Pada 4 tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah lelaki Belanda
atau Eropa jauh lebih besar daripada jumlah perempuan Belanda atau
Eropa. Jumlah penduduk Eropa di atas telah ditotal dari jumlah penduduk
Eropa di setiap kota di wilayah masing-masing, yaitu Jawa Barat, Jawa
Tengah, dan Jawa Timur. Dari tahun 1920 hingga 1930 memang terjadi
kenaikan jumlah penduduk perempuan Eropa di Pulau Jawa. jika
dibandingkan pada awal kedatangan bangsa Eropa ke Hindia Belanda
jumlah perempuan Eropa ini sangatlah berbeda. Dari tahun ke tahun
terjadi peningkatan jumlah, hal ini didukung sejak tahun 1869 dibuka
terusan Suez. Karena perjalanan menuju wilayah koloni di Asia menjadi
lebih cepat dan lebih mudah, maka pengangkutan perempuan-perempuan
Eropa ke wilayah Timur menjadi lebih besar jumlahnya.
Perbandingan jumlah laki-laki Eropa dan perempuan Eropa yang
tidak seimbang, dimana laki-laki Eropa jauh lebih banyak mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi laki-laki lajang yang berada di Hindia
Belanda. Bagi seorang laki-laki Belanda atau Eropa, mempunyai istri
seorang Belanda atau Eropa adalah dambaan. Karena kebutuhan
perempuan Eropa tidak sebanding dengan jumlah lelaki Eropa, maka
beberapa lelaki Eropa memilih untuk hidup bersama nyai atau gundik
selagi menunggu seorang perempuan Eropa. Pengambilan seorang nyai
ini menjadi solusi atas jumlah laki-laki Eropa dan perempuan Eropa yang
tidak seimbang.
2. Peraturan gereja yang tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan
beda keyakinan.
Pada zaman kolonial hingga tahun 1848, keagamaan dipergunakan
sebagai pedoman dalam hal-hal perkawinan campuran. Sesuai dengan
struktur masyarakat yang terdapat pada waktu itu, agama yang dianut
oleh penguasa, agama Nasrani, dijadikan pedoman atau pegangan.27
Agama Kristen merupakan trait d’union dalam masyarakat kolonial.
Pemerintah VOC menginginkan penduduk yang penurut, sesuai dengan
norma-norma Kristen sebagai penduduk Belanda di dalam Republik.
Tugas gereja menjadi sangat kompleks, yaitu mencatat kelahiran,
perkawinan, kematian, penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan,
semuanya termasuk di dalam tanggung jawabnya. Akibatnya gereja
Agama digunakan untuk melindungi golongan Belanda. menjadi benar-benar berakar di dalam masyarakat, lebih dari yang diduga
oleh para pengamat di abad ke-20.28
Proses peng-Kristenan bagi masyarakat pribumi pun diusahakan
dengan mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan serta iming-iming
keuntungan. Pribumi yang telah bertaubat akan menerima tunjangan uang
barang sedikit. Lebih dari itu, pemeluk-pemeluk Kristen pribumi tidak
bisa dijual sebagai budak lantaran utang, dan budak-budak Kristen tidak
bisa dijual kepada tuan-tuan budak yang tidak beragama Kristen. Hanya
sesudah pindah agama perempuan pribumi bisa menikah dengan laki-laki
Belanda atau Eropa.29
Sebelum tahun 1848 sebuah pernikahan antara seorang Eropa Kristen
dengan seorang perempuan pribumi non-Kristen merupakan hal yang
dilarang.
Bahkan dapat dikatakan bahwa orang golongan
rendahan dapat beralih kepihak atasan dengan jalan memeluk agama
Kristen ini.
Namun sesuai dengan perubahan zaman, lambat laun kriteria
agama dan larangan perkawinan campuran ini tidak dapat dipertahankan.
Akhirnya pernikahan campuran bukan berarti dilarang sama sekali, hanya
menjadi hal tidak dikehendaki. Perkawinan campuran menjadi sebuah
fenomena sosial yang banyak terjadi antara laki-laki Eropa denganperempuan pribumi dalam hubungan pergundikan. Hal ini sudah menjadi
sesuatu yang wajar terjadi, tetapi kenyataannya segolongan masyarakat
Eropa masih tetap menentang perkawinan campuran.
Seorang laki-laki Eropa Kristen harus menikahi seorang perempuan
Kristen pula. Jadi jika laki-laki Eropa Kristen menginginkan menikah
dengan seorang perempuan pribumi, perempuan tersebut haruslah
beragama Kristen. Apabila perempuan tersebut adalah seorang budak,
maka si lelaki harus menebus kemerdekaan perempuan pilihannya
kemudian dibaptis, baru setelah itu boleh menjadi istri laki-laki
bersangkutan. Sebagai ganti peralihan agamanya, ia memperoleh
kewarganegaraan suaminya. Anak-anak mereka hanya boleh dibaptis jika
ibu mereka orang Kristen yang aktif menganut agamanya.
Rezim
semacam ini telah mendorong lahirnya hubungan tanpa ikatan antara lakilaki Eropa dengan perempuan Asia.
Praktik pernyaian semakin diminati oleh lelaki Eropa ketika
perempuan yang ingin mereka nikahi adalah seorang Islam. Perempuanperempuan pribumi yang beragama Islam lebih enggan untuk pindah
agama ke Kristen. Karena keadaan itu, banyak lelaki Eropa yang tak
pernah menikahi secara resmi perempuan pribumi, melainkan hidup
dengannya sebagai gundik atau nyai.
3. Memelihara seorang nyai dianggap lebih mudah dan menguntungkan
dibandingkan menikah secara resmi dengan seorang perempuan
pribumi.
Pegawai-pegawai Eropa yang datang ke daerah koloni di Asia berarti
mempunyai tekad dan keberanian yang sangat tinggi. Selain melalui
perjalanan laut yang sangat jauh hingga berbulan-bulan, perbedaan iklim
dengan negara asal yang sangat mencolok menjadi satu tantangan berat
tersendiri. Tidak hanya perbedaan iklim saja, tetapi perbedaan bahasa,
adat, dan budaya antara negara asal dengan daerah koloni menjadi alasan
seorang pegawai Eropa harus berpikir matang untuk mau dikirim ke
daerah koloni tersebut.
Obsesi mengumpulkan harta sebanyak mungkin menyebabkan
seorang pegawai Belanda atau Eropa tidak hanya sekedar tinggal
beberapa bulan lamanya di tanah jajahan. Pegawai Eropa akan meniti
karirnya hingga bertahun-tahun bahkan bisa saja seumur hidup, karena itu
mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru di tanah jajahan,
Hindia Belanda. Keadaan dipersulit karena kebanyakan dari mereka
datang sendiri tanpa didampingi seorang istri atau pun keluarga. Sebagian
besar pegawai Eropa yang datang adalah seorang bujangan. Akhirnya
mereka harus berjuang sendiri di tanah baru yang sangat berbeda dengan
negara asal mereka yang sudah maju. Tanah jajahan di Asia oleh orangorang Eropa dianggap daerah terbelakang dan sangat minim fasilitas.Memilih hidup membujang di tanah koloni dianggap sebagai
keputusan yang tepat mengingat kondisi finansial para pegawai Eropa ini
belum memungkinkan untuk menanggung sebuah keluarga. Apalagi
sebuah keluarga yang bergaya hidup Eropa yang senang dengan
kemewahan. Fasilitas-fasilitas hidup di tanah jajahan seperti sekolah
untuk anak-anak yang sangat terbatas, kondisi rumah sakit, dan tempattempat hiburan juga tidak sesuai dengan ukuran kehidupan orang Eropa.
Alasan tersebut semakin memperkuat alasan seorang pegawai Eropa
memilih untuk tidak menikah.
Bukan berarti para pegawai Eropa ini tidak membutuhkan bantuan
orang lain untuk mengurus rumah dan melayaninya dalam kehidupan
sehari-hari. Untuk mengatasinya mereka biasanya mengambil seorang
perempuan pembantu rumah tangga dari kalangan pribumi. Semakin
lama, perempuan pribumi itu tidak hanya membantunya dalam mengurus
rumah tangga, tetapi juga melayani kebutuhan biologis sang tuannya.
Perempuan-perempuan pribumi inilah yang dipanggil dengan nyai.
Memelihara nyai dianggap lebih mudah dan menguntungkan
daripada menikah secara resmi dengan seorang perempuan Eropa.
Memelihara nyai lebih mudah untuk ditinggalkan dan dapat diperlakukan
sekehendak hati. Nyai juga dapat dimanfaatkan dalam hal menjaga
kesehatan tuan Eropanya dibandingkan dengan jika harus berhubungan
dengan pelacur yang tidak terjamin kebersihannya dari berbagai macam
penyakit kelamin menular seperti syphilis, gonorhae dan sebagainya. Hal ini dikarenakan semakin maraknya praktik pelacuran di masa itu yang
ditandai dengan bertambah banyaknya jumlah kompleks pelacuran
terutama di sekitar barak-barak tentara Belanda. Memelihara nyai juga
dianggap lebih terhormat bagi seorang pejabat tinggi dibandingkan jika ia
berkunjung ke kompleks pelacuran.
Jelas bahwa pengambilan seorang nyai atau perempuan pribumi
pada waktu itu sangat menguntungkan bagi seorang pegawai koloni di
tanah jajahan. Namun kelemahannya dalam paparan keuntungan diatas
adalah bahwa hubungan pernyaian haruskan dilandasi atas ketertarikan
antara keduanya. Padahal hanya sedikit hubungan pernyaian yang
didasari atas rasa cinta antara laki-laki Eropa dengan perempuan
pribumi. Hubungan yang terjadi dalam praktik pernyaian adalah
mutualisme. Baik lelaki Eropa-nya maupun perempuan pribuminya
mendapatkan keuntungan, walaupun memang tidak sebanding tentunya
lebih banyak keuntungan untuk sang lelaki Eropa.
Reggie Baay (2010:4) menjelaskan dalam bukunya dengan lebih
rinci:
Gubernur Jenderal yang memimpin dari 1650 sampai 1653, Carel
Reyniersz, dan penggantinya, Joan Maetsuyker, merupakan
pendukung kuat perkawinan antara pegawai VOC dengan
perempuan Asia atau Eurasia. Menurut mereka ada berbagai
keuntungan dari hal tersebut. Para perempuan Asia lebih
menguntungkan daripada perempuan-perempuan Eropa karena biaya
pelayaran perempuan Eropa tentu harus ditanggung oleh laki-laki
sendiri. Keterikatan dengan tanah kelahiran membuat para
perempuan pribumi ingin tetap tinggal di Timur sehingga mereka
pasti akan membujuk suaminya mereka untuk hal serupaJelas bahwa pengambilan seorang nyai atau perempuan pribumi
pada waktu itu sangat menguntungkan bagi seorang pegawai koloni
Jika dibandingkan dengan perempuan Belanda atau Eropa,
perempuan Asia (dalam hal ini adalah pribumi) tidak terlalu serakah.
Memperoleh gaji yang kecil pun mereka sudah puas, dengan demikian
bahaya akan para pegawai untuk memperkaya diri dengan jalan korupsi
dianggap berkurang. Perkawinan campuran ini akan menghasilkan
anak-anak kelak, dimana laki-laki akan menjadi calon pegawai dan
anak perempuan akan menjadi calon pengantin idaman bagi angkatan
baru pegawai dari Belanda.
Kehadiran nyai pribumi juga dimanfaatkan untuk memperoleh
pengetahuan mengenai kebudayaan Melayu, baik dalam bidang bahasa,
kebiasaan, maupun adat istiadatnya.
Dalam dunia perdagangan
maupun pergaulan resmi, seorang Belanda atau Eropa mau tidak mau
harus berhubungan dan berinteraksi dengan penduduk pribumi.
Hadirnya seorang nyai dapat membantunya untuk mengerti dan
menyelami kehidupan masyarakat serta alam pikiran bangsa Indonesia.
Seorang nyai merupakan kamus berjalan tentang budaya pribumi bagi
tuan Eropanya. Keuntungan lainnya adalah diperoleh pengetahuan
mengenai obat-obatan tradisional dari seorang nyai. Nyai dapat
membantu para tuan Eropa menghadapi ancaman serangan penyakit
tropis karena masih terbatasnya jumlah obat-obatan yang ada. Bahkan
saat menderita sakit ringan, orang Eropa umumnya akan lebih
mengggunakan obat-obatan tradional daripada berkonsultasi pada dokter yang mendalami ilmu kedokteran Barat. Ahli obat-obatan
tradisional dari tanaman atau akar alami, baik yang betul-betul ahli atau
hanya sekedar pengetahuan secara turun temurun, sebagian besar
adalah seorang perempuan.
Melalui para nyai, orang-orang Belanda atau Eropa mendapat
kesempatan untuk tetap bertahan di lingkungan yang baru.34 Melalui
bantuan para nyai itu pula tuan-tuan Eropa memperoleh pengertian
tentang kehidupan masyarakat serta alam pikiran bangsa Indonesia.
Selain itu kita perlu tahu bahwa nyai juga berperan sebagai agen
budaya. Nyai menjadi sebuah mata rantai antara dua kelompok
masyarakat di mana ia memindahkan pengetahuan kebudayaan secara
spesifik dan nilai-nilai serta perilaku atau tabiat dari satu kelompok
masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya,35
Terdapat satu kelebihan lain ketika seorang laki-laki Eropa memilih
hidup bersama seorang perempuan pribumi, hal ini merupakan kenyataan
pahit yang harus diterima oleh pemerintah Hindia Belanda yang melarang
adanya pernyaian. Perkawinan suami istri Belanda di Hindia ternyata
sering mandul, keguguran dan kematian anak-anak sering terjadi. Heren
XVII menambahkan “padahal sebaliknya yang kita jumpai manakala lakilaki kita mengawini perempuan pribumi lahirlah anak-anak yang kuat dan tegap serta panjang umur”. Angka kematian rata-rata para perempuan
Eropa di daerah Timur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kaum lakilaki Eropa.
D. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Praktik Pernyaian
Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, baik sejak bangsa Portugis,
Spanyol, Belanda, hingga Inggris tidak dapat dilepaskan dari munculnya nyai,
seorang perempuan pribumi yang hidup bersama lelaki Eropa dalam hubungan
pernyaian. Tumbuh kuatnya praktik pernyaian di Hindia Belanda bukan
berarti karena didukung oleh pemerintah maupun masyarakat. Justru
dikarenakan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada
waktu itu yang kemudian mempengaruhi pesatnya pertumbuhan pernyaian
hingga berabad-abad lamanya.
Peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah Hindia
Belanda pun sering berubah-berubah dan tidak konsisten. Ada masanya
praktik pernyaian benar-benar ditentang dengan keras, namun dengan alasan
menguntungkan pihak kolonial praktik pernyaian tidak dilarang atau bahkan
dianjurkan. Kebijakan yang berubah-ubah itu tentunya dilihat dari sudut
pandang keuntungan yang diperoleh oleh pihak kolonial.
Telah dijelaskan bahwa fenomena pernyaian muncul jauh sebelum VOC
didirikan, yaitu pada masa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke
Nusantara pada abad ke 16. Dapat dikatakan bahwa pernyaian adalah wajah
utama dalam masyarakat kolonial Portugis. Tetapi mutlak hal itu harus terjadi,
karena jumlah perempuan Portugis yang dikirim ke Timur sangatlah sedikit. Pemerintah Portugis justru menggalakkan perkawinan serdadu-serdadu
dengan perempuan-perempuan setempat sejak sekitar tahun 1505 sampai 1515
semasa Rajamuda Dom Fransisco de Almeida dan penggantinya, Alfonso de
Albuquerque.36
1. Kebijakan Jan Pieterszoon Coen terhadap Praktik Pergundikan
Pernyaian semacam ini masih bertahan hingga datangnya
bangsa Belanda ke Nusantara.
Jan Pieterszoon Coen adalah pendiri Batavia setelah pada tahun 1619
Djakarta berhasil diduduki oleh VOC. Coen adalah Gubernur Jenderal
VOC pada saat itu. Jabatan Gubernur Jenderal adalah sorang pemimpin
umum yang berkuasa dan mengurus semua kepentingan VOC di Asia.
Setelah mendirikan Batavia, Coen berusaha untuk membangun koloni
kulit-kulit putih di tanah jajahan. Berbeda dengan usaha pemerintah
Portugis yang menggalakkan perkawinan para serdadu dengan perempuanperempuan pribumi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Asia dan
membangun sebuah koloni di tanah jajahan, Coen tidak terlalu berharap
dari serdadu-serdadu. Bagi Coen, para serdadu bukanlah jenis yang tepat
untuk pembangunan sebuah koloni.
Maraknya pernyaian pada masa itu yang terjadi di kalangan lelaki
Belanda atau Eropa dengan perempuan pribumi sangat ditentang dan
dibenci oleh Coen karena dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas.
Coen memang seorang yang terkenal sangat keras terhadap pelanggaran seksual.37 Kekerasannya ini terlihat pada sebuah kasus skandal seks di
kalangan kastil Batavia, yakni hubungan gelap antara seorang serdadu
bawahan berbangsa Belanda dengan Sara Specx, putri Jacques Specx38
dari selir Jepangnya. Ketika skandal tersebut terbongkar, serdadu yang
melakukannya dihukum mati, sedangkan Sara Specx dihukum cambuk di
muka umum.
Coen menganggap bahwa perkawinan campuran yang terjadi antara
orang Belanda atau Eropa dengan orang pribumi bukanlah jalan yang tepat
untuk membangun sebuah koloni kulit putih di tanah jajahan. Dalam
beberapa suratnya yang ditulis untuk dewan pengurus di Amsterdam, Coen
menguraikan gagasannya mengenai bagaimana mengisi kota Batavia.
Ditegaskannya bahwa ia terpaksa mengambil langkah sementara dan
membeli perempuan-perempuan budak dari pantai India, karena pengurus
agaknya tak berminat untuk membangun sebuah koloni.
Menurut Coen, perempuan adalah prasyarat dalam berdagang, “dasar
negara di Hindia. Jika perempuan tersedia pasar-pasar perdagangan Hindia
adalah milik Anda”, tulisnya kepada Heren XVII (Opkomst IVxxxiv).41Maka, Coen meminta kiriman anak-anak gadis serta mengusulkan agar
banyak keluarga Belanda dari kalangan yang baik-baik untuk beremigrasi
ke Batavia. Bersama keluarga dan anak-anak mereka ini disertakan pula
sekitar empat sampai lima ratus anak laki-laki dan perempuan berusia 10
sampai 12 tahun, yang diambil dari semua rumah-rumah yatim-piatu di
Verenigde Provincien, dengan perbandingan antara anak laki-laki dan
perempuan diusulkannya 2:1.42
Coen memahami bahwa para laki-laki dalam wilayah jajahan harus
memperoleh alternatif mendapatkan pasangan hidup selain dengan
melakukan praktik pergundikan. Coen menganggap pernyaian sebagai
penyebab dari timbulnya kasus pengguguran kandungan, pembunuhan
bayi, dan terkadang aksi peracunan terhadap si tuan Eropa yang dilakukan
Para yatim-piatu Belanda tersebut memenuhi kriteria Coen untuk
membangun masa depan koloni. Coen mendukung terciptanya wilayah
pendudukan permanen bagi imigran dari Belanda. Bersama para pedagang
dan serdadu, para imigran dapat membentuk kelompok masyarakat yang
akan memberi tempat bagi para petani, pengrajin, agamawan dan guru.
Para yatim-piatu, baik laki-laki maupun perempuan, menurut Coen sangat
cocok untuk menjadi penduduk baru di daerah koloni karena tidak
mempunyai keluarga maupun ikatan dengan tanah air mereka. Karena itu,
akan lebih mudah bagi mereka untuk mengikat diri dengan tempat tinggal
di dalam koloni.oleh gundik yang cemburu. Ia pun meminta calon-calon pengantin
perempuan kulit putih kepada Heren van de Compagnie.
Tahun 1620, barulah Hereen XVII mengabulkan permintaan Coen
ditandai dengan adanya pengiriman sejumlah perempuan Eropa melalui
kapal-kapal laut ke wilayah Timur.
Calon-calon pengantin perempuan kulit yang diminta oleh Coen
haruslah para gadis atau perempuan muda yang berkelakuan baik dan
diutamakan yang pernah dididik dengan ketat dip anti asuhan. Sebelumnya
sudah banyak wanita lajang dibawa ke Hindia Belanda. Mereka
diwajibkan untuk menikah dengan para pegawai VOC di Timur dan
sebagai gantinya mereka mendapat pelayaran gratis beserta mas kawin.
Gagasan tersebut pada awalnya tidak mendapat tanggapan dari Hereen
XVII sehingga Coen harus merintis sendiri usahanya dengan jalan
membeli perempuan-perempuan budak dari pantai India.
Anak-anak perempuan ini
ditempatkan pada keluarga-keluarga, atau di sekolah-sekolah khusus yang
dibiayai kompeni dan di sanalah mereka diasuh, dirawat, dididik, dan
diajar sampai menjadi akil balig dan dapat dikawinkan dengan calon suami
yang baik, agar dari perkawinan mereka itu bisa diturunkan keluargakeluarga yang terhormat. Gagasan pokok rencana ini ialah agar semua
sifat-sifat baik keluarga Belanda dan kaum wanita Belanda khususnya, misalnya kesopanan, kebersihan dan kesalihan. Usaha ini dilakukan agar
bisa mendesak istri-istri dari keturunan Asia atau Indo yang sudah di sini.
Permintaan dan peraturan-peraturan oleh Coen ternyata tidak terlalu
efektif. Jumlah pergundikan di wilayah pendudukan tidak berkurang
secara signifikan. Maka Coen mengeluarkan larangan bagi kaum lelaki
Belanda atau Eropa untuk menikahi kaum perempuan pribumi seperti yang
tercantum pada Regering bij Plakaat pada tahun 1625.
Sesudah masa Gubernur Jenderal Coen, sanksi terhadap hubungan di
luar perkawinan yang sah pun sangat longgar.
Larangan Coen
ternyata tidak dapat menghapus pergundikan di Hindia Belanda,
kebutuhan biologis telah mengalahkan kebijakan pemerintah. Pergundikan
baru benar-benar hilang berabad-abad setelah kepemimpinan Coen, yaitu
seiring dengan perginya bangsa Eropa dari Indonesia.
2. Peraturan Kolonial tentang Perkawinan Campuran
Ketika masa kompeni
berganti dengan masa pemerintah Hindia Belanda, pernyaian semakin
meningkat. Kedatangan laki-laki Eropa dalam jumlah besar telah
memperpanjang sejarah pernyaian di Hindia Belanda.
Peraturan perkawinan campuran di Hindia Belanda diatur dalam
Staatsblad 1898 No. 159. Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 No 23, S
1898/158. Peraturan tersebut memberikan definisi sebagai berikut;
perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang dibawah hukum yang berlainan yang ada di Indonesia. Hukum yang
berlainan ini antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan,
kependudukan dalam berbagai wilayah, golongan rakyat, tempat
kediaman, atau agama. Maka perkawinan campuran dibedakan menjadi
beberapa jenis, yaitu perkawinan campuran internasional, perkawinan
campuran antar-regio, perkawinan campuran antar-tempat, perkawinan
campuran antargolongan, dan perkawinan campuran antar-agama.
Praktik pernyaian yang terjadi antara laki-laki Eropa dengan seorang
perempuan pribumi tentu adalah sebuah perkawinan campuran. Karena
keduanya dipisahkan tidak hanya karena perbedaan ras dan
kewarganegaraan saja, tetapi golongan dan agama yang berbeda. Hukum
kolonial tentang perkawinan campuran ini merupakan salah satu peraturan
yang dikeluarkan untuk menanggapi banyaknya perkawinan laki-laki
Eropa yang ada di Hindia Belanda dengan perempuan pribumi, baik itu
yang dimulai dengan hubungan pernyaian atau pun tidak.
Penulis akan hanya membahas lebih lanjut tentang perkawinan
campuran antaragama, perkawinan campuran antargolongan, dan
perkawinan antara orang-orang yang berkewarganegaraan berbeda. Hal ini
dikarenakan mengingat bahwa bagi Indonesia sebagian besar terjadi
hubungan semacam ini.
1) Perkawinan Campuran antartempat (interlocaal)
Perkawinan campuran antartempat dimaksudkan terutama
perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku bangsa atau daerah yang berlainan dan hidup dalam berbagai
lingkungan hukum. Misalnya perkawinan antara orang Batak dengan
perempuan Sunda, seorang Jawa dengan wanita Lampung, dan
sebagainya.
2) Perkawinan Campuran Antaragama (interreligieus)
Mengenai perkawinan antara mereka dari satu golongan rakyat
tetapi berlainan agama, termasuk istilah perkawinan campuran dari
GHR48
Agama dipakai untuk melindungi golongan Belanda. Seorang
Kristen tidak dapat menikah dengan seorang bukan Kisten. Karena tak
sesuai dengan keadaan zaman, pendirian ini dilepaskan dengan
diterimanya pasal 15 Ov
. Dalam zaman kompeni hingga tahun 1848, keagamaan
dipergunakan sebagai pedoman dalam hal-hal perkawinan campuran.
Sesuai dengan struktur masyarakat yang terdapat pada waktu itu,
agama yang dianut oleh penguasa adalah agama Nasrani, yang
kemudian dijadikan pegangan.
Bahwa perbedaan agama tak
dapat dipergunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan
campuran. Sumber lain dari perkawinan campuran antaragama adalah
Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani Djawa, Minahasa, dan
Amboina, S. 1933/74 (HOCI). Bahwa GHR berlaku pula untuk perkawinan orang-orang Kristen dengan bukan Kristen segolongan
rakyat Indonesia.
Agama Nasrani dapat dianggap sebagai agama yang dianut oleh
kasta tertinggi dalam masyarakat Hindia Belanda sebelum perang.
Agama Nasrani dapat menggantikan status keturunan, orang golongan
rendahan dapat beralih ke pihak atasan dengan jalan memeluk agama
Kristen. Orang Indonesia Kristen seolah-olah berdiri pada perbatasan
antara golongan. Jarak pemisah antara orang Eropa dan Indonesia
Nasrani tidak begitu jauh. Posisi agama di sini dianggap sesuatu yang
penting untuk menentukan status sosial bagi masyarakat Eropa.
Seorang pribumi Kristen akan lebih mendapatkan posisi di mata
masyarakat Eropa, begitu pula dalam hal perkawinan. Praktik
pergundikan menjadi semakin berkembang juga karena larangan
menikahi perempuan pribumi non-Kristen. Karena dipersulit untuk
melaksanakan sebuah perkawinan, seorang laki-laki Eropa Kristen dan
seorang perempuan pribumi Muslim memilih untuk hanya berada pada
hubungan pergundikan.
3) Perkawinan Campuran Antargolongan (intergentiel)
Antargolongan diartikan dalam antar kasta, mengingat masyarakat
kolonial adalah masyarakat kasta. Istilah kasta dalam ilmu sosiologi
dipergunakan untuk menunjukkan adanya bendungan-bendungan yang
hamper tak dapat ditembus dan menghalang-halangi kenaikan sosial
dari seseorang. Bendungan yang dimaksudkan ialah color line, ciri universal pertama dari kolonialisme. Tembok ini adalah alas dari
segenap masyarakat kolonial. Penduduk asing yang menjajah terpisah
dari rakyat asli oleh tembok sosial yang tebal serta tinggi, yang hampir
tidak dapat dilewati.
Akibat dari adanya tembok-tembok pemisah ini, masyarakat
kolonial menyolok mata karena hanya sedikit hubungan sosial (sosial
contact) antara kasta yang dijajah dengan kasta penjajah. Dalam
pergaulan sehari-hari, di jalan-jalan, perkumpulan dan tempat-tempat
bertamasya nampak dengan tegas, distansi antara golongan pribumi
dan bangsa kulit putih. Sifat ini adalah suatu corak pula dari
masyarakat kolonial. Corak-corak ini dapat dikatakan ada pada tiaptiap masyarakat jajahan, meskipun dengan berbagai variasi. Hal
tersebut juga terdapat dalam masyarakat Hindia Belanda, khususnya
dalam abad ke-19.
Di Hindia Belanda pada zaman itu nampak tiga kasta yang hidup
agak terpisah satu sama lain, yaitu kasta Eropa, kasta Timur Asing, dan
kasta Inlanders (pribumi). Kasta Eropa diliputi dengan perlindungan,
sistem hormat, kemewahan yang diperlihatkan, dengan banyak emas
dan bordiran-bordiran, patung-patung, dan tanda-tanda kehormatan,
bahasa Belanda yang hanya boleh dipergunakan oleh orang Belanda,
pakaian dan kelakuan yang tidak dapat dipergunakan oleh kasta-kasta
lain. Kasta Eropa juga identik dengan perkumpulan-perkumpulan
eksklusif, tempat-tempat umum seperti penginapan-penginapan, dan pemandian-pemandian yang hanya menerima orang-orang Eropa,
penghargaan yang berlebihan.
Cukup jelas bahwa dalam suasana demikian dengan batas-batas
ras yang begitu kokoh dan kaku serta sedikitnya kontak sosial dari
individu kasta-kasta yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi
karena dianggap menyalahi hubungan antar kasta, maka perkawinan
campuran secara terang-terangan tidak banyak terjadi. Seorang Eropa
yang mengadakan perkawinan campuran tak dipandang lebih lama
oleh golongannya. Jika seorang Eropa hendak mengadakan hubungan
tetap dengan seorang perempuan Indonesia, ia tidak mengawininya,
melainkan diambilnya sebagai nyai. Baru jika ia mengundurkan diri
dari pergaulan masyarakat, dalam kepentingan anaknya dan supaya
memperoleh pensiun janda, seorang Eropa tersebut berpikir untuk
mengesahkan pergaulan campuran itu di hadapan umum.
Hal ini terjadi karena adanya keberatan-keberatan sosial yang
nyata di kalangan kasta Eropa jika ada seorang dari mereka berbaur
apalagi melakukan perkawinan dengan kasta yang paling rendah,
pribumi. Keberatan-keberatan tersebut dapat berupa resiko pemecatan
dari jabatan-jabatan tinggi, misalnya terdapat seorang dokter militer
pandai berpangkat kolonel, karena kawin dengan “ibu dari anakanaknya”50
50 Istilah “ibu dari anak-anaknya” digunakan untuk menyebutkan
seorang nyai, bahwa ia bukan isteri yang sah bagi Tuan Eropa-nya tetapi seorang
nyai melahirkan anak-anak dari Tuan Eropanya tersebut.
telah dipecat dari kedudukannya. Seorang residen yang
hilang pamornya karena “ibu dari anak-anaknya” ini bertindak terangterangan sebagai isterinya pada resepsi-resepsi dan pertemuanpertemuan resmi hingga timbul ketegangan diantara isteri-isteri Eropa
dari pejabat-pejabat pegawai negeri setempat.
Hanya lapisan-lapisan bawah dari kasta Eropa yang
memberanikan diri untuk menikah dengan “ibu dari anak-anaknya”,
mengingat tindakan ini seolah-olah merupakan penumpasan diri bagi
kehidupan mereka. Perkawinan ini diatur dalam KB tanggal 29
Desember 1896 (S. 1896-158) yang telah beberapa kali diubah. Pasal 2
KB tersebut menentukan bahwa seorang perempuan yang
melangsungkan perkawinan campuran sejak saat perkawinannya itu
mengikuti status suaminya, jadi seorang perempuan bukan Eropa yang
kawin dengan seorang dari golongan Eropa, selama dalam
perkawinannya tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya,
baik dalam hukum publik maupun dalam hukum sipil/perdata.51
Sedangkan perkawinan campuran antara perempuan-perempuan
Eropa dengan lelaki bukan Eropa lebih jarang terjadi. Budaya
patrilineal yang kuat di Hindia Belanda memaksa seorang perempuan
Hal
inilah yang dianggap perkawinan campuran dengan seorang
perempuan pribumi dianggap akan mengotori ras totok yang sangat
menjunjung tinggi prinsip rasial mereka.
Eropa yang harus ikut dalam kasta Inlander ketika ia berani melakukan
perkawinan campuran dengan seorang lelaki Inlander. Bahkan
perubahan status ini tetap berlaku setelah perkawinan itu terputus,
apabila ia dalam waktu satu tahun setelah perceraian itu tidak
menyampaikan pernyataan kepada Kepala Pemerintah setempat
dimana ia bertempat tinggal, bahwa ia ingin kembali ke status
semula.Menjelang akhir abad ke-18, VOC mengalami masa-masa
kemunduran. Kemunduran VOC diakibatkan pelbagai permasalahan
yang terdapat pada VOC sebagai sebuah perusahaan dagang. Salah satupermasalahan serius yang dialami oleh VOC ialah maraknya praktik
korupsi di kalangan pegawainya. Praktik korupsi ini terjadi akibat dari
rendahnya upah yang diterima oleh para pegawai VOC. Praktik korupsi
yang dilakukan oleh para pegawai VOC berdampak pada menurunnya
pemasukkan kas perusahaan dan sangat merugikan negeri Belanda.
Akibat praktik korupsi yang parah dan telah menggerogoti VOC maka,
pemerintah Belanda pada akhirnya membubarkan VOC pada tanggal 31
Desember 1799. Dan sejak tanggal 1 Januari 1800 pemerintah kolonial
Belanda mengambil alih kekuasaan di Hinda Belanda dari VOC.
Bubarnya VOC menyisakkan pekerjaan rumah bagi pemerintah
kolonial Belanda. Salah satu pekerjaan rumah yang harus segera
diselesaikan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah mengisi kas negara
yang kosong. Namun pertama-tama pemeritah kolonial Belanda harus
berhadapan dengan sistem pemerintahan tradisional yang diterapkan
oleh para penguasa pribumi. Ketika VOC masih beriri sebagai sebuah
perusahaan dagang, VOC tidak melakukan intervensi secara penuh
terhadap kekuasaan yang dimiliki para penguasa pribumi. VOC hanya
berusaha untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari para
penguasa pribumi yang ada. Akan tetapi pemerintah kolonial Belanda
memiliki maksud lain, yaitu tidak hanya mengambil keuntungan secara
ekonomis dari para penguasa pribumi melainkan juga mencoba
menguasainya secara politis.
Pertama pemerintah kolonial Belanda mencoba berinteraksi dengan
rakyat, khususnya para petani. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan
hubungan dengan para petani secara langsung dan intens untuk
menjamin arus tanaman sekspor dalam jumlah yang dihendaki. Hal ini
dilakukan untuk memangkas pengeluaran dan menambah keuntungan
dari setiap komoditas yang mereka dapatkan dan jual, serta
meminimalisir keterlibatan penguasa pribumi. Gubernur Jenderal
pertama yang berkuasa setelah bubarnya VOC adalah Dirk van
Hogendorp (1799-1808). Sebagai seorang liberal Hogendorp menganggap
bahwa kondisi rakyat yang sulit diakibatkan oleh sistem feodal yang
mematikan potensi rakyat. Hodendorp mengusulkan agar kedudukan
bupati dan penguasa lokal diatur kembali, penguasaan tanah dicabut dan
dikembalikan pada rakyat untuk ditanami secara bebas (Kartodirdjo,
1991). Namun semasa pemerintahannya usulan tersebut belum
terlaksana. Para penguasa pribumi masih berkuasa secara penuh atas
tanah dan rakyatnya.
Hogendorp mengusulkan agar rakyat diberikan kebebasan untuk
memilih jenis tanaman dan bebas untuk menjualnya. Penyerahan wajib
kepada pemerintah dalam bentuk pajak yang berupa hasil bumi dan pajak
uang perkepala. Pemerintah berhadap dengan sistem ini rakyat menjadi
lebih giat dalam menanam, dan mampu menghasilkan berbagai komoditi
ekspor, seperti kopi, beras, lada, kapas, coklat, dll. Meskipun tidak
berjalan dengan baik akibat masih kuatnya sistem feodal di Jawa, sampai
berkuasanya Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811).
Di bawah pemerintahannya terjadi perombakan total dalam struktur
pemerintahan tradisional dan penguasaan atas tanah.
Gubernur Jenderal Daendels menekankan pentingnya sentralisasi
kekuasaan di bawah wewenang pemerintah pusat. Salah satu tindakan
yang paling fenomenal Daendels ialah mengatur hubungan antara
pemerintah kolonial dengan penguasa pribumi. Hubungan antara
pemerintah kolonial dengan penguasa pribumi yang semula bersifat
horizontal, berubah menjadi hubungan vertikal dengan Gubernur
Jenderal berkedudukan sebagai atasan dan penguasa pribumi sebagai
bawahan (baca: pegawai kolonial). Begitu juga pada penguasaan tanah,
tanah-tanah milik penguas lokal menjadi tanah milik negara. Akibat dari
kebijakan penguasaan tanah tersebut, maka runtuh lah sistem feodal.
Para penguasa pribumi yang sebelumnya berkuasa secara penuh atas
tanah, kemudian berubah menjadi pengurus tanah-tanah tersebut atas
nama pemerintah. Hal ini terjadi sampai kedatangan Inggris pada 1811.
Pada tahun 1881 hingga 1816 Hindia Belanda berada di bawah
pemerintahan Letnan Gubernur Stamford Raffles atas nama Kerajaan
Inggris. Raffles adalah tokoh yang dianggap liberal dan pada masa
kepemimpinannya sistem sewa tanah diperkenalkan di Jawa. Selain
sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles, dirinya juga
merombak sistem feodal di Jawa. Tanah-tanah yang sebelumnya
merupakan milik para penguasa feodal diambil alih oleh pemerintah dan
menjadi milik negara. Para penguasa feodal yang ada kemudian dijadikan
para pegawai pemerintah, yang berada di bawah kekuasaan Letnan
Gubernur. Pemerintahan Letnan Jenderal Raffles menjadi peletak dasar
dari sistem sewa tanah, yang kemudian digunakan oleh pemerintah
kolonial Belanda saat kembali berkuasa.
Pasca penguasaan Inggris di Hindia Belanda (1811-1816), pemikiran
politik di daerah jajahan mulai bergeser dari politik liberal ke pihak
konservatif (Kartodirdjo, 1991). Pada 1810-1830 sistem pajak tanah
diberlakukan dan sistem penyerahan wajib di jawa dihapuskan. Akan
tetapi di daerah Priangan dilaksanakan Preanger Stelsel berupa wajib
tanam kopi yang menjadi pilot project bagi pelaksanaan sistem tanam
paksa (culturrestelsel) yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Johannes
Van den Bosch pada 1830. Kebijakan tanam paksa (cultuurestelsel) ini
lah yang kemudian menjadi sumber kas negara Belanda selama kurang
lebih empat puluh tahun kemudian (1830-1870).
Sekilas tentang Kebijakan Tanam Paksa
Sistem tanam paksa atau cultuurstelsel digagas oleh Gubernur
Jenderal Johannes Van den Bosch pada tahun 1830. Tanam paksa
diberlakukan untuk menggantikan sistem sewa tanah atau landelijk
stelsel yang gagal diterapkan secara maksimal. Sistem sewa tanah yang
diterapkan dari masa Letnan Jenderal Stamford Raffles sampai masa
pemerintahan Komisaris Jenderal Van der Cappelen dan Du Buss gagal
mendorong para petani untuk meningkatkan produksi komoditi tanaman
ekspor.
Kebutuhan akan suatu kebijakan baru yang diharapkan dapat
dengan cepat mengisi kekosongan kas negeri Belanda memang sangat
mendesak. Keadaan perekonomian negeri Belanda saat itu memang
sedang kacau. Peperangan yang dilakukan sungguh menguras kas
negara. Pada saat itu negeri Belanda memang sedang menanggung
banyak hutang akibat dua peperangan yang dihadapi. Pertama perang di
Eropa melawan Belgia dan kedua perang di Hindia Belanda (baca: Pulau
Jawa) melawan Diponegoro.
Negeri Belanda membebankannya pada daerah jajahan mereka untuk
meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai dengan
kebijakan sebelumnya yaitu dengan menetapkan sistem sewa tanah. Akan
tetapi sistem ini gagal memberikan negeri Belanda pemasukan yang
cukup. Namun sistem sewa tanah ini kemudian memberikan pondasi
pada sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diterapkan kemudian.
Sistem sewa meninggalkan peraturan untuk setiap desa harus
menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor,
khususnya kopi, tebu, dan indigo. Hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut nantinya akan diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda.
Sedangkan untuk para penduduk yang tidak memiliki tanah, maka harus
bekerja 66 hari selama satu tahun.
Pada dasarnya, sistem tanam paksa atau cultuurstelsel merupakan
gabungan dari sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Rakyat
memiliki kewajiban untuk membayar pajak dari hasil tanaman mereka.
Sistem ini juga merupakan upaya untuk menghidupkan kembali
eksploitasi yang terjadi pada masa VOC, yaitu berupa penyerahan wajib
untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor. Perbedaannya adalah
sistem tanam paksa lebih terorganisir dan melibatkan unsur-unsur
pokok, seperti birokrasi pemerintahan kolonial, para kepala pribumi,
organisasi desa, tanah pertanian rakyat, tenaga kerja rakyat, dan juga
pengusaha.
Seperti yang tertera dalam Staatsblad tahun 1834 nomor 2 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan
sistem cultuurstelsel sebagai berikut :
1. Penduduk desa menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami
tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa
2. Tanah yang disediakan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah
pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman yang
ditentukan tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan yang
dibutuhkan untuk menanam padi dan komoditi pangan lainnya
4. Bagian yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari
pembayaran pajak tanah
5. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada Pemerintah Hindia
Belanda. Bila hasilnya melebihi pajak tanah yang harus dibayar
rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat
6. Kegagalan panen harus dibebankan kepada Pemerintah Hindia
Belanda, terutama bila kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian
penduduk
7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan
pengawasan kepala-kepala mereka, dan para pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi-segi teknis dan ketepatan
waktu dalam pembajakan tanah, panen, serta pengangkutan.
Penerapan Cultuurstelsel dan Penyelewengannya
Di wilayah Jawa, sistem tanam paksa atau tanam paksa ini
diterapkan di daerah-daerah Gubernemen, yaitu daerah yang langsung
dibawahi oleh pemerintahan administratif Hindia Belanda, dengan
pengecualian daerah Batavia, Buitenzorg, wilayah-wilayah particuliere
landerijen, dan juga wilayah vorstenlanden (Kartodirdjo, 1991). Wilayah
Batavia dan Buitenzorg tidak ditetapkan sebagai daerah penerapan tanam
paksa karena kedua daerah tersebut merupakan pusat pemerintahan.
Selain itu daerah-daerah yang termasuk wilayah pribadi atau particuliere
landerijen juga tidak dianggap sebagai wilayah penerapan tanam paksa.
Hal ini dikarenakan particuliere landerijen merupakan tanah yang
dikelola atau dimiliki oleh swasta, sehingga pemerintah kolonial Belanda
tidak bisa sembarangan dalam menetapkan kebijakan. Selain itu, tanam
paksa juga tidak diterapkan di wilayah milik suatu kerajaan atau
vorstenlanden, seperti di Yogyakarta dan Surakarta. Di wilayah
vorstenlanden tersebut yang berlaku adalah sistem sewa tanah atau
landelijk stelsel. Pemerintah kolonial Belanda berkuasa atas 18
karesidenan, diantaranya Karesidenan Banten, Priangan, Karawang,
Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya,
Pasuruan, Besuki, Kedu, Bagelen, Banyumas, Madiun, dan Kediri .
Pada pelaksanaan sistem tanam paksa, penduduk diminta untuk
menanam berbagai jenis tanaman komoditas dagang. Tanaman tersebut
dibagi menjadi dua skala, yaitu skala besar dan skala kecil. Tanaman
skala besar seperti seperti kopi, tebu, dan indigo. Kemudian untuk
tanaman berskala kecil, antara lain lada, tembakau, teh, dan kayu manis.
Jenis tanaman yang ditanam pada masing-masing daerah berbeda,
bergantung pada kondisi lahan dan kecocokan tanamannya. Tanaman
kopi misalnya, tanaman ini dapat di tanam di seluruh keresidenan. Akan
tetapi hasil tanaman kopi terbaik berasal dari empat keresidenan, yaitu
Keresidenan Priangan, Kedu, Pasuruan dan Besuki.
Tanaman jenis tebu hanya dapat ditanam di 13 karesidenan saja dan
karena tebu merupakan komoditi ekspor yang berpotensi mendatangkan
untung yang besar maka banyak pengusaha swasta mengadakan kontrak
dengan pemerintah untuk menanam dan membudidayakan tanaman
tebu. Akhirnya sejak tahun 1837 produksi gula dari perusahaan swasta
mencapai separuh dari produksi gula dari perusahaan pemerintah. Pada
sistem tanam paksa tugas petani tidak hanya sekedar menanam saja,
melainkan juga diharuskan memproses hasil panennya untuk diserahkan
kepada gudang-gudang milik pemerintah. Sebagai gantinya, para petani
akan menerima sejumlah uang pembayaran yang disebut plantloon, yang
nantinya uang plantloon tersebut digunakan untuk membayar tagihan
pajak tanah dari tanah yang mereka garap di desa mereka sesuai dengan
daerah-daerah yang telah ditetapkan. Meskipun petani menerima upah
dari hasil kerja kerasnya menanam dan menerima pembayaran ketika
menjual hasilnya ke pemerintah kolonial, akan tetapi uang tersebut tidak
pernah cukup untuk menghidup kehidupan mereka. Sistem tanam paksa
telah menciptakan lalu lintas uang yang mempercepat timbulnya ekonomi
uang di desa (Kartodirdjo, 1991).
Pemerintah kolonial Belanda akan memberikan bonus berupa
cultuur procenten, kepada para pejabatnya, baik pejabat Belanda
maupun pribumi apabila panen yang dihasilkan dapat memenuhi target
produksi yang ditetapkan oleh pemerintah, Kebijakan
ini yang kemudian menimbulkan jurang pemisah antara rakyat, yaitu
para petani dengan pejabat pribumi. Para penguasa pribumi dianggap
sebagai antek-antek pemerintah kolonial Belanda dan di satu sisi rakyat,
khususnya para petani tidak bisa berbuat apa-apa atas kondisi yang
berlangsung.
Pada pelaksanaanya, sistem tanam paksa tidak sesuai dengan
peraturan yang telah pemerintah kolonial tetapkan sebagai sebuah
peraturan dalam Staatsblad tahun 1834 nomor 22. Sistem tanam paksa
lebih menguntungkan pemerintah kolonial dan semata-mata sebagai
bentuk eksploitasi (O’Malley, 1988). Gubernur Jenderal Bosch
menghendaki adanya campur tangan orang Belanda dalam proses
produksi. Para petani dipaksa menanam tanaman komoditi yang telah
ditentukan oleh pemerintah di tanah-tanah milik mereka sendiri. Para
petani yang dalam teorinya diberikan kebebasan dalam menjual hasil
panen, justru diwajibkan menjualnya hanya kepada pemerintah.
Tanah-tanah pertanian yang seyogyanya tidak dikenakan tanam
paksa, justru dipaksa menjadi lahan-lahan tanam paksa. Para petani
kehilangan mata pencaharian dan penghasilan. Akibatnya mereka
bertransformasi menjadi para petani penggarap, yang ironisnya mereka
menggarap di atas tanah milik mereka sendiri. Pajak-pajak yang
diterapkan pemerintah bukan dalam bentuk uang melainkan dalam
bentuk tenaga atau in natura yang direpresentasikan dengan berbagai
macam kerja. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan sifat rumah tangga
desa yang ingin dipertahankan sebagai rumah tangga produksi dan
dicegah agar tidak menjalankan rumah tangga uang ,
Mengenai pengerahan kerja wajib, seperti yang tertera dalam
Staatsblad tahun 1834 nomor 22, pengerahan kerja wajib bertujuan
untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah dan harus
dilakukan selama 66 hari dalam satu tahun , Para
pekerja wajib ini terdiri dari mereka yang tidak memiliki tanah dan juga
orang-orang yang diserahkan untuk tanam paksa ,
Pengerahan kerja wajib ini terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama ialah
kerja wajib umum atau heerendiensten, kedua ialah kerja wajib pancen
atau pancen diensten, dan ketiga ialah kerja wajib garap penamaman atau
cultuurdiensten.
Kerja wajib umum atau heerendiensten merupakan kerja wajib
untuk kepentingan umum, seperti pembuatan atau perbaikan jalan,
pembuatan bangunan gedung perkantoran, penjagaan tawanan, dan
sebagainya. Kerja wajib pancen atau pancen disenten merupakan kerja
wajib untuk merawat lahan pertanian di tanah milik para kepala pribumi.
Sedangkan kerja wajib garap penanaman atau cultuurdiensten
merupakan pengerahan kerja paksa untuk pembukaan lahan
perkebunan, pembuatan dan perbaikan irigasi, kegiatan penanaman, pengangkutan hasil panen, atau pekerjaan lain di kebun-kebun milik
pemerintah.
Penyediaan tanah untuk digarap dibebankan kepada seluruh desa,
bukan kepada penduduk secara individu sebagai pemilik tanah.
Pemerintah kolonial Belanda beralasan hal tersebut untuk mempermudah
dalam menanganinya. Akibat dari hal tersebut maka terjadilah perluasan
tanah secara komunal (milik bersama), dan terjadi perubahan hubungan
sosia di pedesaan. Kemudian tanah yang semua hanya diwajibkan 1/5
bagian, lalu kemudian meluas menjadi 1/3 bagian, lalu ½ bagian, bahkan
menjadi seluruh tanah desa .
Penyelewengan yang terjadi selama puluhan tahun sejak
pelaksanaan sistem tanam paksa mengakibatkan kondisi yang buruk bagi
rakyat, khususnya para petani. Gelombang kelaparan akibat minimnya
lahan pertanian dan ekspolitasi tenaga kerja di beberapa daerah banyak
mengakibatkan kematian dan penderitaan. Di Belanda sendiri terjadi
gelombang kritik, khususnya dilakukan oleh golongan humanis dan
liberal untuk menghentikan praktik tanam paksa di Hindia Belanda.
Mulai tahun 1860, terjadi penghapusan sistem tanam paksa secara
bertahap. Beberapa tanaman komoditi dikeluarkan dari daftar tanam
paksa, seperti lada pada 1862, nila, teh dan kayu manis pada 1865, dan
tembakau pada 1866.
Pada 1870 sistem tanam paksa dihentikan sekaligus menandakan
kemenangan golongan liberal di Belanda. Sistem taman paksa yang
dianggap sentralistik dan merugikan pihak pengusaha swasta lalu
kemudian digantikan dengan sistem liberal. Hal ini tercermin dalam
undang-undang agraria kolonial, Agrarische Wet 1870 dan UU Gula 1870.
Keduanya mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sistem kolonial
Belanda, dan bagi rakyat Indonesia era liberal ekonomi ini hanya lah
peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pihak-pihak swasta.
Sekilas Mengenai Penerapan Cultuurstelsel Di Luar Jawa
Sebelum tanam paksa ditetapkan secara formal oleh pemerintah
Belanda, Maluku telah menganut sistem ini untuk tanaman cengkeh di
Kepulauan Ambon dan pala di Kepulauan Banda. Dimulai pada abad 16
ketika Belanda menawarkan bantuan untuk mengusir Portugis dari
Maluku. Rakyat Maluku akhirnya dapat terpengaruh dan mau menuruti
permintaan Belanda untuk tidak menjual rempah-rempahya kepada
bangsa lain. Setelah mendapat kepercayaan dari rakyat Maluku, pihak
Belanda menjadikan dirinya sentra monopoli dan mendirikan banteng di
Maluku. Kemudian setelah Portugis pergi, di Maluku terdapat dua
penguasa, yakni Inggris dan Belanda. Inggris berkuasa atas Banda,
sementara VOC berkuasa di Ambon, Saparua, dan sebagian Maluku
Tengah. VOC memperkuat pertahanan dan armadanya di Maluku Tengah
dan mengikat kontrak dengan penguasa-penguasa daerah agar dapat
memonopoli perdagangan rempah dengan mudah. Hal ini mengakibatkan
rakyat Maluku tidak bisa bebas menanam cengkih dan pala jika tidak ada
izin dari pihak Belanda. Jika peredaran cengkih dan pala terlampau
banyak di pasaran, penguasa tanah tersebut harus membakar tanamantanaman miliknya. Saat Inggris akhirnya bisa berkuasa di Maluku pasca
perang Eropa antara Inggris dan Prancis, peraturan semasa Belanda
banyak yang diubah. Rakyat diberi kebebasan untuk berniaga dan hak
ekstirpasi atau penghancuran pohon pala dan cengkih pada masa VOC
dihentikan. Pada tahun 1830 Belanda kembali datang dan menguasai
Maluku. Tanam paksa tidak diberlakukan lagi di Maluku pada tahun
1860.
Sama dengan Maluku, daerah Minahasa telah memberlakukan
sistem tanam paksa sejak tahun 1822 untuk tanaman kopi. Mulanya
Minahasa merupakan daerah pemasok beras bagi kepentingan niaga
VOC. Namun kewajiban memasok beras dihentikan pada tahun 1852.
Baru kemudian VOC mulai menerapkan cultuurstelsel tanaman kopi
didataran tinggi Tondano. Wilayah tersebut merupakan salah satu
wilayah di Minahasa yang padat penduduk sehingga memungkinkan
adanya tenaga kerja yang banyak untuk proses penanaman kopi hingga
pembangunan sarana prasarana untuk mendukung budidaya kopi.
Tanaman kopi kemudian tumbuh subur dan banyak ditanam di distrik
Romboken, kemudian meluas ke Tomohon, Kawaknokoan dan Sonder.
Pemerintah mengambil tanah-tanah kalekeran, yaitu tanah milik distrik
yang kosong dan tidak digarap penduduk karena kondisi tanah tersebut
kurang baik untuk perkenier atau persawahan. Pilihan VOC untuk
membuka tanah kalekeran sangat memberatkan penduduk, karena
letaknya jauh dari pemukiman warga dan upah yang tidak bisa
mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Rakyat dibayar 10 gulden
per pikol. Pada masa itu satu keluarga hanya bisa menghasilkan satu
pikul, belum lagi adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas
penimbang kopi. Ada pula biaya pengangkutan kopi ke gudang pemerinah
yang berada di wilayah pantai, sangat jauh dari tanah kalekeran dan
pemukiman. Pengangkutan komoditi dilkukan oleh pekerja dengan cara
dipikul. Tahun 1851, pemerintah mulai membuka gudang di daerah
pegunungan. Pengangkutan tetap dilakukan dengan cara diangkut oleh
pekerja upahan yang khusus untuk mengangkut. Mulai dibangun jalan
dan jembatan yang menghubungkan daerah pegunungan dengan daerah
pesisir. Pembangunan jalan dan jembatan ini melibatkan penduduk,
dipimpin oleh kepala walak. Pada proses pembangunan jalan dan
jembatan, lokasi pengerjaan jauh dari desa dan terdapat lokasi yang
sangat sulit dijangkau dan berbahaya. Para pekerja tidak dipilih khusus
menjadi pekerja proyek, melainkan mereka merupakan petani yang
memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sistem tanam
paksa di Minahasa resmi dihapuskan pada tahun 1899.
Sistem tanam paksa di Sumatera Barat dilaksanakan pada tahun
1847 dibawah pimpinan Andreas Victor Michiels yang merupakan seorang
Mayor Jenderal. Sebelum masa kolonial, kehidupan perekonomian di
wilayah dataran tinggi Minangkabau cenderung subsisten; mereka
bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok wilayah mereka sendiri.
Kebanyakan penduduknya ialah petani, lalu ada pula penenun, pandai
besi, dan pedagang. Ketika AV Michiels menerapkan sistem tanam paksa
kopi, ia mewajibkan setiap keluarga menanam sekurang-kurangnya 150
batang kopi. Per batangnya diharapkan menghasilkan 1,05 pikul setiap
tahunnya. Ada tiga jenis kebun kopi di Sumatera Barat, yaitu:
1. Kopi di pekarangan rumah rakyat atau dihutan dekat kampung
(hal ini karena kopi telah dikerjakan rakyat secara turun temurun).
2. Kebun kopi milik rakyat.
3. Kebun kopi yang luas dan teratur; yang pada akhirnya dikontrol
penuh oleh orang Belanda dan terletak jauh dari pemukiman
penduduk.
Andreas Victor Michiels juga membangun jalan yang
menghubungkan daerah pedalaman dengan pusat pengumpulan kopi. AV
Michiels juga mewajibkan “jual paksa” komoditi kopi pada pemerintah.
Setelah 3-4 tahun diterapkan tanam paksa kopi, hasil produksi kopi di
Sumatera Barat meningkat secara kuantitas. Pada tahun ke 5 sampai 20
kopi mencapai puncak produksinya dan menjadi salah satu produksi
unggulan Sumatera Barat. Namun AV Michiels melanggar isi Plakat
Panjang yang kelima, yaitu perjanjian bahwa Belanda tidak akan lagi
memungut pajak, sebagai gantinya masyarakat harus memperluas
penanaman kopi. Rakyat terpaksa berganti profesi secara cepat dari
petani menjadi pekerja kebun. Rakyat yang dahulu berkecukupan,
kemudian harus menggantungkan sumber pemasukkannya dari
penjualan kopi ke gudang Belanda dengan upah yang sangat minim dan
adanya pajak. Belum lagi adanya metode penanaman yang sering diganti
dan adanya upaya pemerasan mandor pada rakyat pekerja, salah satu
contoh adalah dengan memberi berbagai macam denda. Tahun 1908
tanam paksa di Sumatera Barat dihapus. Hal ini dikarenakan banyak
rakyat yang menderita karena beban pekerjaan yang berat dan tingginya
pajak. Hak atas kepemilikan tanah dan hak lainnya juga dirampas dan
diusik oleh pihak Belanda.
Dampak Penerapan Cultuurstelsel Bagi Kehidupan Rakyat Hindia
Belanda
Dampak dari pelaksanaan tanam paksa ini bermacam-macam, ada
dampak positif dan ada pula dampak negatif. Di satu sisi, tanam paksa
dianggap berhasil meningkatkan produksi tanaman ekspor dan
mendatangkan keuntungan besar sehingga hutang-hutang Belanda yang
saat itu sedemikian besarnya pada akhirnya dapat dilunasi. Selain itu,
rakyat mengenal jenis-jenis tanaman ekspor yang bernilai jual tinggi, rakyat mengenal teknologi baru yang digunakan dalam pertanian, dan
rakyat juga dapat mengenal sistem ekonomi uang dan kemudian
menerapkannya dalam kehidupan pedesaan. Namun di sisi lain, rakyat
menderita karena tidak diberi upah atau plantloon yang “janjinya” akan
dibayarkan dan secara fisik pekerjaan mereka terbilang berat. Selain itu,
juga terjadi peristiwa kelaparan di berbagai daerah seperti contohnya di
daerah Demak di tahun 1848 dan di daerah Grobogan pada tahun 1849 .
Banyaknya penderitaan yang dirasakan oleh rakyat akibat
penerapan tanam paksa membuat banyak kritik dan gerakan dilancarkan
untuk menghapus sistem tanam paksa, seperti contohnya kritik dalam
Max Havelaar (Multatuli), L. Vitalis, dan Baron van Hoevell. Seranganserangan dari orang-orang non-pemerintah juga mulai menggencar akibat
terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840-
an di Grobogan, Demak, dan Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke
permukaan dan dijadikan isu bahwa pemerintah telah melakukan
eksploitasi yang berlebihan terhadap bumiputera Jawa. Lalu muncullah
orang-orang humanis maupun praktisi liberal menyusun seranganserangan strategisnya. Dari bidang sastra muncul Multatuli (Eduard
Douwes Dekker), sementara di lapangan jurnalistik muncul E.S.W.
Roorda van Eysinga, dan di bidang politik dipimpin oleh Baron van
Hoevell. Namun tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya
terbatas pada penghapusan Tanam Paksa. Mereka mempunyai tujuan
lebih lanjut. Gerakan liberal di negeri Belanda dipelopori oleh para
pengusaha swasta. Oleh karena itu kebebasan yang mereka perjuangkan
terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda
berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan
dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki agar kegiatan ekonomi
ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bertindak sebagai
pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman
dan menjamin keamanan serta ketertiban warga negaranya dalam
mengelola sektor perkebunan.
Pada 1830, negeri Belanda mengalami krisis ekonomi akibat hutang
yang sangat besar. Oleh karena itu pemerintah Belanda membebankan
negeri jajahan untuk dengan segera melepaskannya dari hutang.
Dibutuhkan sebuah kebijakan yang praktis dan efisien dengan tujuan
mengumpulkan dana bagi negara. Pada masa itu terjadi pula pergeseran
pemikiran dari pemikiran liberal ke ara konservatif. Maka kebijakan baru
yang digunakan sebagai jalan keluar sebenarnya bukanlah sebuah
gagasan baru, melainkan bersumber pada kebijakan eksploitatif yang
pernah diterapkan di Hindia Belanda oleh VOC. Kebijakan tersebut ialah
kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel.
Kebijakan tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johanes Van
den Bosch, dan diterapkan sejak tahun 1830 sampai dengan 1870. Sistem
tanam paksa yang diusung oleh Van den Bosh memiliki tujuan utama,
yaitu meningkatkan produksi tanaman komoditi ekspor agar dapat
menyasai pasar dunia dan mendapatkan keuntungan sebanyakbanyaknya. Secara teori sistem tanam paksa tidak terlalu merugikan para
petani, akan tetapi pada praktiknya sistem tanam paksa justru menjadi
mimpi buruk bagi para petani di Hindia Belanda. Infiltrasi pemerintah
melalui para pegawai Belanda dan penggunaan penguasa pribumi sebagai
kaki-tangan merupakan salah satu sumber penyimpangan dalam praktik
tanam paksa.
Penderitaan rakyat yang hampir lima puluh tahun adalah efek dari
penyimpangan atas sistem tanam paksa. Tanam paksa yang berlangsung
selama hampir lima puluh tahun berdampak pada perkembangan sosial
dan ekonomi masyarakat di pedesan. Kelaparan yang berujung pada
kematian adalah konsekuensi yang harus rakyat terima akibat eksploitasi
lahan tanpa memandang apakah itu lahan pertanian atau bukan.
Eksploitasi terhadap tenaga kerja juga membuat rakyat menderita,
banyak dari mereka yang lari untuk menghindari kerja-kerja wajib yang
merupakan salah satu poin dalam sistem tanam paksa. Sistem tanam
paksa juga melahirkan ekonomi uang di pedesaan yang kemudian
menyingkirkan sistem ekonomi pertanian yang bersifat subsisten.
Dihapusnya sistem tanam paksa pada 1870 tidak serta-merta
membebaskan rakyat khususnya para petani dari penderitaan.
Berlakunya sistem liberal kemudian justru memperparah keadaan bagi
rakyat khususnya para petani.








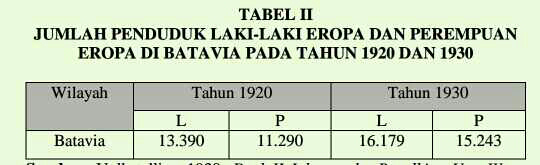




.jpg)









