Rabu, 12 Juli 2023
Home »
pendidikan jaman belanda
» pendidikan jaman belanda
pendidikan jaman belanda
By Lampux.blogspot.com Juli 12, 2023
pemerintah kolonial Belanda mulai
berkuasa di Hindia Belanda (Indonesia)
menggantikan VOC (Vereenigde
Oostindische Compagnie) yang bubar
pada tanggal 31 desember 1799 dan
seluruh aset miliknya dikuasai oleh
Negara Belanda. Bubarnya VOC
disebabkan kesalahan urus dan persoalan
korupsi para pejabatnya.2
Selanjutnya,
sebuah komisi Negara yang diketuai
Sebastian Cornelis Nederburg bergelar
komisaris jenderal dibebani tugas bidang
administrasi, hukum, dan pertahanan.
Barulah kemudian pada tahun 1808, si
tangan besi, Herman Willem Deandels
mengawali kekuasaannya sebagai
gubernur jenderal di Hindia Belanda. Di
antara kebijakannya adalah memangkas
kekuasaan penguasa-penguasa lokal. Ia
hanya tiga tahun berkuasa (1808-1811)
yang kemudian digantikan oleh Thomas
Stamford Raffles (1811-1816) yang
mewakili penguasa Inggris di tanah
bekas jajahan Belanda. Pada masanya
terjadi sedikit pembaharuan.
Kebijakan-kebijakan gebernur
jenderal berikutnya bukan memperingan
beban rakyat Hindia Belanda, bahkan
semakin mempersulit keadaan, misalnya
dengan penerapan cultuurstelsel.
Sistem
ini hanya menguntungkan pemerintah
kolonial dan sedikit menguntungkan
penguasa lokal akan tetapi sangat
memperberat kehidupan rakyat jajahan.
Berikutnya, pada era liberal hingga era
politik etis, rakyat tetap saja menderita
dan tidak banyak mengalami perubahan.
Kondisi-kondisi inilah yang membuat
rakyat semakin meningkatkan banyak
perlawanan bersenjatanya4
menyerang
penjajah Belanda.
Sebenarnya, perlawanan
abad XIX rakyat Banten merupakan
kelanjutan dari abad-abad sebelumnya.
Sebagaimana kita ketahui, Sultan
Ageng Tirtayasa (1651-1683 M)
gigih mempertahankan Kesultanan
Banten dari kejahatan adu domba yang
dilakukan oleh kaum kompeni antara
dia dan putra mahkota, Sultan Haji,
yang berujung tergerusnya kekusaan
kesultanan oleh kompeni.
Disamping itu, perlawanan
terhadap Belanda di abad XIX muncul
juga di berbagai daerah seperti Perang
Jawa di bawah pimpinan Pangeran
Diponegoro, Perang Padri di bawah
pimpinan Imam Bonjol yang bergejolak
di Sumatera Barat, Perang Batak dan
Perang Aceh di Sumatera Bagian Utara.5
Bahkan, perang yang tak kalah penting
adalah perlawanan rakyat Banten yang
tak henti-hentinya sejak awal abad ini sampai peristiwa Geger Cilegon 18886
yang dikomandoi oleh K.H. Wasyid.
Peristiwa-peristiwa perlawanan
rakyat Banten didukung, dipelopori
dan dipimpin oleh para Ulama, kaum
bangsawan, dan Jawara bahkan
para Srikandi7
Banten, di antaranya
adalah Nyai Gumpara, Tumenggung
Muhammad, Demang dari Menes,
Mas Jakaria, Ratu Bagus Ali, Pangeran
Radli, Mas Jebeng (putera Mas Jakaria),
Mas Anom, Mas Serdang, Mas Adong,
Mas Anjung (Puteri Mas Jakaria), Nyai
Permata (Ibu Nyai Gumpara), Raden
Yintan, Pangeran Lamir, Sarinam, Mas
Derik, H. Wakhia, Tubagus Ishak, Mas
Diad. Peristiwa perlawanan petani
Banten pada 1888 diinspirasi, dipimpin,
dan/atau dipelopori oleh K.H. Abdul
Karim, K.H. Tubagus Ismail, dan
K.H. Wasyid. Selain mereka, tokoh
yang juga berperan dalam perlawanan
rakyat Banten adalah Haji Singadeli,
Haji Asnawi, Haji Abu Bakar, dan Haji
Marjuki.8
Para pejuang dan pahlawan
Banten di atas memiliki semangat jihad yang kuat yang didasarkan
pada keyakinan keagamaan bahwa
kaum penjajah adalah orang kafir
yang menzhalimi kaum Muslimin
sehingga rakyat Banten wajib untuk
memeranginya. Demikian yang dapat
kita telusuri dari motivasi dan pendorong
mereka untuk berperang; artinya
hanya ada dua kata kunci bagi mereka,
yaitu Jihad dan Perang. Hal demikian
yang menjadikan K.H. Wasyid rela
mengorbankan jiwa dan raganya demi
mempertahankan harkat dan martabat
rakyat Banten yang memang ia buktikan
dengan wafatnya beliau di medan perang
sebagai syahid dan pahlawan.
K.H. Wasyid memiliki semangat
perjuangan menegakkan kebenaran
Amar Ma’ruf Nahi Munkar sejak
usianya masih muda. Darah pejuang
yang dimiliki K.H. Wasyid diwariskan
dari ayahnya, Abbas, yang pada tahun
1850 bersama H. Wakhia melakukan
perlawanan bersenjata. Dalam
perjuangannya, ia memiliki keahlian
dan kemampuan strategis, misalnya
bagaimana ia melakukan komunikasikomunikasi politik dengan para
ulama, jawara, dan pejuang-pejuang
lainnya di Banten dan luar Banten
untuk terlibat dalam perang melawan
penjajah Belanda. K.H. Wasyid juga
dikenal sebagai seorang ulama yang
berdakwah dari satu tempat ke tempat
lainnya terutama mengajak umat
menjauhi perbuatan syirik. Akibat dari
sikap tegas menegakkan ajaran Islam
di tengah masyarakat ini, K.H. Wasyid
menghadapi meja pengadilan sebelum
peristiwa Geger Cilegon 1888.Sejak didirikan oleh Sunan
Gunung Jati, Banten sebagai sebuah
kesultanan sudah sangat menarik bagi
para pedagang untuk merapatkan
kapalnya di pelabuhan Banten, baik
yang berasal dari Eropa maupun Asia
termasuk Nusantara.9
Kemudian, pada
era sultan-sultan berikutnya; Sultan
Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana
Yusuf sampai Sultan Ageng Tirtayasa,
menurut Claude Guillot, Banten masih
menarik karena 1) sepenuhnya merdeka;
2) merupakan periode yang cemerlang,
khususnya tahun 1670 M; dan 3)
Sultan Ageng Tirtayasa masih berkuasa
penuh.
Sekalipun demikian, negara
satelitnya, Jayakarta sudah lebih dulu
jatuh ke tangan J.P. Coen pada 1619 dan
mengganti namanya menjadi Batavia.
Artinya, upaya VOC menggerogoti
kekuasaan kesultanan Banten sudah
dimulai, di antaranya dengan berupaya
mengurangi peran pelabuhan Banten.
Upaya-upaya VOC di Batavia
yang sudah dikuasainya menggembosi
peran pelabuhan Banten. Hal ini sangat
dirasakan oleh Abdul Fath (Sultan
Ageng Tirtayasa) yang mulai berkuasa
tahun 1651. VOC dianggap menghalangi
usaha Banten memajukan perdagangan.
Namun, beliau tetap dianggap berhasil
dalam bidang perdagangan dengan
adanya ekspor-impor antara Banten dan
Persia, Surat, Koromandel, Benggala,
dan Siam. Dia juga membangun irigasi
untuk pertanian dan persawahan.
Suasana damai dan tenteram berjalan
hinggga 1676.13 Lantas, Sultan Ageng
Tirtayasa mengangkat putranya Abdul
Kohar Nasar (Sultan Haji) menjadi
sultan muda yang ternyata tidak suka
keluarga kerajaan memusuhi kompeni.
Dapat diprediksi bahwa akan terjadi
pertentangan antara ayah dan anak.
Sultan Ageng ingin terus mengadakan
blokade terhadap VOC sementara Sultan
Haji ingin mengadakan hubungan baik.
Pasca perang Trunojoyo, tahun 1680
Belanda melakukan agitasi terhadap
Banten yang sudah dikuasai oleh
Sultan Haji. Namun, Sultan Ageng
Tirtayasa tidak mau kompromi dengan
kompeni. Pertikaian antara Sulan Ageng dan Sulan Haji membuat Belanda
mendukung salah satunya untuk dengan
mudah menguasai. Terjadi perlawanan
bersenjata Sultan Ageng Tirtayasa
bersama ulama dan rakyatnya terhadap
Kompeni, tapi berakibat jatuhnya
Banten ke tangan mereka di atas nama
Sultan Haji.
Pasca bangkrutnya VOC
(tahun 1799), kondisi sosial rakyat
Banten bukan bertambah baik, justru
sebaliknya, pemerintah kolonial
Belanda bertambah represif sehingga
menimbulkan perlawanan di berbagai
daerah di Indonesia, termasuk di Banten.
Berbagai sistem yang diciptakan
kaum kolonial tak satupun yang dapat
mensejahterakan rakyat; bahkan
dipaksakan penerapannya dengan
kekerasan. Pada saat Herman Willem
Deandels berkuasa, sepak terjangnya
sangat otoriter. Ia menambah serdadu
dari 200 menjadi 18.000 orang dalam
waktu singkat. Umumnya, serdadu
berasal dari anak-anak Manado, Madura
dan Jawa. Yang tidak mau menjadi
tentara ia hukum dengan berbagai bentuk
kekerasan. Untuk pakaian seragam
serdadu, dia paksa petani memintal
benang dan menenun kain. Semua
bidang kehidupan di berbagai daerah
dijamah Deandels, termasuk pengrajin
tembaga untuk membuat bedil. Pada
tahun 1808 Daendels membangun jalan
raya dari Anyer sampai ke Panarukan
dengan kerja paksa. Tidak sedikit rakyat
meregang nyawa dalam pembangunan
jalan ini karena kekurangan makan,
penyakit, dan sebagainya. Si tangan besi Daendels juga
memangkas kekuasaan para penguasa
lokal; raja-raja lokal diturunkan
jabatannya menjadi pegawai biasa,
ia hapus pula tanda kehormatannya.
Timbul perlawanan dari penguasapenguasa lokal khususnya di Banten.
Daendels marah besar, istana sultan
dihancurkan, Sultan ditangkap dan
dibuang ke Ambon.
Pada tahun 1811, Daendels
digantikan oleh Janssens. Akan tetapi,
karena Perancis-Belanda dikalahkan
Inggris maka pada tahun yang
sama Inggris mengangkat Thomas
Stamford Raffles berkuasa di daerah
jajahan Belanda hingga tahun 1816.
Pemerintahan Raffles disebut-sebut
sebagai pemerintahan tangan liberal
yang lebih lunak dibandingkan Daendels
dan melakukan berbagai pembaharuan.
Ia menghapus kebijakan-kebijakan
Deandels, misalnya dalam bidang
monopoli dagang, kerja rodi, sistem
hak pemerintah atas hasil bumi, tak ada
pemaksaan, yang paling terkenal dari
kebijakan Raffles adalah pelaksanaan
pajak tanah (land-rent).
Kemudian, penguasaan tanah
jajahan diserahkan kembali ke tangan
pemerintah Belanda, berbagai kebijakan
para gubernur jenderal di Hindia Belanda
kembali membuat rakyat menderita,
semisal penerapan sistem tanam paksa
(cultuurstelsel) yang digagas Gubernur
Jenderal Johannes Van den Bosch
pada tahun1830.17 Empat puluh tahun
lamanya sistem ini diterapkan dengan
berbagai dampak negatifnya bagi
rakyat Indonesia umumnya dan rakyat
Banten khususnya. Banyak penduduk
yang meninggalkan kampungnya
menghindari tanam paksa, lain
halnya dengan rakyat Banten, mereka
melakukan perlawanan terhadap sistem
ini,18 dan kebijakan-kebijakan lainnya
yang tidak pro-rakyat.
Jika dirunut dari sejak sebelum
penerapan kultuurstelsel, hingga
penerapannya selama empat puluh
tahun, telah terjadi berbagai perlawanan
bersenjata dari rakyat Banten terhadap
kaum penjajah. Antara 1810 sampai
1840, terjadi sebelas kali perlawan
bersenjata rakyat Banten, di antaranya
perlawanan Nyai Gumpara pada 1818
untuk mengembalikan kesultanan
Banten dan penyerangan ke Anyer
dengan kekuatan 500 orang pada 1822.
Pada akhir tahun 1825 Tumenggung
Muhammad Demang dari Menes
dengan dukungan para kiyai dan tokoh
agama serta para santrinya memimpin
perlawanan bersenjata menentang
pemungutan pajak. Letnan de Quay
mematahkan perlawanan ini yang
membuat Tumenggung Muhammad
mengundurkan diri melintasi puncak
gunung Pulosari melalui perbatasan
Pandeglang. Dua tahun kemudian
muncul lagi perlawaanan bersenjata
dari Mas Jakaria. Pada 1811, ia pernah
menduduki Pandeglang yang kala itu
menjadi kota kraton, tetapi ia tertawan.
Namun pada tahun 1927, ia berhasil
melarikan diri. Banyak hadiah disediakan
bagi yang dapat menangkapnya,
tetapi tetap gagal bahkan pada tahun
ini ia kembali menyerbu Pandeglang
dan berhasil menewaskan anggotaanggota detasemen tentara Belanda.
Pasukan Belanda secara membabi buta
membakari rumah penduduk untuk
memaksa pengakuan penduduk dimana
keberadaan Mas Jakaria. Barulah
beberapa bulan kemudian ia berhasil
ditangkap dan dijatuhi hukuman mati
dengan memenggal lehernya dan
membakarnya.
Pada tahun-tahun 1831,
1833, 1836, dan 1839 terjadi banyak
perlawanan bersenjata. Pemimpinpemimpin yang lolos dari perlawanan
tahun 1936 adalah Ratu Bagus Ali
dikenal sebagai Kiyai Gede, Pangeran
Radli dan Mas Jebeng, putera Mas
Jakaria. Rakyat bersemangat lagi
melawan penjajah ketika ketiga putra
Mas Jakaria melarikan diri dari penjara
Banyuwangi; Mas Anom, Mas Serdang,
dan Mas Andong. Salah seorang wanita
yang memimpin perlawanan Nyai Mas
Anjung, puteri Mas Jakaria, ikut pula
Mas Ubid, kemenakan dan menantu
Mas Jakaria. Raden Yintan, Pangeran
Lamir, dan seorang wanita Sarinam
dapat ditambahkan sebagai pemimpin
perlawanan bersenjata.
Pada tanggal 13 Desember 1845,
para pejuang Banten merebut rumah
tuan tanah di Cikandi Udik dengan
membunuh tuan tanah Kamphuys,
istrinya dan lima anaknya. Peristiwa
ini disebut peritiwa Cikandi, semua
orang Eropa Cikandi menemui ajalnya.
Sebuah detasemen bejumlah 60 orang
berhasil melumpuhkan perlawanan
di Cikandi. Sebenarnya, peristiwa ini
dilakukan sebagai isyarat perlawanan
di seluruh Banten. Mereka bersekutu
dengan pemimpin kelompok BantenSelatan yang dipimpin oleh Nyai
Permana, ibu Nyai Gumpara, pemimpin
perlawan tahun 1836. Pada 24 Pebruari
1850, Raden Bagus Jayakarta, patih
Serang, mencetuskan perlawanan dan
menewaskan Demang Cilegon beserta
stafnya. Raden Bagus Jayakarta didukung
oleh pemuda-pemuda antara lain
Tubagus Iskak, Mas Derik, Haji Wakhia,
dan Penghulu Dempol. Di Lampung,
banyak orang Banten yang melarikan
diri dari Banten untuk menghindar dari
pengejaran kaum penjajah atau untuk
mengelak dari penindasan para pejabat.
Salah seorang daripadanya adalah orang
kaya H. Wakhia dari Budang Batu yang
dikejar-kejar polisi yang bersembunyi
di Lampung kemudian menuju Mekkah
untuk menunaikan ibadah haji. Pada
tahun 1847 ia kembali ke desanya.
Lagi-lagi ia tidak mau membayar
pajak. Ia dipanggil residen, tapi tidak
mengindahkannya. H. Wakhia turut
serta dalam merencanakan perlawanan
dan seruan H. Wakhia yang dibantu oleh
Penghulu Dempol untuk melancarkan
Perang Sabil disambut dengan semangat
dan menyala-nyala. H. Wakhia dan
penghulu Dempol mengambil posisi
di sebelah barat bukit-bukit Simari
Kangen, kelompok yang dipimpin Mas
Derik dan Nasid berada di pegunungan
sebelah timur Pulau Merak, sedangkan
Tubagus Ishak dan Mas Diad dan
pasukannya beroperasi di distrik Banten.
R.B. Jayakarta, pengambil inisiatif
berada di belakang layar. Lebih kurang
tiga bulan lamanya pasukan-pasukan
rakyat maju mundur diselingi seranganserangan sporadik terhadap kota-kota
kecil dan desa seperti Tanjak dan Anyer.
Dalam menghadapi pasukan kolonial
pada tanggal 3 Mei 1850 di Tegalpapak
mereka mengalami kekalahan dan
beberapa pemimpin mereka ditawan.
H. Wakhia dan Tubagus Ishak berhasil
meloloskan diri ke Lampung dan di
daerah ini ia kembali ikut perlawanan
terhadap penjajah Belanda yang
dilancarkan Raden Intan dan Pangeran
Singabranta. H. Wakhia akhirnya
ditangkap dan dihukum mati. Anak dan
isterinya menetap di desa asal H. Wakhia
yang kemudian dikenal dengan nama
Arjawinangun. Di tempat ini mereka
sangat dihormati.
Antara tahun 1851 sampai 1871
masih sering terjadi perlawan bersenjata,
seperti peristiwa Usup di tahun 1851,
peristiwa Pungut di tahun 1852,
kerusuhan di Kolelet di tahun 1866 dan
kasus Jayakusuma di tahun 1869.
Dari rentetan peristiwa
perlawanan bersenjata rakyat Banten
terhadap kolonial Belanda sejak awal
abad XIX, perlawanan bersenjata
yang sangat besar adalah yang terjadi
pada 9 Juli tahun 1888 yang dipimpin
oleh K.H. Wasyid. Tengku Ibrahim
Alfian merasa perlu menjelaskan ini
secara komprehensif mengingat begitu
dahsyatnya keadaan Banten baik
sebelum, saat terjadinya peristiwa, dan
sesudahnya
Dikutip dari Tengku Ibrahim
Alfian. “Semangat Keagamaan Rakyat
Banten dalam Mempertahankan Kemerdekaan” …. Alfian mengakui berhutang budi
pada Sartono Kartodirdjo yang telah
membuat kajian secara komprehensif
tentang keperkasaan Rakyat Banten
dan perlawanan mereka terhadap kaum
penjajah Belanda khususnya tentang
peristiwa Cilegon di tahun 1888 Disertasinya di Den Haag yang berjudul, The
Peasent’ Revolt of Banten in 1888: Its
Condition, Course and sequence.
20Tengku Ibrahim Alfian. “Semangat Keag- Tengku Ibrahim Alfian
menyatakan bahwa peristiwa
perlawanan bersenjata rakyat Banten
yang besar adalah yang terjadi
pada 9 Juli 1888 di Cilegon, suatu
perlawanan yang telah dipersiapkan
dan direncanakan serta mempunyai
ruang lingkup yang melampaui batasbatas kota Cilegon. Menurut Prof.
Dr. Sartono Kartodirdjo peristiwa ini
merupakan kulminasi gerakan-gerakan
perlawanan selama bertahun-tahun.
Tarekat telah dijadikan sarana untuk
menyebarkan informs-informasi rahasia
dan komunikasi-komunikasi antara
anggota dan memberikan peranan
penting meletuskan peristiwa ini.21
Dalam teori sejarah, setiap
peristiwa sejarah sedikitnya di dalamnya
terdapat Pionir (pencetus peristiwa),
Soil (tempat terjadinya peristiwa)
dan peristiwa itu sendiri. Peristiwa
perlawanan bersenjata Cilegon188822
pionir atau pencetus utamanya adalah
K.H. Wasyid.
1. Pendidikan Dan Semangat
Keagamaan
K.H. Wasyid adalah seorang
ulama dan pendakwah yang dalam ilmuagamanya, seorang alumnus pesantren
dan Timur Tengah. Seperti halnya
rakyat Banten yang memiliki semangat
keagamaan yang kuat dan mendalam,
demikian pula K.H. Wasyid, beliau
memiliki ilmu agama yang dalam berkat
ketekunan dan kegigihannya menuntut
ilmu di berbagai pesantren di Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Corak pendidikan pesantren masa itu
masih sangat berorientasi ilmu-ilmu
agama dan sangat tergantung pada
ustadz atau Kiyai. Mereka mempelajari
kitab-kitab yang berkaitan dengan
hukum Islam seperti Miftàh al-Jannah,
Shiràt, Sabîl al- Muhtadîn, Bidàyah,
Kitab Delapan dan Majmu’, Matan
Taqrib, Fathu al-Qarîb, Fathu alMu’în, Tahrir, Iqna’, Fathu al-Wahhab,
Mahally, dan sebaginya. Di antara
ilmu alat yang mereka pelajari, yakni
Sharaf, Kitab al-Jurmiyah, Mukhtashar,
Mutammimah, Nahwu. Mereka juga
mempelajari kitab-kitab Tafsir dan
Hadis, Balaghah, Tashawwuf, ihya
ulumuddin, al-Mantiq, Tauhid, Ushul alFiqh.23 Mata pelajaran yang diajarkan di
pesantren-pesantren pada abad ke XIX
sangat memengaruhi kepribadian para
santri. Tidak mengherankan jika pada
abad ini banyak peristiwa sejarah yang
dimobilisasi oleh alumnus pesantren
dan masyarakat pedesaan. Misalnya,
peristiwa perlawanan bersenjata yang
sangat terkenal, yakni “Geger Cilegon”
yang juga terkenal dengan sebutan
“Perang Wasyid”.24
Beranjak dewasa, disampingmenimba llmu di pesantren, KH. Wasyid
berangkat ke Mekkah berguru pada
Syekh Nawawi al-Bantani,25 sedang di
Banten dia berguru pada ulama-ulama
Banten, seperti Kiyai Wakhia. Dengan
ilmu yang dimilikinya, ia berdakwah
dari satu tempat ke tempat lainnya.
Dalam kesempatan dakwah ini K.H.
Wasyid menyampaikan ayat-ayat dan
hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad.
Dalam al-Qur’an. dua ungkapan
yang memotivasi setiap Muslim untuk
berjuang menegakkan kebenaran
dan keadilan serta menentang setiap
kezhaliman kaum penindas ialah
berperang di Jalan Allah dan berjihad
di jalan Allah. Khusus untuk istilah
perang dipakai kata qitàl yang terdapat
dalam surat al-Baqarah 190, 191, dan
193; surat al-Taubah ayat 111 dan surat
al-Hajj ayat 39.a. Al-Baqarah
190. Dan perangilah di jalan
Allah orang-orang yang memerangi
kamu, (tetapi) janganlah kamu
melampaui batas, karena sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas.
191. Dan bunuhlah mereka di
mana saja kamu jumpai mereka, dan
usirlah mereka dari tempat mereka
telah mengusir kamu (Mekah); dan
fitnah[117] itu lebih besar bahayanya
dari pembunuhan, dan janganlah kamu
memerangi mereka di Masjidil Haram,
kecuali jika mereka memerangi kamu
di tempat itu. Jika mereka memerangi
kamu (di tempat itu), maka bunuhlah
mereka. Demikanlah balasan bagi
orang-orang kafir.
192. Kemudian jika mereka
berhenti (dari memusuhi kamu), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.
b. At-Taubah
111. Sesungguhnya Allah telah
membeli dari orang-orang mukmin diri
dan harta mereka dengan memberikan
surga untuk mereka. Mereka berperang
pada jalan Allah; lalu mereka membunuh
atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji
yang benar dari Allah di dalam Taurat,
Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang
lebih menepati janjinya (selain) daripada
Allah? Maka bergembiralah dengan jual
beli yang telah kamu lakukan itu, dan
itulah kemenangan yang besar.
c. Al-Hajj
39. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena
sesungguhnya mereka telah dianiaya.
Dan sesungguhnya Allah, benar-benar
Maha Kuasa menolong mereka itu.
Secara etimologi Jihàd berasal
dari kata jahada yang berarti bersungguhsungguh mencurahkan segenap pikiran,
kekuatan dan kemampuan untuk
mencapai suatu tujuan, dapat juga berarti
perang dan kekuatan. Secara terminologi
(Ishtilàhan Syar’iyyan) “ jihad berarti
bersunggguh-sungguh mencurahkan
segenap pikiran dan kekuatan melawan
hawa nafsu, setan, kebatilan, dan
menghancurkan orang-orang yang
melawan agama Allah serta membangun
manusia yang berkemajuan.” Ayat-ayat
lain yang berkaitan dengan ini seperti di
bawah ini:
d. Al-Ankabût:
6. Dan barangsiapa yang
berjihad, maka sesungguhnya jihadnya
itu adalah untuk dirinya sendiri.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari
semesta alam.
69. Dan orang-orang yang
berjihad untuk (mencari keridhaan)
Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan
kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan
sesungguhnya Allah benar-benar beserta
orang-orang yang berbuat baik.
e. Al-Hajj
78. Dan berjihadlah kamu pada
jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan
Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk
kamu dalam agama suatu kesempitan.
(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.
Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian
orang-orang muslim dari dahulu[993],
dan (begitu pula) dalam (Al Quran)
ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas
dirimu dan supaya kamu semua menjadi
saksi atas segenap manusia, maka
dirikanlah sembahyang, tunaikanlah
zakat dan berpeganglah kamu pada
tali Allah. Dia adalah Pelindungmu,
maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan
sebaik- baik Penolong.
Bak gayung bersambut, seruanseruan K.H. Wasyid diamini oleh semua
elemen masyarakat mulai dari ulama,
kiyai, petani, santri, anak-anak muda,
pengikut tarekat, dan bahkan para jawara.
Pada abad XIX semangat keagamaan
mereka bertambah kuat. Seperti yang
disebutkan Sartono Kartodirdjo dalam
beberapa dasawarsa di akhir abad ke
XIX, tampak peningkatan kebangkitan
agama yang sangat luar biasa. Dimulai di
Timur Tengah dengan Pan-Islamismenya
yang sangat anti barat. Fanatisme dan
militanisme keagamaan muncul karena
benci orang kafir termasuk di Banten.
Gejala lain kebangkitan agama ini ialah
ramainya masjid dengan shalat jama’ah
dan pengajian-pengajian oleh anak-anak
muda Banten, bermunculan cabangcabang tarekat, jumlah orang naik haji
bertambah dan tinggal disana sambil
mencari ilmu.26 Tampaknya inilah yang
memudahkan K.H. Wasyid memobilisir
kekuatan dan massa untuk memerangi
penjajah.
bagi orang-orang yang diperangi, karena
sesungguhnya mereka telah dianiaya.
Dan sesungguhnya Allah, benar-benar
Maha Kuasa menolong mereka itu.
Secara etimologi Jihàd berasal
dari kata jahada yang berarti bersungguhsungguh mencurahkan segenap pikiran,
kekuatan dan kemampuan untuk
mencapai suatu tujuan, dapat juga berarti
perang dan kekuatan. Secara terminologi
(Ishtilàhan Syar’iyyan) “ jihad berarti
bersunggguh-sungguh mencurahkan
segenap pikiran dan kekuatan melawan
hawa nafsu, setan, kebatilan, dan
menghancurkan orang-orang yang
melawan agama Allah serta membangun
manusia yang berkemajuan.” Ayat-ayat
lain yang berkaitan dengan ini seperti di
bawah ini:
d. Al-Ankabût:
6. Dan barangsiapa yang
berjihad, maka sesungguhnya jihadnya
itu adalah untuk dirinya sendiri.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari
semesta alam.
69. Dan orang-orang yang
berjihad untuk (mencari keridhaan)
Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan
kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan
sesungguhnya Allah benar-benar beserta
orang-orang yang berbuat baik.
e. Al-Hajj
78. Dan berjihadlah kamu pada
jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya. Dia telah memilih kamu dan
Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk
kamu dalam agama suatu kesempitan.
(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim.
Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian
orang-orang muslim dari dahulu[993],
dan (begitu pula) dalam (Al Quran)
ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas
dirimu dan supaya kamu semua menjadi
saksi atas segenap manusia, maka
dirikanlah sembahyang, tunaikanlah
zakat dan berpeganglah kamu pada
tali Allah. Dia adalah Pelindungmu,
maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan
sebaik- baik Penolong.
Bak gayung bersambut, seruanseruan K.H. Wasyid diamini oleh semua
elemen masyarakat mulai dari ulama,
kiyai, petani, santri, anak-anak muda,
pengikut tarekat, dan bahkan para jawara.
Pada abad XIX semangat keagamaan
mereka bertambah kuat. Seperti yang
disebutkan Sartono Kartodirdjo dalam
beberapa dasawarsa di akhir abad ke
XIX, tampak peningkatan kebangkitan
agama yang sangat luar biasa. Dimulai di
Timur Tengah dengan Pan-Islamismenya
yang sangat anti barat. Fanatisme dan
militanisme keagamaan muncul karena
benci orang kafir termasuk di Banten.
Gejala lain kebangkitan agama ini ialah
ramainya masjid dengan shalat jama’ah
dan pengajian-pengajian oleh anak-anak
muda Banten, bermunculan cabangcabang tarekat, jumlah orang naik haji
bertambah dan tinggal disana sambil
mencari ilmu.26 Tampaknya inilah yang
memudahkan K.H. Wasyid memobilisir
kekuatan dan massa untuk memerangi
penjajah. Pertempuran Cilegon memang
diakui Snouck Hurgronye bahkan oleh
pemeintah Belanda sangat serius, dia
katakan, “Memang kekuasaan kita tidak
akan mudah dirubuhkan oleh suatu
gerakan fanatik. Tapi huru-hara setempat
di Cilegon tahun 1888 memang cukup
serius.” 27 Dua hal yang bisa kita telaah
dari peristiwa ini, yakni latar belakang
dan faktor-faktornya. Latar belakangnya
tentu jauh dari yang telah diuraikan di
atas, sedang faktor-faktornya dikatakan
sendiri oleh K.H. Wasyid yang pernah
disebut oleh saksi, Achmad; pertama,
dua pejabat pemerintah kolonial, yaitu
patih dan jaksa telah melarang umat
Islam melakukan ibadah di Masjid.
Kedua dinaikkannya pajak perahu dan
pajak-pajak usaha yang lain. Ketiga, para
pejabat sama sekali tidak menghiraukan
para kiyai, bahkan memusuhi Islam,
melarang shalat dengan suara keras
dan melarang membuat menara-menara
masjid tinggi, dan menyebar terlalu
banyak mata-mata untuk mencaricari kesalahan orang yang melanggar
peraturan.
Didorong latar belakang
dan faktor-faktor di atas, K.H.
Wasyid membuat perencanaan dan
mengorganisir serta memobilisir seluruh
elemen rakyat Banten untuk melakukan
perlawanan. Dari hasil penyelidikanterhadap para tawanan dapat diketahui
bahwa anggota-anggota perlawan
bersenjata K.H. Wasyid mengadakan
pertemuan di berbagai tempat dan
menggunakan tarekat sebagai tempat
berkumpul dan bersama-sama
melakukan sembahyang dan dzikir. K.H.
Wasyid dan para kiyai lainnya dapat
bertemu dalam kesempatan ini untuk
mengatur strategi dan taktik-taktik serta
kordinasi.
Dari setiap pertemuan, nampak
kepiawaian dan kemampuan K.H.
Wasyid mengumpulkan para kiyai,
ulama, tokoh-tokoh agama lainnya
bahkan para jawara. Dapat disebutkan
disini K.H. Abdul Karim, seorang
ulama besar dan dihormati rakyat
Banten, pemimpin agama dan guru
tarekat Qadariyah. K.H. Tubagus Ismail,
H. Abdul Gani, K.H. Usman, Haji
Nasiman, H. Sangadeli dari Kaloran, H.
Abu Bakar dari Pontang, H. Asnawi dari
Bendung Lempuyang, H. Muhammad
Asik dari Bandung. Masing-masing
mereka dan K.H. Wasyid menyampaikan
propaganda-propaganda yang berkaitan
dengan jihad dan perang sabil.
Perjuangan rakyat Banten
menuju kemerdekaan mendapat
kekuatan baru dengan pulangnya H.
Marjuki pada tahun 1887 dari Mekkah.
Ia mulai mengunjungi daerah-daerah di
Banten, Tengerang, Betawi, dan Bogor
untuk menyampaikan gagasan tentang
jihad. Tidak lama dikunjungi Haji
Marjuki, entusiasme rakyat bertambah
bergelora dan semangat keagamaan
rakyatpun semakin meningkat, sehingga
K.H. Wasyid menganggapnya sekutu
paling setia. Kunjungan H. Marjuki
ke para Kiyai tarekat Qadariyah
mendapat sambutan dan dari mereka keluar pernyataan mendukung gerakan
perlawanan yang dicanangkan K.H.
Wasyid yang sebelumnya sudah
melakukan apa yang dilakukan oleh
H. Marjuki. Akan tetapi H. Marjuki
kembali ke Mekkah sebelum terjadi
perang. Sekalipun demikian, K.H.
Wasyid taat asas mengabdikan dirinya
kepada perjuangan berjihad melawan
penjajah.
Disela-sela kesibukannya
berpropaganda, tiga bulan sebelum
pertempuran K.H. Wasyid memimpin
persiapan perang dengan mempergiat
latihan-latihan pencak silat,
pengumpulan dan pembuatan senjatasenjata, dan sembari membakar
semangat melalui khutbah-khutbahnya
untuk melaksanakan perang sabil.29
Berkat kepiawian K.H. Wasyid
mengorganisir dan memoblisasi rakyat,
gerakan kolektif ini diakui sangat
terorganisir dan memiliki perencanaan
yang matang. Tanda-tanda akan
dimulainya perang tampak pada tanggal
8 Juli 1888. Rombongan-rombongan
prajurit berpakaian putih-putih mulai
bergerak ke pos komando yang sudah
disiapkan di desa saneja di rumah
H. Ishak. Para pimpinan rombongan
bermusyawarah di pimpinan K.H.
Wasyid. Selaku pimpinan operasi,
K.H. Wasyid mulai mengatur strategi
penyerangan, ia bagi pasukan dalam
beberapa kelompok yang masing-masing
bertugas menyerang penjara, yang lain
membebaskan tahanan, menyerang
Kepatihan, menyerang rumah Asisten
Residen. Pada hari Senin, 9 Juli 1888
perang dimulai dan pada sore harinya
Cilegon dapat diduduki K.H.Wasyid
29Tengku Ibrahim Alfian. “Semangat Keagamaan Rakyat Banten dalam Mempertahankan
Kemerdekaan” …. Hlm. 9.
dan para pasukannya.
Di bawah komando Kapten
A.A. Veen huyzen, Belanda melakukan
operasi mematahkan perlawanan dan
melakukan pengejaran terhadap K.H.
Wasyid dan kawan-kawannya. Namun,
pertempuran terus berlangsung dan pada
tanggal 30 Juli 1888 K.H. Wasyid, K.H.
Tubagus Ismail, Haji Usman, dan Haji
Abdul Gani terbunuh sebagai syahid
dan pahlawan.30
Singkat cerita, dalam
pertempuran Cilegon 1888, di pihak
Belanda tewas 19 orang, yang luka 7
orang. Di pihak prajurit Banten syahid
30 orang, termasuk K.H. Wasyid, terluka
13 orang. 94 orang dari pihak K.H.
Wasyid dibuang ke berbagai daerah
di dalamnya 42 orang haji, dua orang
wanita Nyi Aminah dan Nyi Rainah dari
Arjawinangun, keduanya puteri K.H.
Wakhia.31
Dampak dari peristiwa Cilegon
1888 sangat dirasakan oleh para kiyai,
ulama, guru agama dan pengikut
organisasi tarekat. Oleh karena Belanda
meyakini bahwa peristiwa Cilegon 1888
penggerak utamanya adalah anggota
tarekat, maka diusulkan agar mereka
dibuang. Kenyataan lain dimana-mana
Belanda memburu guru agama, bahkan
ada bupati yang melarang pengajaran
kitab dan penyebaran tarekat. 32
Tengku Ibrahim Alfian bertanya
apakah pelajaran yang dapat ditarik dari
sejarah perjuangan rakyat Banten dalam
melawan penjajah di abad XIX?Historical Conciousness
(kesadaran sejarah) akan eksistensi
bangsa kita di masa lalu perlu kita
bangun. Hal ini sudah dimiliki oleh
para pemimpin agama dan kiyai oleh
karena memiliki pengetahuan yang
dalam tentang al-Qur’an dan hadis Nabi
hamammad Saw. yang tentunya wajib
kita ikuti sebagai seorang Muslim, serta
sanggup menggerakkan rakyat dengan
semangat yang tinggi melawan penjajah.
Kesadaran sejarah masa lalu
bangsa kita perlu dibarengi oleh sense
of responsibility (rasa tanggung jawab)
setiap generasi berikutnya untuk terus
mempertahankan eksistensi mereka
sebagai sebuah bangsa yang besar yang
sudah dibangun oleh para pendahulu
dengan mengorbankan jiwa dan raga
mereka sampai titik darah penghabisan.
Disamping tanggungjawab itu, perlu
pula kita merenungkan apa yang pernah
disampaikan oleh presiden pertama kita,
JASMERAH artinya jangan sekali-kali
melupakan sejarah, sebab sebagaimana
dikatakan oleh presiden kedua kita
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang
mengingat jasa para pahlawannya”.
Abul ‘Ala Maududi, seorang
ulama besar dasri India abad XX berkata
bahwa semua tindakan dilakukan demi
kehidupan umat manusia yang layak
secara kolektif dan yang fungsionarisnya
tidak ditunggangi kepentingan pribadi
di dunia ini. Kepentingan tunggalnya
hanyalah ridla Allah dalam Islam yang
diakui sebagai “amal fi sabilillah”.
Perjuangan untuk berbuat kebaikan
dalam masyarakat Islam dan melawan
kemungkaran adalah sebuah jihad.
Maududi mengemukakan bahwa
mengubah pendapat suatu masyarakat
serta memulai suatu revolusi mental
adalah salah satu bentuk jihad. Bukankah
hal ini yang telah dicontohkan oleh para
pejuang Banten?
Jihad fi sabilillah yang digalakkan
untuk menggelorakan semangat
berkorban guna mempertahankan
tanah air dari penjajah seperti yang
diperlihatkan oleh K.H. Wasyid dan
rakyat Banten dapat dijadikan pendorong
untuk membangun Banten khususnya
dan Indonesia pada umumnya.
PENDIDIKAN
Politik etis berakar pada orientasi kemanusiaan sekaligus
keuntungan ekonomi, yang dilatarbelakangi oleh kecaman terhadap
Pemerintah Belanda melalui kritik dalam novel Max Havelaar (1860).
Kebijakan politik etis dimulai tahun 1901 melalui pernyataan Ratu
Wilhelmina untuk meneliti kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda.
Menteri Urusan Daerah Jajahan yang kemudian menjadi Gubernur
Jenderal yaitu Alexander W. F. Idenburg melaksanakan politik etis
dimulai tahun 1902 dengan tiga prinsip utama yaitu pendidikan,
pengairan, dan perpindahan penduduk
Kajian mengenai politik etis banyak dilakukan oleh para sejarawan
maupun akademisi karena dianggap sebagai faktor pendorong sekaligus
pendukung pergerakan nasional Indonesia, khususnya karena aspek
pendidikan.
bahwa pendidikan dalam politik etis sebenarnya diberikan secara terbatas
dengan akses pendidikan yang tidak luas serta berorientasi kepentingan
ekonomi pemerintah kolonial. Meskipun demikian terbatas, pendidikan
menjadi faktor penting bagi runtuhnya dominasi kolonial
Keterbatasan pada penelitian politik etis dalam bidang pendidikan
adalah belum banyak dilakukan kajian mengenai pembelajaran sejarah
pada pendidikan Kolonial. Sebagai salah satu faktor penting dalam
kurikulum pendidikan Belanda, patut diduga pelajaran sejarah
meningkatkan kemampuan berpikir kritis elit bumiputera. Awalnya
pelajaran sejarah ditujukkan sebagai indoktrinasi serta mengajarkan agar
siswa bumiputera menerima kolonialisme Belanda, namun tujuan ini gagal. Oleh karena itu, kajian mengenai pelajaran sejarah yang diterapkan
serta kurikulum yang menyertainya penting untuk diteliti.
Pelajaran sejarah tidak hanya membicarakan mengenai peristiwaperistiwa masa lalu yang tidak berhenti pada hapalan tanggal dan tahun,
karena memiliki nurturant effect lain yaitu meningkatkan kemampuan
berpikir kritis-logis dan memberikan stimulus bagi pengembangan nilainilai implementatif untuk dipraktekkan dalam kehidupan kemanusiaan.
Nurturent effect tersebut tidak disadari oleh Pemerintah Kolonial Hindia
Belanda yang memandang pelajaran sejarah dari instructional effect sebagai
ajang untuk menyebarkan narasi mengenai legitimasi kolonialisasi dan
imperialisasi kepada para murid Hollanders maupun Inlanders.
Pembelajaran sejarah dapat menjadi penggerak bagi politik pemerintahan,
yang dapat mempengaruhi tujuan, posisi hingga materi pelajaran sejarah
agar sesuai dengan ideologi serta kepentingan politik penguasa
Pada awal abad XX, anak-anak bumiputera mulai diizinkan
menempuh pendidikan ‘modern’ Belanda melalui kebijakan politik etis
yang diterapkan di Hindia Belanda. Politik etis dilatarbelakangi oleh
pengaruh politik Mr. Van Deventer yang mengkritik pemerintah kolonial
untuk menaruh perhatian yang lebih luas terkait pendidikan dan
pengajaran bagi bumi-putera
Berdasarkan penelitian Maftuh, disebutkan bahwa kebijakan politik
pendidikan kolonial, mulai dari pendidikan rendah sampai tertinggi
tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang Indonesia,
melainkan tak lebih daripada sekedar memberi kesempatan kepada keluarga golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta
mempertahankan kelangsungan kolonialnya
Adapun faktor-faktor utama yang melatarbelakangi kebijakankebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda
dilaatarbelakangi oleh faktor politik, ekonomi, Kristenisasi, rasialisme,
situasi dan kondisi internal Belanda, serta kondisi umat Islam , Faktor politik, yakni suasana perpolitikan baik yang
terjadi di Parlemen Belanda maupun di Hindia Belanda. Faktor ekonomi,
yakni pendirian sekolah-sekolah selalu didorong pertimbangan untungrugi secara ekonomis. Faktor Kristenisasi, adalah upaya penyebaran
agama di Hindia Belanda. Faktor rasialisme yang berkaitan dengan
struktur sosial dalam kolonialisme yang meletakkan bangsa Belanda dan
kulit putih lainnya, sebagai kelas yang tertinggi. Faktor situasi dan kondisi
internal di Negeri Belanda yang memaksa Pemerintah Koloni. Faktor
kondisi umat Islam Indonesia, yaitu fenomena revival umat Islam yang
memicu pemerintah kolonial Belanda untuk menyainginya dengan
mendirikan sekolah-sekolah.
Pendidikan kolonial bagi bumi-putera memiliki struktur dan
tingkatan yang khas, disebut oleh Sri Soetjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo
sebagai “Pendidikan Dualisme di Hindia Belanda” yang berlangsung
pada tahun 1900 sampai 1942
Disebut dualisme karena bumiputera dapat memilih diantara dua yaitu
pertama pendidikan rendah yang khusus untuk bumi-putera, dan kedua
pendidikan yang menggunakan bahasa pengantar Belanda yang dimulai
dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi (universitas). Sebagai upaya menghadapi kritik, Pemerintah Hindia Belanda
akhirnya membolehkan anak-anak dari kalangan bumi-putera
diperbolehkan memasuki Sekolah Rendah Belanda, yang dapat
dilanjutkan ke Sekolah Dokter Jawa dan Sekolah Pamong Praja . Sekolah Kelas II diperbanyak, bahkan pada tahun
1903 diadakan “Sekolah Desa” yang lamanya tiga tahun dan hanya belajar
membaca, menulis, berhitung, bahasa daerah, dan menggambar.
Sekolah Desa yang digagas oleh Gubernur Jenderal van Heutz
dibiayai oleh desa dan pemerintah yang memberikan subsidi sangat
terbatas karena tujuannya hanya pemberantasan buta huruf yang
nyatanya berjalan secara lambat. Dirasakan pula bahwa pemerintah tidak
serius dalam menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat bumi-putera
karena dalam pendidikan rendah tidak diajarkan bahasa Belanda, ilmu
pengetahuan modern, dan sejarah
Pelajaran bahasa Belanda karena berbagai desakan akhirnya
dimasukkan dalam Sekolah Kelas I mulai dari kelas III sampai kelas VI
agar anak bumi-putera dapat mengikuti pelajaran yang lebih tinggi yang
didominasi dan diwajibkan penggunaan bahasa Belanda. Namun tetap
saja, Sekolah Kelas I yang memberikan pendidikan selama 6 tahun tidak
diberikan mata pelajaran sejarah Indonesia. Sifat pengajaran pada masa
Kolonial Hindia Belanda tidak berisi semangat kebangsaan atau tidak
berisi usaha-usaha untuk perkembangan kebudayaan kebangsaan,
adapun perubahan kurikulum pada 1914 pun hanya mendekatkan elit
lapisan atas bumi-putera kepada kebudayaan Belanda dan bukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan bangsa secara bebas dan merdeka
.Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki beberapa pandangan
mengenai pentingnya memahami dan menguasai kompetensi sejarah,
khususnya bagi para pendidik di berbagai tingkatan struktur dalam
sistem pendidikannya. Kewajiban menguasai kompetensi sejarah
diantaranya ditujukkan kepada guru atau pendidik, guru les serta kepala
sekolah. Dalam mengkaji bagian ini, peneliti bersumber pada buku
referensi pendidikan di Hindia Belanda karya D. Brakel yang diterbitkan
tahun 1914 berjudul Vraagbaak voor ouders (voogden) in Nederlandsch Indie ,
die hun kinderen (pupillen) niet naar Holland zenden.
Salah satu kompetensi wajib seorang pendidik atau guru
(Onderwijzer) adalah memiliki keakraban dengan peristiwa-peristiwa
sejarah Belanda dan Hindia Belanda . Seorang
pendidik atau guru pada masa kolonial, memiliki kewajiban untuk
memahami peristiwa-peristiwa sejarah Belanda dan Hindia Belanda
sebagai kompetensi dasar bagi setiap guru yang mengajar dan bukan
hanya guru sejarah. Sebenarnya bukan hanya guru, pengajar les dari
rumah ke rumah juga dalam sistem pendidikan Belanda, harus memiliki
kompetensi pengetahuan Sejarah Belanda dan Hindia Belanda , Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga menetapkan kompetensi
bagi Kepala sekolah (Hoofd-onderwijzer) untuk menguasai sejarah secara
lebih dalam. Kompetensi yang wajib dikuasai oleh kepala sekolah adalah
menguasai beberapa pengetahuan tentang tokoh-tokoh sejarah Klasik,
keakraban dengan fakta-fakta utama dari sejarah Abad Pertengahan dan
sejarah Baru, terutama dengan peristiwa-peristiwa utama Abad ke-19,
pengetahuan tentang sejarah Belanda sebagai Tanah Air Belanda serta
kekuasaan Kolonialisme yang dimilikinya ,
Dari kutipan di atas diketahui fakta bahwa kompetensi seorang
kepala sekolah (Hoofd-onderwijzer), tidak hanya wajib memahami sejarah
Belanda dan Hindia Belanda, akan tetapi secara lebih mendalam wajib
mengetahui berbagai materi lain dalam sejarah yaitu tokoh-tokoh sejarah
Klasik. Mengetahui dan dapat menjelaskan fakta-fakta utama sejarah
Abad Pertengahan dan Sejarah Zaman Baru (enlightment), dan terutama
penguasaan atas peristiwa-peristiwa sejarah penting pada abad ke-19.
Selain itu kepala sekolah wajib memiliki kompetensi sejarah Belanda
sebagai tanah air bagi kolonialisme, dan memiliki pengetahuan sejarah
akan negeri-negeri koloni Belanda, terutama sejarah Hindia Belanda.
Buku Teks Rujukan Pelajaran Sejarah
Buku teks merupakan salah satu bagian penting dalam materi
pelajaran sejarah. Dengan berbagai keterbatasan, pemerintah Kolonial
mengeluarkan buku rujukan bagi pelajaran sejarah. Buku teks sejarah
setebal 97 halaman dengan judul Korte geschiedenis van Nederlandsch-Indie
diterbitkan tahun 1917 ) merupakan sumber bagi penelitian
ini. Buku tersebut merupakan rujukan yang digunakan untuk sekolah
lagere scholen, MULO dan Middelbaar Onderwijs. Buku tersebut berisi sejarah Nusantara dalam perspektif kolonial yang disusun secara
kronologis dan ringkas tentang pelajaran sejarah. Berikut merupakan
periodisasi yang disusun peneliti karena dalam teks tidak dilakukan
pembagian berdasarkan periode namun berisi bab saja.
Titik awal periodisasi dalam buku tersebut dimulai dengan sejarah
pra-Islam dengan waktu mundur sekitar 2000 tahun lalu sampai masa
Kerajaan Majapahit. Dimulai dengan materi tentang Jawa 2000 tahun yang
lalu, dilanjutkan dengan hadirnya penduduk baru, Jawa di antara umat
Hindu, Kerajaan Hindu, agama penduduk tertua (pra-Hindu), agama
orang Jawa Hindu, Hindu dan pribumi, Agama Hindia lainnya di Jawa,
kuil, serangan Cina, Kerajaan Majapahit dan akhir dari sebuah kerajaan
besar tersebut.
Materi pada periode kedua adalah mengenai latar belakang
kedatangan Kompeni Belanda yaitu VOC, perusahaan perniagaan multi
nasional terbesar dunia pada zamannya, hingga runtuhnya VOC. Diantara
materi teks referensi tersebut adalah Hindia dan Eropa, orang-orang asing
di Nusantara, Hindia pada abad ke-16, Kunjungan pertama dari Belanda
dan kunjungan selanjutnya, Kerjasama, Dasar-dasar Hindia Belanda,
Sultan Ageng dan kompeni, kompeni (VOC) di luar Jawa, Sulawesi,
Sumatera dan seterusnya, Mataram membutuhkan kompeni, Banten,
Compagnie, Vorsten, dan Onderdanen, bagian dalam Mataram, perang untuk
tahta Mataram, Perdagangan dengan Kompeni, pemberontakan orang
Cina, Perubahan Jawa, berakhirnya Kompeni.
Periode ketiga yaitu kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di
Nusantara, yang dimulai awal abad 18 hingga peristiwa-peristiwa aktual
sebelum tahun 1917. Diantara bab yang terdapat dalam periode ini adalah Nusantara di bawah pemerintahan baru, Bangsa Inggris di Hindia dan
Jawa, Hindia kembali di bawah otoritas Belanda, Sistem budaya, Hindia
di luar Jawa, Perang Aceh, Perang di Lombok, Hindia dan Tanah Air,
Peradaban dan kemakmuran, dan beberapa peristiwa ‘kontemporer’ di
Hindia.Selain ketiga periode yang ditentukan dan dipengatuhi ideologi
pemerintah Kolonial, terdapat bab atau materi lain yang menjadi
suplemen tambahan bagi buku. Yaitu susunan kronologi perisitwa sejarah
penting sejak 2000 tahun yang lalu, kelahiran Kristus, pelayaran Eropa,
sampai penaklukan Aceh, yang kesemuanya Barat-sentris , Buku teks ini ditutup dengan lampiran peta Dunia yang
berisikan rute pelayaran orang Eropa ke Nusantara.
Pelajaran Sejarah di Sekolah Kolonial
Mata pelajaran sejarah menjadi kompetensi murid-murid pada
pendidikan kolonial di berbagai tingkatan. Mata pelajaran yang diberikan
pada Europeesche Lagereschool (ELS) seperti yang diberikan pada sekolah di Negeri Belanda, dengan perkecualian pelajaran Sejarah Tanah Air
(Belanda) diganti dengan Sejarah Negeri Belanda dan Hindia Belanda
. Sedangkan Gewoon Lager Onderwijs merupakan sekolah
dasar dengan jumlah sekolah 20 di Jawa dan Madura dan diluar itu 15
sekolah, dengan jumlah siswa dapat mencapai 200 orang , Pada kelas permulaan sekolah dasar tersebut para
siswa mendapatkan mata pelajaran die der geschiedenis van Nederland en
Nederlandsch-lndië (Sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda)
Adapun sekolah menengah lanjutan yaitu Meer Uitgebreid Lager
Onderwijs (MULO) mendapatkan pelajaran die der algemeene geschiedenis
(Sejarah Umum) bagi murid-muridnya , Sedangkan,
AMS A II yang berorientasi klasik Barat terdapat pelajaran Sejarah
Kebudayaan Kuno Barat, namun sejarah kebudayaan/kesenian ‘Indonesia’
tidak diberikan tempat
Selain sekolah formal, sekolah keagamaan juga memiliki mata
pelajaran sejarah. Diantaranya adalah Zusters Ursulinen (Suster Ursulin)
merupakan lembaga pendidikan untuk suster khususnya wanita muda
yang bertempat di Weltevreden terdapat pelajaran De Geschiedenis
(Algemeene en Vaderlandsche) Adapun sekolah
Ursulinen-School To Bandoeng yang merupakan sekolah persiapan untuk
pendidikan lager (dasar) dan uitgebreid lager (lanjutan), mewajibkan
siswanya untuk menempuh mata pelajaran De geschiedenis van Nederland
en Nederlandsche Indies (Sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda) dan
bahkan selain sejarah umum belajar juga De Fransche en Engelsche taal
Algemeene geschiedenis (Sejarah Sastra Perancis dan Inggris) , Sekolah ini juga terhubung dengan Fröbelschool (sekolah Frobel) dan
industrieschool (Sekolah Industri).
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga menetapkan diantara ujian
untuk Middelbaar Onderwijs, diperlukan kemampuan output pembelajaran
sejarah yakni kompetensi yang wajib dimiliki setiap siswa yaitu van zijn
kennis van de voornaamste feiten en jaartallen der vaderlandsclie geschiedenis
(pengetahuan siswa tentang fakta-fakta utama sejarah dan tahun-tahun
bersejarah)
Urgensi pembelajaran sejarah juga merupakan salah satu kompetensi
pada HBS dimana untuk ujian akhir Hoogere Burgerscholen (HBS), terdapat
mata uji Sejarah . Di sekolah Hoogere Burgerschool
En Pensionaat Voor Meisjes Te Weltevreden, kandidat yang menginginkan
masuk sekolah tersebut harus memiliki kemampuan sejarah diantaranya
Van hare bekendheid met de Vaderlandsche Geschiedenis (Memiliki keakraban
dengan Sejarah Tanah Air Belanda)
Selain murid dan pendidik, kompetensi sejarah juga diperlukan
untuk beberapa persyaratan pekerjaan baik di bidang sipil maupun nonsipil. Diantaranya adalah ujian akhir pegawai administratif Hindia
Belanda, dimana kandidat akan mendapatkan tes mengenai de geschiedenis
van N. I., alsmede de historie en de methoden der zending in den Maleischen
Archipel sedert 1800 (Sejarah Hindia Belanda serta sejarah dan metode
zending di Nusantara/Kepulauan Melayu sejak tahun 1800)
Selain pegawai administratif, pendaftaran ke sekolah militer seperti
pada Meester-Cornelis, memerlukan kompetensi yaitu mata uji Sejarah
yang lebih mendalam. Kompetensi untuk masuk dalam sekolah militer, siswa sebagai pelamar harus memiliki pemahaman pengetahuan tentang
[1] sejarah Klasik dan Abad Pertengahan serta pengantar menuju Sejarah
Baru; [2] Sejarah Baru: Gambaran umum mengenai sejarah Baru sampai
dengan 1648, terutama menyangkut tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa
yang telah memberikan pengaruh dominan pada perkembangan
masyarakat pada umumnya, atau lebih khusus terkait dengan Belanda. [3]
[Penguasaan] Sejarah Patriotisme Belanda hingga 1568 dengan sangat
baik; sejak 1568 hingga 1648 dengan paparan lebih detail dan ikhtisar
ringkas tentang sejarah Koloni Belanda dan harta-harta benda, sejak
pembentukan otoritas Belanda - 1648. Sebagai perbandingan, kursus
perdagangan pun yaitu Prins Hendrikschool Te Batavia-Handelscursus, selain
mendapatkan penguasaan kemampuan pencatatan (akuntansi) dan
kemampuan bahasa, juga sampai pemahaman mengenai sejarah yaitu
Handelsgeschiedenis en staahuishoudkunde (sejarah perdagangan dan
ekonomi baja), meskipun tidak spesifik berhubungan langsung dengan
sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda
Tokoh Bumiputera Belajar Sejarah
Tokoh pertama yang menjadi bagian dari penelitian tentang
pelajaran sejarah pada pendidikan Kolonialisme adalah Soekarno. Dalam
pembahasan ini artikel pada koran Leeuwarder Courant berjudul “Soekarno,
Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie” menjadi salah satu
referensi penting. Perjalanan pendidikan Soekarno dimulai ketika ia
masuk dalam sekolah Hollandsch-Indische, di mana ayahnya adalah kepala
sekolah. Ketika dia melalui lima kelas, ayahnya memutuskan bahwa
waktunya telah tiba bagi Soekarno untuk masuk ke jenis sekolah yang
lebih tinggi, yang awalnya ditujukan untuk anak-anak Belanda: sekolah dasar Eropa. Pada masa transisi, Soekarno kehilangan satu tahun: ia
datang di kelas lima ELS. Setelah selesai ELS, ayahnya mewajibkannya
untuk melanjutkan pendidikannya ke HBS. Sebelum itu, Soekarno pergi
ke dan menjadi murid seorang teman ayahnya, H.O.S. Tjokroaminoto.
Bertahun-tahun Soekarno tinggal di sana, mendapat pengaruh yang
sangat besar pada kehidupan selanjutnya. HBS kemudian dilewati
Soekarno tanpa banyak kesulitan dimana Soekarno masuk pada usia 15
tahun dan lulus pada saat usianya 20 tahun.
Setelah memutuskan untuk meninggalkan sebuah beasiswa studi ke
luar negeri, keinginan lama Soekarno untuk menjadi seorang seniman
kembali bergelora. Pada 1921 Soekarno melanjutkan studi yang dapat
menyalurkan jiwa seni dengan kemampuan hardskill teknik, yaitu
Technische Hogeschool di Bandung ,. Kemudian di Surabaya, datang
berita bahwa Tjokroaminoto ditangkap karena sifat anti Kolonialisme
organisasi politik Sarekat Islam yang dipimpinnya, sehingga Soekarno
memutuskan untuk bekerja demi mengurus berbagai keperluan keluarga
Tjokroaminoto. Tjokroaminoto dibebaskan setelah tujuh bulan dan
Soekarno kembali ke Technische Hogeschool (sekarang ITB).
Meskipun Soekarno juga menghabiskan cukup banyak waktu untuk
kegiatan politik, studinya berkembang dengan baik dan sangat cepat
sehingga pada 25 Mei 1926 ia lulus sebagai insinyur sipil dengan
spesialisasi arsitektur dan waktu belajarnya telah selesai. Soekarno
kemudian memilih jalan non-kooperatif sebagai kelanjutan dari ideologi
yang ditularkan gurunya, Tjokroaminoto sang tokoh Sarekat Islam,
sehingga Soekarno menolak bergabung dan bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Soekarno menerima beberapa tugas pribadi untuk
pembangunan perumahan, yang kemudian ia bekerjasama dengan Ir.
Anwari pada sebuah perusahaan arsitektur. Yang menarik adalah
Soekarno pernah menjadi guru sejarah dan matematika di sekolah swasta
yang digerakkan oleh Dr. Setia Buddhi Danoedirdjo (nama aslinya adalah
Dr. E.F.E. Douwes Dekker)
Dalam sebuah koran Belanda yaitu Leeuwarder courant, disebutkan
lebih lanjut bahwa seorang inspektur yang menghadiri pelajaran sejarah
dari Soekarno menyatakan dia tidak cocok untuk pekerjaannya
(“Soekarno, Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie,”
1970). Patut diduga bahwa seorang inspecteur yang menghadiri kelas
pelajaran sejarah dari Soekarno keberatan jika Soekarno mengajarkan dan
mempertajam kemampuan berpikir kritis siswa-siswanya dengan
pelajaran sejarah. Kemampuan berpikir kritis dikhawatirkan mengganggu
stabilitas jalannya pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, sehingga
pengawas tersebut keberatan dan menilai Soekarno tidak cocok
mengajarkan sejarah. Dalam hal kecil saja misalnya, Soekarno enggan
menggunakan sebutan “raden” yang menunjukkan sikap kritisnya
terhadap feodalisme yang saat itu bergandengan tangan dengan
kolonialisme Hindia Belanda.
Dari pelajaran sejarah, Soekarno memahami pentingnya pergerakan
rakyat melalui organisasi yang mendorong cita-cita kemerdekaan
menentang kolonialisme Barat, sehingga ia aktif bekerjasama dan
mendirikan berbagai organisasi sebagai corong perjuangan. Soekarno
mendirikan Algemene Studie Club (Klub Studi Umum) di Bandung pada tahun 1925, di mana ia menjadi ketua. Selain studi klub, Soekarno juga
aktif dalam Jong Java. Soekarno juga mengadakan pidato dimana pada
setiap kesempatan ia menyampaikan penentangannya terhadap
pemerintahan kolonial Belanda, yang selanjutnya menunjukkan bahwa
Soekarno adalah orator handal yang mampu menarik kerumunan massa
yang banyak. Pada 4 Juli 1927 Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional
Indonesia, yang namanya diubah setahun kemudian di Partai Nasional
Indonesia dengan para pendiri lainnya yaitu Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo,
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Mr. Budiardjo dan Mr. Soenarjo.
Dalam buku autobiografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams,
bung Karno menjelaskan bagaimana besarnya pengaruh guru-guru yang
meskipun berbangsa Belanda, telah mengajarkan bagaimana demokrasi
Yunani dari pelajaran sejarah. Pada zaman demokrasi Yunani Kuno, para
wakil rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan mengajar rakyat untuk
menentang penindasan dan penghisapan, sambil membangun
kemerdekaan dan keadilan
Materi pelajaran mengenai sejarah Yunani Kuno tersebut ternyata
membuat Soekarno berpikir bahwa kondisi di Hindia Belanda
mengkhawatirkan dimana berbanding terbalik dengan realitas sosial
kondisi dimana penindasan, penghisapan, kemerdekaan dan keadilan.
Hal tersebut, tidak hanya berhenti pada pemikiran personal saja, akan
tetapi juga diungkapkan dan mengadu argumentasi-argumentasinya
dalam debating club bersama siswa-siswa Belanda di HBS Surabaya
mengenai kolonialisme
Dalam perspektif ilmu pendidikan, saat Soekarno mempresentasikan
hasil penelitian atau pemikirannya di depan kelas atau dalam debating club, menurut Maor sebenarnya melalui kegiatan tersebuts kemampuan
berpikir kritis tingkat tinggi akan terbukti
Pemikiran Soekarno juga dipengaruhi oleh diskusi tokoh-tokoh dari
berbagai aliran yang berdiskusi di rumah Tjokroaminoto, tempat
Soekarno tinggal, sehingga dalam menelurkan pemikirannya dalam
media massa penentangan kolonialisme yaitu Oetoesan Hindia. Pemikiran
kritis Soekarno membuatnya dijuluki “Karel” oleh seorang guru wanita
Belanda. HBS bagi Soekarno, telah menjadi suatu forum pertemuan
kebudayaan Barat dengan pemuda Indonesia yang minoritas, dan menjadi
tempat “transformasi” jiwa kemerdekaan bangsa Belanda kepada kita
.
Tokoh selanjutnya yang mengalami pendidikan masa Kolonialisme
adalah Roeslan Abdulgani yang kelak menjadi Menteri setelah Indonesia
merdeka . HBS Surabaya selain oleh Soekarno juga pernah
menjadi tempat belajar bagi Roeslan Abdulgani (masuk tahun 1932), dan
lulus pada tahun 1934 dengan mengikuti kelas 4 dan kelas 5 dari de
wiskundige afdeeling. Di samping itu juga ada de literaire afdeeling yang
banyak mempelajari sastra dan kebudayaan, termasuk bahasa Yunani dan
bahasa Latin. Roeslan Abdulgani dalam pemaparan pengalamannya
mengenai sistem pendidikan belanda menyebutkan bahwa:
“Suatu kenyataan yang tak dapat diungkiri ialah bahwa jiwa
pendidikan dan sistem pelajaran dalam lingkungan HBS Surabaya
adalah jiwa kemerdekaan dan kebebasan yang kuantitatif dan
kualitatif sangat bernilai sekali. Sesuai dan sama seperti yang
dipraktekkan di Negeri Belanda sendiri. Inilah konsekuensi dari
concordantie-beginsel. Dengan begitu anak pribumi yang dapat masuk
ke lingkungan HBS itu ikut menghirup udara segar kemerdekaan.
Padahal di luar itu adalah masyarakat kolonial. Dengan adanya
situasi kontradiktif dan antagonistis ini jiwa anak-anak pribumi selalu memberontak. Udara segarnya HBS memberi dorongan dan
inspirasi untuk menentang sistem kolonialisme Belanda. Dengan
demikian HBS Surabaya merupakan suatu ”enclave dan oase” di
tengah-tengah masyarakat kolonial.”
Pemikiran-pemikiran kritis murid-murid HBS, selain melalui
pengajaran dari guru-guru, juga melalui budaya literasi yang tinggi di
tengah berbagai keterbatasan sumber bacaan. Misalnya, di kelas 4 pada
mata pelajaran bahasa, murid-murid diwajibkan membaca karya sastra
yang harus dibaca dan akan diuji melalui ujian lisan yaitu 30 buku Sastra
Belanda, 10 buku Sastra Inggris, 10 buku Sastra Jerman, dan 10 buku
Sastra Perancis dengan berjumlah 60 buku ,Hal tersebut menjadi bahan renungan dan evaluasi bagi pengajar
sejarah khususnya bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kritis bagi siswa harus juga didampingi dengan budaya literasi yang baik.
Selain melalui pelajaran sastra, menurut Roeslan Abdulgani, mata
pelajaran sejarah sangat mempertebal patriotisme dan nasionalisme.
Roeslan Abdulgani diajari seorang guru sejarah berkebangsaan
Belanda bernama Postma mengajarkan berbagai pelajaran yang berharga
dan berpengaruh bagi nasionalisme Indonesia. Pelajaran sejarah yang
diberikan dianggap sebagai ajaran sejarah yang progresif dan tak
disebutkan sedikitpun bahwa sejarah merupakan hafalan tanpa makna
yang membosankan:
“Dari Postma beliau [Roeslan Abdulgani] mendapat pelajaran
tentang Revolusi Perancis, yaitu revolusi yang berpengaruh
terhadap revolusi-revolusi antara tahun 1830- 1850 di Jerman, dan
disusul dengan adanya kontra revolusi dan seterusnya. Juga adanya
gerakan pemuda dan mahasiswa Jerman pada awal abad ke-19,
tumbuhnya gerakan buruh di Jerman dan Inggris, lahirnya
Manifesto Komunis oleh Karl Marx, meningkatnya sistem
kapitalisme dan kolonialisme Eropa menjadi imperialisme modern sekitar tahun 1870, akibat-akibat imperialisme modern terhadap Asia
Afrika, perjuangan Garibaldi dan Mazzini untuk persatuan Italia,
dan aktivitas Bismarck untuk menyatukan seluruh Jerman.
Semuanya itu mendebarkan hati murid-murid pribumi HBS
Surabaya.”
Pelajaran sejarah progresif diberikan di HBS, menurut Dr. H.
Roeslan Abdulgani bertentangan dengan pelajaran sejarah di MULO
Ketabang Surabaya yang mengutamakan hafalan dan berbau rasialisme,
mengagungkan sejarah bangsa kulit putih dan meremehkan sejarah
bangsa sawo matang
HBS memfasilitasi perkembangan peserta didiknya melalui berbagai
aktifitas pendidikan diantaranya terdapat discussion group yang diatur
oleh kepala sekolah dan juga terdapat debating club dimana pada akhirnya
terdapat anak-anak pribumi dengan teman Cina dan tiga murid Belanda
yang simpati terhadap nasionalisme dan patriotisme Indonesia
. Debating-club telah berhasil
menghadirkan diskusi-diskusi dengan sumber-sumber primer seperti
pidato pembelaan Bung Hatta di muka pengadilan Belanda di Den Haag
tahun 1928 berjudul De on uitgesproken pleifrede van Mon. Hatta voor de
Arrondissements rech tbank te 's-Gravenhage, yang sebelumnya dilarang
beredar, juga dibahas pidato pembelaan Bung Karno di pengadilan
kolonial di Bandung pada 2 Desember yaitu Indonesie klaagt aan! Para
murid berhasil mentrasformasikan pemikiran Soekarno dan Hatta,
dimana terdapat persamaan bahwa keduanya mencerminkan jiwa ingin
merdeka.
Sekolah HBS menjadi tempat yang terbuka bagi pengembangan
intelektualitas bahkan jika harus menentang kolonialisme Belanda. Hal
tersebut dapat dilihat dengan kewajiban membaca buku karya sastra yangdibaca bersama di muka kelas pada pelajaran bahasa Belanda, yaitu buku
Max Havelaar of de koffie-veilingen de Nederlansche Handelsmaatschappij oleh
Multatuli yang terkenal itu. Menurut Roeslan Abdulgani, bahwa dengan
dijadikannya bacaan wajib buku tersebut mengakibatkan timbulnya
kesadaran merasa bersalah atau Schuldbewustheid hingga “ingin menebus
dosa” di kalangan Pemerintah Belanda juga dirasakan khususnya guruguru Belanda di HBS . Menarik
untuk dicermati bahwa buku anti kolonial yang telah membakar
semangat itu ditetapkan sebagai buku wajib termasuk bagi mayoritas
murid-muridnya adalah anak-anak Belanda di HBS.
Aspek-aspek pembelajaran sejarah yang terdapat dalam penelitian
ini adalah kompetensi pendidik mengenai sejarah, buku teks rujukan
pelajaran sejarah, penerapan pelajaran sejarah, serta objek pendidikan
yaitu murid yang mengikuti proses pembelajaran dalam sistem
pendidikan Belanda. Berbagai aspek tersebut akan dibahas dan dianalis
pada bagian pembahasan ini.
Pemahaman sejarah merupakan kompetensi yang wajib dikuasai
bagi pendidik mulai dari guru kelas, guru les, sampai kepala sekolah.
Bahkan kepala sekolah harus menguasai materi sejarah secara lebih
dalam. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki pandangan bahwa
pelajaran sejarah penting untuk dipahami dan dikuasai karena menjadi
basis dan legitimasi bagi ideologi pemerintah kolonial yaitu Kolonialisme
yang ditujukkan kepada peserta didik. Sebelum peserta didik diajarkan
sejarah versi kolonial, maka peran pengajar menjadi penting sebagai
perantara indoktrinasi serta salah satu sumber belajar. Kompetensi pelajaraan sejarah juga digunakan pada berbagai ujian
dalam tingkatan jenis sekolah. Diantara sekolah formal yang mewajibkan
sejarah adalah Europeesche Lagereschool (ELS), Gewoon Lager Onderwijs, Meer
Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Algemeenee Middelbare School (AMS),
serta Hoogere Burgerschool (HBS). Sekolah keagamaan juga memiliki mata
pelajaran sejarah diantaranya Zusters Ursulinen, Ursulinen-School,
Fröbelschool (sekolah Frobel) serta industrieschool (Sekolah Industri). Selain
sekolah, kompetensi sejarah juga diperlukan untuk pekerjaan di bidang
sipil maupun non-sipil seperti ujian akhir pegawai administratif Hindia
Belanda, pendaftaran sekolah militer Meester-Cornelis, sampai kursus
perdagangan (ekonomi).
Dalam sistem pendidikan Belanda, pelajaran sejarah dijadikan alat
untuk mendukung tujuan, program serta kebijakan pemerintah Kolonial.
Oleh karena itu, materi pelajaran sejarah selain Sejarah Hindia Belanda,
juga mewajibkan Sejarah Belanda yang disebut ‘tanah air’ menjadi bagian
penting dari materi yang diberikan kepada siswa Belanda maupun
bumiputera . Materi sejarah juga beriorentasi sejarah
Eropa-sentris yang mengagungkan superioritas Barat sehingga materi
berikut menjadi penting diantaranya tentang tokoh sejarah klasik Eropa,
peristiwa Abad Pertengahan dan Pencerahan di Eropa sampai peristiwa
abad 18-19 di Eropa. Materi pelajaran sejarah tidak mementingkan
kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu. Hal tersebut dapat terlihat dari
susunan kronologis serta materi sejarah yang diajarkan pada sekolahsekolah Belanda. Selain itu diajarkan sejarah penguasaan akan negerinegeri koloni Belanda, seperti Hindia Belanda juga Hindia Barat.Buku teks yang dijadikan rujukan bagi pelajaran sejarah juga
didesain sedemikian rupa sehingga sejalan dengan agenda penyebaran
ideologi Kolonialisme. Peneliti menganalisis bahwa perspektif kolonial
sangat berpengaruh pada buku teks dengan berdasarkan pada beberapa
temuan yang sarat akan hubungan dengan kepentingan kolonialisme
Belanda. Temuan-temuan tersebut akan disebut sebagai propaganda pada
buku teks. Propaganda pertama, Bangsa Kulit Putih merupakan bangsa
yang lebih beradab dibandingkan bumiputera dan hal ini merupakan
rasialisme dan mengungkapkan superioritas Barat. Hal inilah yang
disebut disaksikan oleh Roeslan Abdulgani yang menyatakan bahwa
pelajaran sejarah pada masa kolonial mengutamakan hapalan dan berbau
rasialisme, mengagungkan sejarah bangsa kulit putih dan meremehkan
sejarah bangsa sawo matang
Propaganda kedua, Nusantara dan Jawa berakar dan berasal dari
Hindu, sehingga terlihat kesan untuk menjauhkan Islam dari penduduk
Nusantara dan termasuk tidak banyak membahas mengenai sejarah Islam
di Nusantara. Hal ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah Kolonial
menghadapi umat Islam Indonesia karena fenomena revival umat Islam
dengan memperbanyak pendirian lembaga pendidikan kolonial ,
Propaganda ketiga, VOC dan Belanda datang ke Nusantara adalah
untuk berbisnis dan bukan menjajah, adapun pada akhirnya berkuasa itu
karena kesalahan raja-raja Nusantara yang saling bertikai. Dengan narasi
ini, Belanda membangun legitimasi kekuasaannya atas penjajahan di
Nusantara dengan menyebut diri sebagai penyelamat karena berperan menengahi konflik antar kerajaan sehingga seyogyanya bumiputera
menerima Kolonialisme Belanda.
Propaganda keempat, melalui simbol pengagungan tokoh-tokoh
yang dianggap sebagai penjajah namun dalam perspektif kolonial adalah
pahlawan. Diantara tokoh Barat yang ditampilkan melalui lukisan yaitu
potret J. P. Koen, Daendels, Raffles, van Heutz, tanpa ada satupun tokoh
Nusantara. Sebaliknya disebutkan bahwa Sultan Agung adalah “raja yang
kejam yang tidak menyelamatkan nyawa manusia [dimana] seluruh
wilayah hancur, desa dan kota dibakar, penduduk dibunuh atau diambil
sebagai budak” ,
Propaganda kelima, Belanda memberikan stigma dan label jahat bagi
siapapun pihak yang menentang Kolonialisme Belanda. Misalnya Belanda
menyebut dirinya pahlawan dan sebaliknya disebutkan bahwa rakyat
Aceh yang melawan Belanda adalah bajak laut, pencuri, licik, dan
sebagainya. Sedangkan ketika Aceh ditaklukan disebutkan bahwa
“Belanda [akhirnya] melakukan yang terbaik dengan memberi orangorang Aceh kemakmuran yang seharusnya sudah begitu lama [mereka
dapatkan]” ,
Bagi murid-murid bangsa Belanda, pelajaran sejarah telah
menanamkan rasa superioritas mereka sebagai bangsa penjajah dan
sebaliknya bagi bumi-putera pelajaran sejarah menanamkan identitas
sebagai bangsa terjajah. Narasi kebesaran kaum Eropa ke Nusantara
menjadi salah satu bagian yang berimplikasi pada produk pendidikan
yang menghasilkan siswa-siswa bumiputera yang menghasilkan
kemampuan berpikir kritis, mengembangkan nilai-nilai positif untuk
diimplementasikan. Hal tersebut memberikan landasan bagi siswa bumiputera untuk melawan Kolonialisme dan Imperialisme Belanda dan
membangkitkan kesadaran kolektif kebersamaan sejarah bumiputera
sebagai proses pengenalan diri.
Proses pengenalan diri, menurut Wiraatmadja, merupakan titik awal
dari timbulnya harga diri, kebersamaan, dan keterikatan (sense of
solidarity), rasa keterpautan dan rasa memiliki (sense of belonging),
kemudian rasa bangga (sense of pride) terhadap bangsa dan tanah air
sendiri . Pelajaran sejarah secara tidak langsung telah
menanamkan rasa bangga (sense of pride) terhadap bangsa dan tanah air
Indonesia, meskipun pendidikan Belanda untuk bumi-putera baru
dimulai sejak awal abad XX melalui politik etis (etische politiek) dan hanya
terbatas pada anak-anak dari kalangan elit.
Fenomena yang tidak direncanakan Belanda tersebut menunjukkan
bahwa mata pelajaran sejarah, telah membuka cakrawala dan pemikiran
para tokoh untuk mengambil pelajaran, dan tidak hanya berhenti pada
intelektualitas, pengajaran sejarah dapat menggerakkan para siswa untuk
bertindak dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Tindakan-tindakan
(Acts) yang meningkatkan keterampilan berpikir yang didasari atas
pengaruh dari aktifitas-aktifitas pedagogis di ruang kelas, jika ditinjau
dari taksonomi Bloom, maka dapat dikategorisasi bahwa murid-murid
HBS dengan pelajaran sejarah tak berhenti pada tingkatan keterampilan
berpikir tingkat rendah (LOTS/Low Order Thinking Skills) akan tetapi
hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS/High Order Thinking
Skills) . Para murid tidak hanya
mengingat (Cl) dan memahami (C2), akan tetapi juga sampai pada
tahapan analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6), karena setelah mendapatkan pelajaran sejarah, mereka juga mengambil sintesis dan
mengevaluasi kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi yang terjadi.
Perlu diketahui pula bahwa situasi politik pada lembaga pendidikan
Belanda turut mempengaruhi dan meningkatkan rasa kritis para murid
bumiputera. Misalnya angkatan Soekarno yang berada pada situasi tahun
1916-1921 diliputi progresivitas aktivitas gerakan Serikat Islam,
berakhirnya Perang Dunia I, naiknya ekspor gula, serta janji ‘merdeka’
dari Pemerintah Belanda tahun 1918 yang tidak dipenuhi telah
mendorong pergerakan nasional Indonesia termasuk para murid
bumiputera menuju ke arah radikalisme. Situasi tersebut telah mencetak
banyak generasi yang kritis terhadap Kolonialisme bahkan cenderung
radikal.
Periode selanjutnya diantaranya zaman Mukarto dan Roeslan
Abdulgani, situasi politik diliputi pengaruh krisis malaise 1930,
pemberontakan kapal perang Zeven Provincien, serta tangan-besi
pemerintah kolonial terhadap pemimpin-pemimpin pergerakan nasional
Indonesia. Panasnya situasi politik umum dan itu ternyata masuk juga ke
dalam gedung sekolah HBS
Pemikiran kritis para murid, yang telah sampai pada tingkatan
mengevaluasi situasi politik di ruang-ruang kelas, jika dihubungkan
dengan pendapat Stasz et al. dan Thomas mengenai HOTS dimana kondisi
keterampilan berpikir tinggi tersebut menandai adanya proses
pembelajaran yang ditandai adanya: (a) kolaborasi antara guru, siswa, dan
lintas ilmu (b) mendorong keingintahuan, eksplorasi, dan penyelidikan (c)
pembelajaran berpusat pada siswa (d) kegagalan dipandang sebagai
kesempatan belajar (e) pengakuan terhadap usaha, tidak hanya pada prestasi (f) belajar secara kontekstual dalam kehidupan nyata
,Meskipun taksonomi Bloom muncul jauh
setelah Indonesia merdeka, akan tetapi pandangan Bloom dan ahli
pendidikan cukup memberikan gambaran bahwa pendidikan sejarah
yang diajarkan pada masa kolonialisme Belanda berhasil melahirkan
tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bertindak dan
beraksi pada kehidupan nyata siswanya di masa depan sebagai bentuk
tertinggi dalam taksonomi kognitif.
Eksplanasi serta interpretasi yang disajikan di atas menunjukkan
penelitian sejarah melalui metode sejarah dapat dibantu dengan bidang
keilmuan lain diantaranya konsep atau teori pendidikan dalam membahas
tema-tema sejarah pendidikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu
sumber-sumber primer sezaman dengan jumlah yang terbatas mengenai
sistem pendidikan kolonial khususnya yang berkenaan dengan
pembelajaran sejarah. Namun, kajian terhadap kompetensi pendidik,
materi pelajaran, buku teks rujukan pelajaran, serta kesaksian murid, yang
berhubungan dengan pelajaran sejarah dapat membuka ruang bagi
penelitian selanjutnya dengan kualitas maupun kuantitas data yang lebih
beragam. Penelitian ini cukup memberikan informasi mengenai situasi,
kondisi, serta implikasi dari pembelajaran sejarah pada masa
Kolonialisme Belanda yang diharapkan dapat berkontribusi bagi kajian
Sejarah Pendidikan di Indonesia.Pendidikan merupakan proses yang berkaitan
dengan upaya untuk mengembangkan tiga aspek dalam
diri seseorang dalam kehidupanya, yaitu pandangan
hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Bangsa
Indonesia telah mengalami berbagai bentuk praktek
pendidikan, pertama dimulai dari praktek pendidikan
Hindu, pendidikan Budha, pendidikan Islam, pendidikan
zaman Vereenigde Oest Indische Compagnie (VOC),
pendidikan kolonial Belanda, pendidikan zaman
pendudukan Jepang dan zaman setelah merdeka hingga
sekarang, akan tetapi pendidikan Belanda yang sangat
melekat di Indonesia, antara lain dari bentuk sekolah,
kelas dan susunan tempat duduk, sangat persis dengan
pendidikan Belanda dulu.
Pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda
pada awalnya hanya diterapkan untuk memenuhi
kebutuhan para pegawai Belanda beserta keluarganya
yang memerlukan pendidikan dan latihan, baik mengenai
pengetahuan umum maupun mengenai pengetahuan
khusus tentang Indonesia (Sumarsono 1996: 11). Ini
berarti pendidikan Barat hanya tersedia bagi pihak
Belanda sendiri, yang kemudian memberikan kebijakan
bagi golongan yang dipersamakan dengan orang-orang
Eropa dan Barat serta anak-anak priyayi. Perkembangan
pendidikan di Indonesia semakin mendapati tahapan
barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun
1900. Ketika Van Deventer menjabat sebagai Gubernur
Jendral Hindia Belanda dan menerapkan sebuah
kebijakan baru yang dikenal sebagai Politik Etis (Politik
Balas Budi). Dengan motto “de Eereschuld” (hutang
Kehormatan) dan slogan “Educatie, Irrigate, Emigrate”
(Pendidikan, Irigasi, Emigrasi). Akan tetapi program
politik etis ini ternyata menjadi program yang merugikan
rakyat, karena pendidikan yang diberikan diharapkan
dapat mengurangi dasar pendidikan nasional bangsa
Indonesia seperti patriotisme, gotong royong, berdikari
dan sebagainya (Ary Gunawan, 2006:19).
Sistem pendidikan Belanda diatur dengan
sistem prosedural yang ketat dalam pelaksanaannya.
Pendidikan yang diberikan dibedakan berdasarkan tiaptiap golongan stratifikasi sosial. Pendidikan yang
diberikan pemerintah Hindia Belanda lebih diutamakan
bagi para golongan bangsawan dan yang dipersamakan
dengan orang-orang Eropa. Untuk menentukan status
seseorang dalam masyarakat kolonial, pemerintah
Belanda berpegangan pada penghasilan. Dengan
perhitungan tertentu maka yang berpenghasilan di atas f1
1.200 setahun dianggap sebagai golongan yang
mempunyai status yang cukup tinggi. Dalam dunia
kepegawaian, ini berlaku bagi pangkat asisten wedana ke
atas (Niel, 1997:34).
Sekolah-sekolah yang disediakan oleh
pemerintah Hindia Belanda bagi kaum bangsawan di
Indonesia salah satunya adalah Europese Lagere School
(ELS) yang merupakan sekolah dasar Eropa yang pada
dasarnya diperuntukan bagi keturunan Belanda yang
kemudian memberikan kebijakan pada para ketutunan
raja untuk memasukinya, Hollandse Inlandse School
(HIS) merupakan sekolah dasar yang diperuntukkan bagi
para bangsawan pribumi yang pada kenyataannya
golongan rakyat biasa juga dapat memasuki sekolah ini,
Hogere Burger School (HBS) merupakan sekolah
menengah dan sekolah lanjutan bagi lulusan ELS dan
Opleiding School Voor Inlandshe Ambteneran (OSVIA)
merupakan sekolah dasar yang disebut juga Sekolah
Raja (Sumarsono 1996: 14)
Berbagai kebijakan pendidikan telah diterapkan
oleh pemerintah Hindia Belanda berupa pendirian
lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secaraefektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaum bangsawan
adalah orang-orang keturunan raja-raja dan aristroktat
dalam sistim feodal. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah
Hindia Belanda mengenai pendidikan bagi kaum
bangsawan di Indonesia pada masa kolonial Belanda di
Indonesia tahun 1900-1920.Sejak kedatangan Belanda sebagai penguasa
politik di kepulauan Nusantara, berbagai kebijakan
sebagai wujud bentuk imperialisme modern
menampakkan dirinya sebagai kesatupaduan dalam
seluruh aktivitas kolonial yang selalu berupaya
menguasai seluruh wilayah kolonialnya secara sungguh- sungguh. Hasrat pemerintah kolonial Hindia Belanda
untuk mengekspolitasi daerah jajahan membutuhkan
sumber daya manusia yang terdidik. Oleh karena itu,
timbul kebijakan dan usaha pemerintah kolonial untuk
memperluas pendidikan dalam rangka menciptakan
tenaga-tenaga kerja murah yang terdidik. Dengan
semakin pesatnya perkembangan perekonomian Barat
yang ada di Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda
terpaksa menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat
Bumiputera yang bertujuan untuk mendidik tenaga
terampil yang dapat dipekerjakan pada perusahaan dan
berbagai bidang lainnya.
Pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan politik
di negeri Belanda yang sangat berpengaruh pada politik
pemerintahan Belanda di Indonesia. Perubahan politik ini
memberi angin segar bagi peningkatan kesejahteraan
orang pribumi sebagai tanggung jawab moral dari
pemerintah kolonial Belanda terhadap orang-orang
pribumi. Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh
seorang berkebangsaan Belanda, Van Deventer berjudul
“Hutang Kehormatan” (Een Eereschuld) dalam majalah
De Gids, yang berisi kerisauan kaum intelektual Belanda
terhadap humanisasi Hindia Belanda yang telah
terpengaruh kapitalisme. Munculnya artikel tersebut
memicu perubahan yang sangat drastis pada kebijakan- kebijakan pemerintah Belanda terhadap penduduk
jajahan di Hindia Belanda, yaitu dengan dicanangkannya
politik etis atau politik balas budi secara resmi pada
tahun 1901 oleh Ratu Belanda (Niel, 1997:48).
Seiring dengan kebijakan politik etis, dalam
kurun waktu 1900-1940 menunjukkan secara jelas bahwa
sejak abad ke-20 telah terjadi arus balik dari pendidikan
yang elitis menuju pendidikan yang lebih populis.
Kebijakan pendidikan diarahkan pada pemberian
kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat jajahan,
sehingga perluasan besar-besaran jumlah sekolah
dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pembukaan sekolah
tersebut kemudian juga membuka peluang untuk
pembukaan sekolah-sekolah guru untuk penyediaan guru
(Sumarsono, 1996: 60).
Pemerintah kolonial Belanda memiliki landasan
prinsip pendidikan dimana pemerintah berusaha untuk
tidak memihak salah satu agama tertentu, tidak
diusahakan untuk hidup selaras dengan lingkungannya
tetapi lebih ditekankan agar anak didik dikemudian hari
dapat mencari pekerjaan demi kepentingan kolonial.
Sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan
lapisan sosial yang ada dalam masyarakat pribumi. Pada
umumnya pendidikan diukur dan diarahkan untuk
membentuk golongan elit sosial agar dapat dipakai
sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi
politik dan ekonomi Belanda di Indonesia. Pembukaan
sekolah pribumi dilakukan hanya sebatas kebutuhan
praktis pemerintah Belanda. Sistem pendidikan yang
dijalankan pun bersifat dualistis, dimana terdapat garis
pemisah yang tajam antara dua subsistem, sistem sekolah
Eropa dan sistem sekolah pribumi (Sumarsono 1996:93).
Secara teoritis tujuan pendirian persekolahan
sangat baik, namun dalam prakteknya meskipun tidak
secara langsung terdapat kecenderungan diskriminatifdan materialistis. Kecenderungan ini nampak dalam hal
cara penyaringan anak sekolah. Caranya adalah dengan
memberlakukannya biaya sekolah yang cukup mahal dan
sering juga diutamakan bagi keluarga yang memiliki
darah priyayi (pangreh praja atau pegawai dalam kantor
pemerintahan Belanda). Pihak Belanda sangat berhati- hati dalam memberikan pendidikan agar dapat
memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka
yaitu untuk menghasilkan tenaga pekerja yang sangat
dibutuhkan, namun di sisi lain tidak membahayakan bagi
kedudukan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam
memberikan kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat
jajahannya tidak disia-siakan oleh bangsa pribumi,
walaupun Belanda hanya sebatas mendirikan sekolah
rendah atau sekolah dasar membuat seluruh lapisan
masyarakat pribumi ingin memperoleh kesempatan
belajar, yang kemudian memaksa pemerintah Hindia
Belanda untuk memperbanyak pendirian sekolah dasar
tersebut. Lulusan dari pendidikan Belanda diharapkan
untuk menjadi tenaga administrasi pertanian dan industri
sebagai tenaga pekerja kelas dua dengan upah rendah.
Tidak ada diantara rakyat Bumiputera yang menduduki
posisi jabatan tinggi, mereka hanya menduduki jabatan
rendahan yang tidak mempunyai wewenang dan
pengaruh pada jabatannya.dan materialistis. Kecenderungan ini nampak dalam hal
cara penyaringan anak sekolah. Caranya adalah dengan
memberlakukannya biaya sekolah yang cukup mahal dan
sering juga diutamakan bagi keluarga yang memiliki
darah priyayi (pangreh praja atau pegawai dalam kantor
pemerintahan Belanda). Pihak Belanda sangat berhati- hati dalam memberikan pendidikan agar dapat
memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka
yaitu untuk menghasilkan tenaga pekerja yang sangat
dibutuhkan, namun di sisi lain tidak membahayakan bagi
kedudukan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam
memberikan kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat
jajahannya tidak disia-siakan oleh bangsa pribumi,
walaupun Belanda hanya sebatas mendirikan sekolah
rendah atau sekolah dasar membuat seluruh lapisan
masyarakat pribumi ingin memperoleh kesempatan
belajar, yang kemudian memaksa pemerintah Hindia
Belanda untuk memperbanyak pendirian sekolah dasar
tersebut. Lulusan dari pendidikan Belanda diharapkan
untuk menjadi tenaga administrasi pertanian dan industri
sebagai tenaga pekerja kelas dua dengan upah rendah.
Tidak ada diantara rakyat Bumiputera yang menduduki
posisi jabatan tinggi, mereka hanya menduduki jabatan
rendahan yang tidak mempunyai wewenang dan
pengaruh pada jabatannya.dan materialistis. Kecenderungan ini nampak dalam hal
cara penyaringan anak sekolah. Caranya adalah dengan
memberlakukannya biaya sekolah yang cukup mahal dan
sering juga diutamakan bagi keluarga yang memiliki
darah priyayi (pangreh praja atau pegawai dalam kantor
pemerintahan Belanda). Pihak Belanda sangat berhati- hati dalam memberikan pendidikan agar dapat
memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan mereka
yaitu untuk menghasilkan tenaga pekerja yang sangat
dibutuhkan, namun di sisi lain tidak membahayakan bagi
kedudukan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam
memberikan kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat
jajahannya tidak disia-siakan oleh bangsa pribumi,
walaupun Belanda hanya sebatas mendirikan sekolah
rendah atau sekolah dasar membuat seluruh lapisan
masyarakat pribumi ingin memperoleh kesempatan
belajar, yang kemudian memaksa pemerintah Hindia
Belanda untuk memperbanyak pendirian sekolah dasar
tersebut. Lulusan dari pendidikan Belanda diharapkan
untuk menjadi tenaga administrasi pertanian dan industri
sebagai tenaga pekerja kelas dua dengan upah rendah.
Tidak ada diantara rakyat Bumiputera yang menduduki
posisi jabatan tinggi, mereka hanya menduduki jabatan
rendahan yang tidak mempunyai wewenang dan
pengaruh pada jabatannya.Politik etis dalam bidang pendidikan yang
bertujuan menyejahterakan dan meningkatkan
kecerdasan dan perbaikan hidup rakyat jajahan hanyalah
kebohongan belaka. Diskriminasi yang dilakukan oleh
pemerintah Belanda adalah diskriminasi sosial.
Diskriminasi sosial ini terlihat dari didirikannya sekolah
yang membedakan antara sekolah yang dikhususkan bagi
kaum bangsawan dan sekolah untuk rakyat biasa.
Sekolah yang diperuntukkan bagi anak Bumiputera tidak
direncanakan secara sistematis, segalanya berjalan
berdasarkan keadaan zaman, kebutuhan dan kehendak
kolonial. Tidak adanya persekolahan yang tetap dan
selalu dengan ketidak stabilan dengan berbagai
perubahan di dalamnya sehingga terkesan bahwa
pemerintah Belanda tidak memiliki keseriusan dalam
menangani masalah pendidikan bagi bangsa Bumiputera,
segalanya hanya sebagai percobaan dalam pemenuhan
kebutuhan kepentingan Belanda.
Dalam suatu proses pendidikan pemerintah
kolonial menggunakan kriteria tertentu agar memberikan
hasil dan pencapaian yang baik dan sesuai dengan
harapan dari pihak Belanda, sehingga menimbulkan
berbagai kebijakan dalam pendidikan. Salah satunya
kebijakan gradualisme dima untuk penyediaan
pendidikan bagi anak-anak Indonesia, Belanda
membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang
hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki,
pendidikan tidak terlalu diperhatikan. Kebijakan lain
adalah Dualisme yang diartikan berlaku dua sistem bagi
golongan penduduk dan pendidikan dibuat terpisah.
Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua
tidak mempunyai pengaruh langsung pada politik
pendidikan. Pendidikan didirikan dengan tujuan untuk
merekrut pegawai sebagai tenaga kerja yang murah.
Selain itu, adanya prinsip konkordasi menyebabkan anak
Indonesia tidak berhak bersekolah di pendidikan Belanda
(Nasution. 1997:20).
Dalam pelaksanaan implementasi pendidikan,
kebijakan pemerintah kolonial Belanda selalu
berorientasi kepada menggolongkan stratifikasi
masyarakat sesuai keturunan atau status sosial, anak
didik diciptakan untuk dapat mencari pekerjaan demi
kepentingan kolonial, sistem persekolahan disusun
menurut adanya perbedaan sosial yang ada dalam
masyarakat Indonesia, pembukaan sekolah-sekolah
didasarkan akan kebutuhan pemerintah kolonial atau
pengusaha bukannya kebutuhan rakyat pribumi
(Sumarsono 1996:87).
Sekolah-sekolah yang dapat ditempuh oleh
anak-anak keturunan bangsawan di Indonesia pada masa
politik etis adalah ELS, HBS, HIS dan OSVIA. ELS
(Europese Lagere School) merupakan Sekolah Dasar
pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. ELS
menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda yang
dapat dimasuki oleh anak-anak keturunan Belanda dan
anak-anak golongan bangsawan (anak raja) dengan lama
belajar 7 tahun. ELS mulai berdiri pada tahun 1817 di
Batavia (Jakarta). Nama Europese Lagere School sendiri
baru dipakai pada tahun 1902 sebagai pengganti nama
Onderwijs een Lagere School voor Europeanen.Sebelum masuk ELS terdapat sekolah Taman
Kanak-Kanak (Frobel). Selain itu juga ada sekolah
untuk persiapan memasuki ELS (Europese Lagere
School) bagi anak-anak bukan keturunan Eropa, agar
anak-anak tersebut mendapat pelatihan berbicara Bahasa
Belanda, sehingga pada saat masuk ELS mereka sudah
mampu mengikuti kelas satu ELS yang menggunakan
pengatar Bahasa Belanda. Batas usia masuk ELS anatara
6 sampai 16 tahun, tetapi khusus untuk anak Eropa dan
anak-anak dari perkawinan campuran wanita Eropa
dengan laki-laki Bumiputera dapat memasuki ELS
sebelum usia 6 tahun, sedangkan anak-anak Bumiputera
yang akan menjadi murid di ELS harus cukup usianya
dan masih akan diseleksi. ELS sedianya diperuntukkan
bagi orang Eropa dan mereka yang disamakan statusnya
kemudian dirumuskan sebagai sekolah untuk pendidikan
Eropa yang membuka jalan bagi anak bumiputera untuk
memasukinya. Anak-anak Indonesia tidak ditolak,
selama jumlah anak bumiputera dalam jumlah yang
kecil. Bahkan dianggap penting menerima anak-anak
aristokrasi memasuki ELS untuk mempererat hubungan
antar kedua bangsa. Akan tetapi penambahan anak
bumiputera yang di luar batas dirasakan sebagai ancaman
dan banyak alasan yang dikemukakan untuk membatasi
penambahan penerimaan anak bumiputera selanjutnya.
Berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda
dalam membatasi jumlah anak Bumiputera yang semakin
meningkat dalam memasuki sekolah ELS adalah seperti
anak Indonesia tidak boleh melebihi usia 7 tahun agar
dapat diterima (ini tidak berlaku bagi anak Belanda),
penerimaan anak bukan keturunan Belanda jangan
menyebabkan ditolaknya penerimaan anak keturunan
Belanda karena kekurangan tempat, untuk bumiputera
dikenakan pembayaran uang sekolah yang lebih mahal,
anak bumiputera tidak boleh tinggal di kelas yang sama
lebih dari dua tahun (Nasution, 1997:100).Proses penerimaan murid di ELS
mempertimbangkan kedudukan orang tuanya, murid
yang diperbolehkan memasuki ELS merupakan anak- anak dari keturunan bangsawan (priyayi). Maka dari data
tersebut di atas merupakan jumlah keseluruhan anak
bangsawan yang masuk ke ELS. Kurikulum yang
diberlakukan untuk ELS sebenarnya telah ditentukan
pada peraturan tahun 1893 yang terdiri atas mata
pelajaran membaca dan menulis dalam bahasa daerah,
huruf daerah dan latin, membaca dan menulis dalam
Bahasa Melayu, berhitung, ilmu bumi Indonesia, ilmu
alam, sejarah pulau tempat tinggal, mengukur tanah,
menggambar dan semua pelajaran yang diajarkan di
Sekolah Guru kecuali ilmu mendidik boleh diajarkan
setelah mendapat persetujuan dari inspektur atau
pemimpin sekolah tersebut. Namun setelah memasuki
abad ke-20 pemerintah mulai mengembangkan sistem
pendidikan di ELS dengan menyetujui penyebaran
Bahasa Belanda dikalangan penduduk bumiputera
terutama penyebaran dalam sistem pengajaran di sekolah
ELS, dengan memberlakukan Bahasa Belanda sebagai
mata pelajaran pokok. Dalam penyediaan tenaga
pengajar dipilih guru-guru yang langsung didatangkan
dari negeri Belanda. Pada tahun 1912 ELS mendapatkan
kesulitan dalam penyediaan guru yang dapat berbahasa
Belanda, untuk itu pemerintah Belanda mengambil
keputusan untuk melatih calon-calon guru dari penduduk
Bumiputera yang nantinya akan dipekerjakan sebagai
guru bantu di ELS.
Selama beberapa dekade ELS merupakan satu- satunya sekolah yang memberi persiapan untuk ujian
pegawai rendah (Klein Ambtenaar) dan untuk melajutkan
pelajaran ke HBS (Hogere Burger School) dan
seterusnya ke Sekolah Dokter Djawa dan OSVIA
(sekolah pamong praja). ELS memberi jalan yang lebih
terjamin dan pendek untuk kelanjutan pelajaran. Secara
kualitas ELS selalu lebih tinggi daripada HIS dalam
kenyataan pendidikan dan juga dalam mata para majikan.
Standar akademis ELS sama dengan yang ada di
Nederland, penguasaan bahasa Belanda jauh lebih tinggi
karena banyak kesempatan menggunakannya dalam
pergaulan antar murid. ELS adalah sekolah elit yang
memberi prestis tinggi kepada anak dan orang tua. Demi
itu orang tua anak Indonesia rela memberi pengorbanan
finansial yang sebenarnya beban yang telampau berat
untuk dipikul (Nasution. 1997:102-103).
Selain ELS (Europese Lagere School), terdapat
juga HBS (Hogere Burger School) yang merupakan
sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman Hindia
Belanda bagi orang Eropa dan bagi golongan elit
Bumiputera. Pada awalnya HBS bernama sekolah
Gymnasium dengan masa belajar 3 tahun kemudian pada
tahun 1867 nama Gymnasium diubah menjadi HBS
(Hogere Burger School) dengan lama belajar 5 tahun.
Pada tahun 1864 didirikan HBS pertama di Batavia, 1875
di Surabaya, 1877 di Semarang. HBS sedianya
diperuntukkan bagi murid-murid Belanda dan golongan
yang sanggup menyekolahkan anaknya ke ELS yang
mengajarkan Bahasa Perancis sebagai syarat masuk
HBS. Selama hampir seperempat abad HBS tidak
menerima murid wanita. Faktor-faktor yang
menyebabkan kecilnya jumlah murid Bumiputera antaralain sulitnya bagi anak Indonesia memasuki ELS “Kelas
Satu” untuk memperlajari Bahasa Perancis dan
ketidaksanggupan membayar tingginya uang sekolah
sebesar f-15.
HBS (Hogere Burger School) adalah satu- satunya sekolah yang dapat melanjutkan ke perguruan
negeri Belanda. Kurikulum yang diberikan tidak berbeda
dengan kurikulum yang ada di negeri Belanda tanpa ada
perubahan dan dapat bertahan dari berbagai kritik, mata
pelajaran yang diajarkan pun bersifat universal.
Kurikulum yang diberikan di sekolah HBS sifatnya
sangat seragam bagi semua. Kurikulumnya semata-mata
mengikuti yang ada di Nederland dengan tidak
menghiraukan keadaaan di Indonesia. Untuk periode
lebih dari setengah abad sekolah inilah satu-satunya yang
memberikan jalan menuju ke perguruan tinggi di
Belanda. Memasuki HBS dengan hasil yang baik
merupakan kebanggaan tersendiri dimata masyarakat.HIS (Hollands Inlandse School) merupakan
Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas
anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah
keinginan yang kuat dari kalangan orang Indonesia untuk
memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.
Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan
keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan
bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah
pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang
tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta.
Ada pula yang merasa keberatan karena adanya
pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk
menyelenggarakan sekolah ini sehingga menguranggi
anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula
yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang
terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda.
Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu
dan pada tahun 1914 telah resmi bernama Hollands
Inlandse School. Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum
HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas
satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis
bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam
tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak
meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah
dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi
dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang
kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan
untuk menguasai keterampilan membaca yang pada
umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa
daerah, Melayu dan Bahasa Belanda. Mata pelajaran
yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini
meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran. Mata
pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa
ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian
pegawai rendah (Klein Ambtenaar Examen), ini
merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun
kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan
kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi
disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari
merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda
yang memandang Indonesia dari segi pandangnya
sendiri.
Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental
dengan unsur-unsur ke-Belandaan. HIS merupakan
lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat,
khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa
Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh
pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk
kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan
pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bisa
membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit
intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda
dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena
sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang
senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru
Indonesia lulusan dari HKS (Hogere Kweek School).
Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang
mempunyai Hoofdacte atau ijazah Kepala Sekolah, akan
tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah
apabila memiliki H.A (Hoofdacte).
Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS
dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan
pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan
sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang
termasuk golongan atas tersebut karena dalam
pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak
mencukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun
secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS,
akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai.
Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka
golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan
banyak diantara mereka yang berbakat intelektual
kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari
pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan
pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh
pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni
keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Dengan
demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak
yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau
anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal f. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan
tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka
kesempatan bagi golongan swasta dan yang
berpenghasilan rendah.HIS (Hollands Inlandse School) merupakan
Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas
anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah
keinginan yang kuat dari kalangan orang Indonesia untuk
memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.
Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan
keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan
bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah
pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang
tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta.
Ada pula yang merasa keberatan karena adanya
pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk
menyelenggarakan sekolah ini sehingga menguranggi
anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula
yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang
terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda.
Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu
dan pada tahun 1914 telah resmi bernama Hollands
Inlandse School. Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum
HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas
satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis
bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam
tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak
meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah
dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi
dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang
kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan
untuk menguasai keterampilan membaca yang pada
umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa
daerah, Melayu dan Bahasa Belanda. Mata pelajaran
yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini
meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran. Mata
pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa
ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian
pegawai rendah (Klein Ambtenaar Examen), ini
merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun
kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan
kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi
disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari
merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda
yang memandang Indonesia dari segi pandangnya
sendiri.
Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental
dengan unsur-unsur ke-Belandaan. HIS merupakan
lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat,
khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa
Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh
pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk
kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan
pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bisa
membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit
intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda
dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena
sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang
senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru
Indonesia lulusan dari HKS (Hogere Kweek School).
Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang
mempunyai Hoofdacte atau ijazah Kepala Sekolah, akan
tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah
apabila memiliki H.A (Hoofdacte).
Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS
dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan
pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan
sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang
termasuk golongan atas tersebut karena dalam
pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak
mencukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun
secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS,
akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai.
Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka
golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan
banyak diantara mereka yang berbakat intelektual
kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari
pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan
pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh
pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni
keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Dengan
demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak
yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau
anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal f. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan
tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka
kesempatan bagi golongan swasta dan yang
berpenghasilan rendah.HIS (Hollands Inlandse School) merupakan
Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas
anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah
keinginan yang kuat dari kalangan orang Indonesia untuk
memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.
Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan
keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan
bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah
pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang
tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta.
Ada pula yang merasa keberatan karena adanya
pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk
menyelenggarakan sekolah ini sehingga menguranggi
anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula
yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang
terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda.
Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu
dan pada tahun 1914 telah resmi bernama Hollands
Inlandse School. Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum
HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas
satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis
bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam
tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak
meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah
dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi
dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang
kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan
untuk menguasai keterampilan membaca yang pada
umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa
daerah, Melayu dan Bahasa Belanda. Mata pelajaran
yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini
meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran. Mata
pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa
ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian
pegawai rendah (Klein Ambtenaar Examen), ini
merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun
kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan
kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi
disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari
merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda
yang memandang Indonesia dari segi pandangnya
sendiri.
Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental
dengan unsur-unsur ke-Belandaan. HIS merupakan
lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat,
khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa
Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh
pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk
kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan
pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bisa
membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit
intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda
dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena
sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang
senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru
Indonesia lulusan dari HKS (Hogere Kweek School).
Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang
mempunyai Hoofdacte atau ijazah Kepala Sekolah, akan
tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah
apabila memiliki H.A (Hoofdacte).
Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS
dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan
pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan
sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang
termasuk golongan atas tersebut karena dalam
pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak
mencukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun
secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS,
akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai.
Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka
golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan
banyak diantara mereka yang berbakat intelektual
kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari
pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan
pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh
pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni
keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Dengan
demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak
yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau
anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal f. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan
tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka
kesempatan bagi golongan swasta dan yang
berpenghasilan rendah.HIS (Hollands Inlandse School) merupakan
Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas
anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah
keinginan yang kuat dari kalangan orang Indonesia untuk
memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.
Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan
keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan
bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah
pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang
tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta.
Ada pula yang merasa keberatan karena adanya
pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk
menyelenggarakan sekolah ini sehingga menguranggi
anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula
yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang
terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda.
Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu
dan pada tahun 1914 telah resmi bernama Hollands
Inlandse School. Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum
HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas
satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis
bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam
tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak
meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah
dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi
dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang
kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan
untuk menguasai keterampilan membaca yang pada
umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa
daerah, Melayu dan Bahasa Belanda. Mata pelajaran
yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini
meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran. Mata
pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa
ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian
pegawai rendah (Klein Ambtenaar Examen), ini
merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun
kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan dengan
kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi
disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari
merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda
yang memandang Indonesia dari segi pandangnya
sendiri.
Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental
dengan unsur-unsur ke-Belandaan. HIS merupakan
lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat,
khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa
Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh
pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk
kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan
pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bisa
membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit
intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda
dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena
sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang
senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru
Indonesia lulusan dari HKS (Hogere Kweek School).
Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang
mempunyai Hoofdacte atau ijazah Kepala Sekolah, akan
tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah
apabila memiliki H.A (Hoofdacte).
Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS
dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan
pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan
sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang
termasuk golongan atas tersebut karena dalam
pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak
mencukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun
secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS,
akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai.
Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka
golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan
banyak diantara mereka yang berbakat intelektual
kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari
pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan
pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh
pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni
keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Dengan
demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak
yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau
anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal f. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan
tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka
kesempatan bagi golongan swasta dan yang
berpenghasilan rendah.Pada tahun 1916 populasi HIS seluruhnya
berjumlah 20.737 diantaranya 3.338 atau 16% anak
wanita dan kebanyakan dari golongan atas. Di Jawa
maupun di pulau-pulau lain, kebanyakan gadis adalah
anak pegawai. Di Jawa 77,7% anak wanita berasal dari
golongan bangsawan dan di luar Jawa 59,1%. Pegawai
pemerintah yang telah menerima pendidikan Barat,
rupanya progresif dalam sikapnya untuk menyekolahkan
anak-anak gadisnya.
OSVIA merupakan Sekolah Dasar yang
disediakan bagi anak-anak golongan bangsawan. Sekolah
ini pada mulanya didirikan di Tondano (1865-1872
sebagai percobaan) dan di Bandung, Magelang, dan
Probolinggo (1878) yang dalam bahasa sehari-hari
disebut Sekolah Raja (Hoofdenschool) dengan bahasa
pengantar Bahasa Melayu dan Bahasa Belanda, dan
dimaksudkan untuk kepentingan administrasi
pemerintahan Hindia Belanda bagi anak-anak tokoh
terkemuka Bumiputera. Tetapi sekolah raja tersebut
kemudian diintegrasikan ke ELS atau HIS. Pada tahun
1900 Sekolah Raja tersebut mengalami reorganisasi dan
diberi nama OSVIA. Masalah keturunan merupakan
faktor yang sangat penting dalam penerimaan murid di
OSVIA. Meskipun uang pembayaran sekolah
disesuaikan dengan penghasilan orang tua, bagi keluarga
berpenghasilan rendah yang meyekolahkan anaknya di
OSVIA biaya tersebut dirasakan sangat mahal.
Penerimaan siswa sering harus disertai surat
rekomendasi pribadi pejabat Binenlandsch Bestuur (BB)
dan para bupati. Sedangkan bupati-bupati tersebut
menggunakan haknya untuk mengajukan sanak
saudaranya dan orang-orang yang disukainya. Tingkat
lanjutan dari sekolah OSVIA adalah MOSVIA atau
Middelbare Opleiding voor Indische Ambtenaren
(setingkat SMTA).
Pada dasarnya lembaga-lembaga pendidikan
yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda selalu
mengalami perkembangan jumlah setiap tahunnya begitu
pula dengan jumlah murid yang memasuki sekolah- sekolah tersebut. kebijakan pendidikan yang dijalankan
oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap keturunan
Bumiputera sangatlah tidak efisien. Keadaan seperti ini
memang sengaja diciptakan dikarenakan pemerintah
Hindia Belanda berkeinginan agar orang-orang
Bumiputera tidak menduduki jabatan penting dalam
pemerintahan. Jadi kebijakan pendidikan bagi rakyat
Bumiputera diselenggarakan secara sederhana dan
kurang efisien karena pendidikan yang diberikan kepeda
rakyat jajahan hanya sebagai pemenuh kebutuhan
kepentingan kolonial bukanlah untuk mencerdaskan dan
meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pribumi.
KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan tentang Kebijakan
Pemerintah Hindia Belanda Mengenai Pendidikan Bagi
Kaum Bangsawan Di Indonesia Tahun 1900-1920, dapat
diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah Hindia Belanda
dalam melaksanakan kebijakan dalam bidang pendidikan
bagi kaum bangsawan di Indonesia dalam bentuk
mendirikan lembaga-lembaga sekolah, yaitu: Europese
Lagere School (ELS), Hogere Burger School (HBS), Hollands Inlandse School (HIS), Opleiding School voor
Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). Kebijakan pemerintah
Hindia Belanda khususnya mengenai pendidikan lebih
diutamakan bagi para kaum bangsawan Bumiputera
dengan tujuan Pemerintah Hindia Belanda ingin
menciptakan kelompok elite yang terpisah dengan
masyarakatnya sendiri. Para kaum bangsawan ini
diharapkan oleh pemerintah Hindia Belanda agar
menjadi pemimpin yang berjiwa kebarat-baratan yang
akan digunakan sebagai alat oleh Pemerintah Hindia
Belanda untuk melangsungkan penjajahannya di
Indonesia.









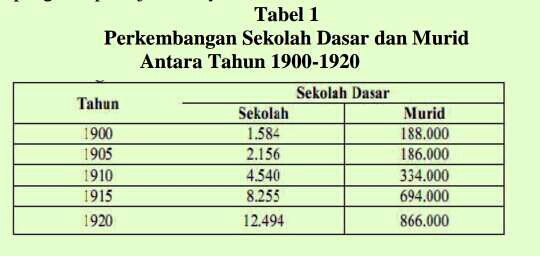





.jpg)









