Rabu, 19 Juli 2023
Home »
raja majapahit. 1
» raja majapahit 1
raja majapahit 1
By Lampux.blogspot.com Juli 19, 2023
pelaut-pelaut Nusantara telah menguasai perairan dan tampil sebagai penjelajah samudera sejak 1.500 tahun
lampau. Ini jauh sebelum Cheng Ho dan Colombus membuat sejarah pelayaran fenomenal. Para penjelajah
laut Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia, bahkan sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke
tanah air pada paruh pertama abad 16.
Sejak abad ke-9 Masehi, bangsa Indonesia yang dikenal sebagai penjelajah Nusantara telah berlayar
mengarungi lautan ke barat Samudera Hindia hingga Madagaskar dan ke timur hingga Pulau Paskah. Ini menjadi
bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki peradaban dan budaya maritim yang maju sejak dulu kala. Seiring
semakin ramainya aktivitas melalui laut, lahirlah kerajaan-kerajaan bercorak maritim dan memiliki armada laut besar.
Perkembangan budaya maritim pun membentuk peradaban bangsa yang maju di zamannya.
Puncak kejayaan maritim nusantara terjadi pada masa Kerajaan Majapahit
(1293-1478).Di bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada,
Majapahit berhasil menguasai dan mempersatukan nusantara. Pengaruhnya
bahkan sampai ke negara-negara asing, seperti Siam, Ayuthia, Lagor, Campa
(Kamboja), Anam, India, Filipina, China.Di jaman Majapahit dulu, Hayam Wuruk, ‘Ayam yang pandai’, berhasil memerintah dan menguasai seluruh
Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, sebagai bangsa yang berdaulat. Majapahit di bawah Hayam Wuruk adalah
kerajaan maritim yang jaya, merupakan kekuasaan besar di Asia Tenggara, sekaligus pengganti dua kerajaan besar
sebelumnya, Mataram – kerajaan pertanian, dan Sriwijaya – kerajaan maritim.
Keberhasilan Majapahit dalam mengembangkan teknologi bahari dengan membangun kapal bercadik menjadi
tumpuan utama kekuatan armada lautnya. Di relief candi Borobudur kita dapat melihat pahatan kapal ini yang
dibangun dengan pasak kayu, tanpa menggunakan paku. Layarnya terbuat dari tanaman yang dianyam yang mudah
digerakkan sesuai arah angin, sehingga laju kapal dapat bergerak lincah sesuai tujuan.Armada laut Majapahit juga
didukung oleh persenjataan meriam
hasil rampasan dari bala tentara
Kubilai Khan ketika menyerang
Kediri. Kapal-kapal Jawa berukuran
raksasa dengan tiga-empat layar ini
dikagumi dan dipuji kehebatannya
oleh para penjelajah dunia di abad
ke-14. Kapal raksasa dengan panjang
70 meter dan berat lebih dari 500 ton
ini mampu memuat 600 penumpang.
Jumlah armada ketika itu mencapai
angka yang fantastis, 400 kapal. Bisa
dibayangkan betapa sudah majunya
teknologi perkapalan waktu itu.
Nusantara di bawah Majapahit tujuh
abad yang lalu!
Dalam buku Da Asia yang ditulis
oleh Diego de Couto disebutkan
bahwa orang Jawalah yang terlebih
dulu berlayar sampai ke Tanjung
Harapan, Afrika, dan Madagaskar.
Banyak penduduk keturunan Jawa
yang tinggal di Tanjung Harapan di
awal abad ke-16, sampai sekarangDi tahun 1500, pelaut Portugis juga menemukan Kapal dagang milik
orang Jawa di perairan Asia Tenggara. Kota pelabuhan Malaka pada waktu
itu praktis menjadi kota orang Jawa. Banyak tukang kayu Jawa yang terampil
membangun galangan kapal di kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Juga
banyak saudagar dan nakoda kapal Jawa yang menetap di sana. Merekalah
yang menguasai jalur rempah-rempah yang sangat vital antara Maluku, Jawa,
dan Malaka, sekaligus mengendalikan perdagangan internasional.Hubungan dagang yang telah terajut pada abad ke-13 antara Kerajaan Ryu
Kyu yang terletak di Pulau Okinawa, Jepang bagian selatan dengan Kerajaan
Majapahit dibuktikan dengan penemuan sebilah keris purba di sebuah kuil
purba “Enkakuji Temple”di dasar lautan Pulau Okinawa.
Hubungan lainnya juga terjalin antara Kerajaan Majapahit dengan masyarakat Okinawa, Jepang, yang dahulu
bernama Ryukyu, pada abad ke 15. Diketahui, Masyarakat Okinawa melakukan kunjungan ke Majapahit sebanyak
sembilan kali. Sementara Majapahit berkunjung ke Jepang sebanyak lima kali.
Saat itu hubungan dagang Kerajaan Majapahit dan masyarakat Okinawa sangat baik. Masyarakat Okinawa membeli
rempah-rempah dari Majapahit, sementara masyarakat kerajaan Majapahit membeli barang barang seperti keramik dari
Okinawa.•
L
etak geografis Indonesia sangat strategis, karena diapit dua benua
dan dua samudera. Sebagian besar luas wilayah Indonesia terdiri
dari lautan, perbandingannya adalah duapertiga berupa lautan dan
hanya sepertiga wilayah yang berbentuk daratan. Dengan kondisi
geografis seperti ini, maka sudah sepantasnya bagi Indonesia
berfokus pada pengembangan wilayah maritim ketimbang daratan.
Atas alasan itu juga, Presiden Joko Widodo mengeluarkan doktrin
mengenai peran Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lima pilar utama
poros maritim itu bahkan secara gamblang beliau beberkan dalam pidato di
forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar, pada
November 2014 lalu.
Berikut uraian agenda Presiden Jokowi yang akan menjadi fokus Indonesia
di abad ke-21. Dengan agenda ini, diharapkan Indonesia akan menjadi Poros
Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa
bahari yang sejahtera dan berwibawa.
1. Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia
Membangun kembali budaya maritim Indonesia berangkat dari kesadaran
bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17 ribu
pulau. Artinya, penanaman identitas sebagai negara maritim perlu dilakukan
agar setiap generasi bangsa sadar bahwa maritim adalah identitas bangsa.
Sehingga alur pikiran masyarakat tertanam bahwa kemakmuran bangsa sangat
bergantung dengan pengelolaan samudera yang mengapit negeri.
2. Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Laut
Kedaulatan pangan dari hasil laut menjadi fokus agenda ini. Industri sektor
perikanan menjadi penting untuk dimaksimalkan demi kemakmuran rakyat,
tapi di satu sisi tetap menjadikan nelayan sebagai pilar utama dalam agenda.
Dalam agenda ini, Jokowi menggarisbawahi agar kekayaan maritim digunakan
sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia
3. Pengembangan Infrastruktur Dan Konektivitas Maritim
Konektivitas antar pulau menjadi fokus dalam visi negara maritim. Namun konektivitas ini bukan berarti setiap
pulau harus terhubung dengan jembatan. Tapi dengan infrastruktur yang menunjang bagi berlabuhnya kapal-kapal ke
semua pulau yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, konektivitas dan infrastruktur juga diharapkan bisa menambah
devisa bagi daerah-daerah di kepulauan.
Sehingga, pembangunan tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim menjadi
prioritas agenda ini.
E
kspedisi Spirit of Majapahit secara resmi diluncurkan pada
tanggal 2 Mei 2016. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Rizal Ramli secara resmi meluncurkan ekspedisi kapal replika
Majapahit itu berlayar ke Okinawa, Jepang. Acara peluncuran
ekspedisi itu turut dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk
Indonesia Tanizaki Yasuaki, serta General Secretary Majapahit Admiration
Community Takajo Yoshiaki.
Dalam sambutan pelepasan tersebut, Menko Rizal mengatakan
bahwa ‘Ekspedisi Spirit of Majapahit 2016’ merupakan bagian dari misi
untuk mengangkat serta melestarikan nilai- nilai sejarah dan budaya
maritim Indonesia. Melalui Ekspedisi Spirit of Majapahit, Menko Rizal
siap membuktikan bahwa Indonesia pernah berjaya di masa lalu melalui
penguasaan laut
S
ebelum membahas Napak Tilas Spirit of Majapahit 2016 menuju Jepang, ada baiknya kita ketahui terlebih
dahulu, di mana kapal Spirit of Majapahit dibuat dan bagaimana proses pembuatannya.
Dalam buku Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17 yang ditulis oleh sejarawan maritim
Indonesia, Adrian B. Lapian dijelaskan “Galangan kapal di Jawa juga terkenal di Asia Tenggara, khususnya
pada abad ke-16 M. Keahlian arsitek kapal di Jawa begitu tersohor sehingga Alfonso D’ Albuquerque,
seorang pelaut Portugis, membawa 60 tukang yang cakap pada waktu ia meninggalkan Malaka pada tahun 1512 M
(Alfonso D’ Albuquerque bersama pasukan Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 M). Pada jaman
Kerajaan Majapahit, Tuban menjadi salah satu pelabuhan ramai. Pasukan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit juga
dipusatkan di Tuban. Hal ini dikarenakan posisi Tuban, dekat dengan Lasem tempat para arsitek dan pembuat kapal
yang hebat saat itu. Di samping itu kayu jati yang dimiliki Rembang (dekat dengan Lasem), memudahkan tersedianya
bahan material untuk membuat kapal atau memperbaiki kapal-kapal yang rusak.
bangunan yang disucikan oleh masyarakat kabuyutan atau
dusun yang mendapatkan hak istimewa berupa
pengurangan pajak ,
4 Suatu daerah yang mendapatkan status sima atau otonomi
mendapatkan hak istimewa berupa pengurangan jumlah
pajak atau bahkan bebas untuk tidak membayar pajak
Majapahit! Siapa yang tidak mengenal kata itu?
Sebagian besar masyarakat Indonesia tentu mengenal kata
Majapahit. Di dalam pelajaran-pelajaran sejak tingkat SD
diajarkan tentang Kerajaan Majapahit yang berpusat di
Trowulan, Kabupaten Mojokerto sekarang, Majapahit
merupakan kerajaan yang pernah menguasai Nusantara,
bahkan juga dikenal di banyak wilayah di Asia Tenggara.
Banyak kearifan yang dapat dipetik dari keberadaan
Majapahit, aspek sosio-politik, budaya, ekonomi, bahkan
hubungan luar negeri.
Selama ini sudah banyak artikel, makalah, dan buku
tentang berbagai aspek kehidupan pada masa naik-puncaksurut Kerajaan Majapahit, namun terbitan yang
memaparkan dan mengupas aspek-aspek tersebut di atas
dalam satu buku yang kompak, menyatu. Dapat dicatat di
antaranya: 700 Tahun Majapahit terbit tahun 1993,
Majapahit. Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota terbit
tahun 2014, Inspirasi Majapahit terbit tahun 2014.
Meskipun demikian masih banyak aspek terkait dengan
Majapahit yang belum digali, apalagi penelitian-penelitian
tentang Majapahit masih terus dilakukan.
Oleh karena itu, buku yang diterbitkan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bekerja
sama dengan Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
dengan judul Sandhyakala ning Majapahit: Pembelajaran
dari pasang surut Kerajaan Majapahit ini menjadi kajian yang penuh makna, mengemukakan yang belum terungkap
mengenai Majapahit. Buku ini terdiri atas empat bagian.
Bagian pertama mengenai “Kejayaan Majapahit”, bagian
kedua mengenai “Pasca Hayam Wuruk”, bagian ketiga
mengenai “Majapahit dari Perspektif Geologi”, dan bagian
keempat mengenai “Bukti Bioarkeologi”. Keempat bagian
tersebut memuat makalah-makalah yang ditulis oleh 14
orang ahli di bidang-bidang tersebut, yang semua
mengungkap aspek-aspek terkait dengan Majapahit.
Makalah-makalah tersebut disajikan dan didiskusikan
dalam Seminar Sandhyakala ning Majapahit pada tanggal 16
November 2019 di Surabaya, yang diselenggarakan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
bekerjasama dengan Museum Etnografi dan Pusat Kajian
Kematian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Airlangga.
Bagian pertama mengenai “Kejayaan Majapahit”
memuat tiga makalah yang ditulis oleh Mimi Savitri dan
Adrian Perkasa serta Sambit Datta. Makalah Mimi Savitri
yang berjudul “Musyawarah pada Masa Majapahit Abad
XIII–XIV M: Bukti Kehidupan Demokratis pada Kerjaan
Jawa” mengemukakan bahwa sejak awal berdiri sampai
menjelang kemunduran Majapahit musyawarah digunakan
oleh raja untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hal ini
diperoleh Mimi Savitri, setelah ia mengkaji beberapa
prasasti masa Majapahit di antaranya prasasti Kudadu,
prasasti Hamad, dan prasasti Bendosari; beberapa naskah
seperti Nagarakertagama, Pararaton, dan Manawa
dharmaçāstra; serta relief pada candi Ampel Gading yang
menggambarkan dewa-dewa bermusyawarah. Data dari berbagai sumber tersebut menurut Mimi Savitri
membuktikan adanya kepemimpinan yang demokratis
pada Kerajaan Majapahit. Pada tataran yang tinggi
musyawarah dipimpin oleh raja, namun semua lapisan
masyarakat dapat melaksanakan musyawarah secara aktif.
Tulisan mengenai sejarah pengungkapan kejayaan
Majapahit dikemukakan oleh Adrian Perkasa dengan judul
“Majapahit di antara Dua Penguasa Kolonial: Inggris dan
Belanda”. Dalam makalah tersebut ia menyajikan sejarah
pengungkapan kejayaan Majapahit, yang diawali oleh
Thomas Stanford Raffles dan dituliskan dalam History of
Java. Sejak diungkap oleh Raffles, Kerajaan Majapahit lalu
mendapat tempat penting dalam pandangan orang-orang
Eropa. Adrian Perkasa juga menggambarkan peran R.T. Ario
Kromo Adinegoro dalam upaya menyingkap sejarah
Majapahit. Diungkap juga tentang Schnitger yang menduga
fragmen arca terakota sebagai potret wajah Gajah Mada.
Menurut pendapatnya karakter wajah arca tersebut penuh
kuasa.
Makalah yang ditulis oleh Sambit Datta dengan
judul ”Evolution and Interconnection: Geometry in Early
Temple Architecture” mengungkap evolusi serta hubungan
antara tradisi membangun kuil/candi di Asia Selatan dan
Asia Tenggara, dengan meneliti candi-candi yang sudah
rusak di India, Kamboja, dan Jawa. Ia mengambil data dari
beberapa kuil/candi, antara lain: kuil-kuil masa Gupta di
India, candi-candi di Dieng dan Gedong Sanga di Jawa, serta
kuil Sambor Prei Kuk di Kamboja. Penelitiannya dilakukan
dengan rekonstruksi digital 3D, menggunakan metode
analisis image based dengan teknik generative modelling. Di sisi lain, dalam teks-teks tentang kuil-kuil India kuno
didapatkan prinsip-prinsip geometris yang didasarkan
pada kitab-kitab suci. Sementara itu, Datta menemukan
bahwa arsitektur candi/kuil di Asia Tenggara
memperlihatkan hubungan inter-Asia, lintas benua, dalam
hal lay-out bentuk, aspek geometri denah, penggunaan atap
bertingkat, elemen-elemen pada pintu masuk candi/kuil,
serta penggunaan ragam-ragam hias yang khas.
Bagian kedua yang diberi judul “Pasca Hayam
Wuruk” berisi empat makalah yang ditulis oleh Edi
Triharyantoro, Agus Aris Munandar, John N.Miksic, dan Sri
Margana. Tulisan Edi Triharyantoro yang berjudul
“Tinggalan Arkeologi. Bukti Kegoncangan Politik Majapahit”
menguraikan artefak-artefak yang berhubungan dengan
keguncangan politik Majapahit. Bangunan-bangunan suci
berundak dan arca-arca dari abad XIII–XIV M yang
menyimpang dari tradisi arsitektur dan ikonografi HinduJawa menurut pendapat Edi membuktikan terjadinya
keguncangan politik, dan memunculkan kembali
kepercayaan asli. Berarti hal tersebut menunjukkan
terjadinya kontra akulturasi dan dinamika keudayaan pada
masa itu.
Agus Aris Munandar dalam makalahnya yang
berjudul “Beberapa Proposisi Keruntuhan Kerajaan
Majapahit” menguraikan perihal keruntuhan Majapahit,
sebab musababnya, dan apa yang dapat dipetik dari
keruntuhan tersebut. Pemakalah menggunakan sumber
terutama berupa karya sastra, karena data arkeologi hanya
berupa sisa kota Majapahit di Trowulan yang sampai
sekarang pun belum dikaji secara komprehensif. Karya sastra yang ditelaahnya adalah: Babad Tanah Jawi karya
R.Ng. Yasadipura, Babad Tanah Galuh–Mataram, Babad
Dalêm Bali, Sêrat Darmogandul, Babad Arung Bondan, dan
Carita Lasêm. Sesudah meninggalnya Rajasanagara (Hayam
Wuruk), Majapahit mengalami kegoncangan-kegoncangan
politik, sampai kehilangan kekuasaan pada tahun 1519 TU,
meskipun ada prasasti dari tahun 1541 fi TU yang
menyebut nama Majapahit. Kerajaan Majapahit runtuh
melalui proses yang panjang, tidak serta merta karena
diserang bala tentara Demak. Ada perang perebutan
kekuasaan yang berkepanjangan, terakhir adalah serangan
Girindrawardana kepada Bhre Kertabumi. Pelajaran yang
dapat dipetik dari keruntuhan Majapahit: negara dapat
bertahan apabila ada dukungan rakyat.
Dalam makalah John N. Miksic yang berjudul
“Majapahit after Hayam Wuruk. Decline or
Transformation?”, ia memulai pembicaraan dengan
menyampaikan bahwa historiografi tradisional Indonesia
menyebutkan bahwa Majapahit runtuh oleh Demak pada
tahun 1400 Ç = 1478 TU. Tetapi Miksic menulis bahwa hal
tersebut tidak sejalan dengan data epigrafi dan beberapa
sumber lain, bahkan potensi Arkeologi tentang hal tersebut
belum digunakan sepenuhnya. Digambarkannya bahwa
kehidupan politik Majapahit memang kacau, tetapi
kehidupan ekonominya masih berjalan lancar, terbukti dari
temuan-temuan keramik impor dari Cina, juga dari
Thailand, Vietnam. Kuantitas dan kualitas keramik Vietnam
dan Thailand yang ditemukan di Trowulan menunjukkan
bahwa Majapahit masih jaya. Fragmen keramik Vietnam,
Cina, bahkan Persia, yang ditemukan menggambarkan relasi yang erat dengan erajaan-kerajaan di wilayahwilayah terseut pada abad XIII – XV M. Miksic juga
menyatakan bahwa raja-raja Majapahit biasa mengirim
utusan kepada kaisar Cina, bahkan sampai tahun 1499 M.
Dalam makalah yang berjudul “Sandhyakala ning
Majapahit. Menurut Babad Jawa” Sri Margana menguraikan
tentang jattuhnya Majapahit, khususnya peran orang-orang
Islam, berdasarkan sumber-sumber utama historiografi
tradisional Jawa. Sumber-sumber yang ditelaahnya adalah
“Babad Tanah Jawi” dari istana Surakarta dan Yogyakarta,
serta ‘Babad Kraton”. Dengan membandingkan narasi
dalam naskah-naskah tersebut, Sri Margana menyampaikan
bahwa naskah-naskah tersebut mempunyai narasi yang
sama tentang latar belakang runtuhnya kerajaan Majapahit,
yaitu lahirnya Patah dan Husen. Namun, setelah itu
narasinya berbeda, sehingga menimbulkan penafsiran yang
berbeda pula.
Bagian ketiga mengenai “Majapahit dari Perspektif
Geologi” berisi dua makalah yang ditulis oleh Amin Widodo
bersama Firman Syaifudin, dan Yahdi Zaim. “Rekonstruksi
Digital Pantai Zaman Majapahit” adalah judul makalah yang
ditulis oleh Amin Widodo bersama Firman Syaifudin.
Mereka menguraikan bahwa suatu kerajaan akan menjadi
kuat dan ideal apabila dapat menguasai seluruh aliran
sungai, sehingga akan menguasai pertanian di pedalaman
dan perdagangan maritime di wilayah muara. Struktur
sedemikian pernah terjadi pada masa pemerintahan
Airlangga, Kertanegara, dan Hayam Wuruk. Pelabuhan
untuk Majapahit diperkirakan berada di area muara Kali
Mas / Kali Surabaya. Pada masa itu sungai tersebut dapat dilayari sampai mendekati pusat kerajaan, yakni di
daerahJapanan. Majapahit sukses dalam memadukan
keunggulan agraris dan memperkuat kekuatan maritime
dengan memanfaatkan sungai Brantas. Para pemakalah
juga mengusulkan ada kolaborasi riset antara Arkeologi
dengan bidang-bidang ilmu lain untuk menentukan garis
pantai pada masa Majapahit.
Pemakalah berikutnya adalah Yahdi Zaim yang
menyampaikan “Adakah Kejayaan Majapahit Pudar Karena
Bencana Alam?” Dalam pemikirannya wilayah Tarik tepat
dipilih sebagai pemukiman pusat pemerintahan Majapahit
karena secara morfologis merupakan dataran yang luas,
dekat aliran Sungai Brantas, sehingga subur. Di samping itu,
juga dekat dengan jalur transportasi air. Kemudian pusat
pemerintahan pindah dari Tarik ke wilayah Trowulan
sekarang. Akan tetapi daerah yang datar, dekat sungai
besar, juga rentan bencana banjir. Di selatan wilayah TarikTrowulan terdapat Gunung Wilis dan Kompleks Kelud yang
berpotensi Meletus dalam kurun waktu Majapahit.
Bencana-bencana alam tersebut berdampak pada
kesejahteraan, kehidupan sosial-ekonomi-psikologi
masyarakat, juga pada keamanan negeri. Hal-hal tersebut
ikut memicu terjadinya gejolak politik yang pada gilirannya
menyebabkan lemahnya Majapahit.
Bagian keempat diberi judul “Bukti Bioarkeologi”
berisi dua makalah, yakni” ditulis oleh Yusuf Bilal Abdillah,
bersama Delta Bayu Murti dan Toetik Koesbardiati; dan
“Kondisi Kesehatan Penduduk Pesisir pada Sekitar Akhir
Masa Majapahit di Caruban, Lasem, Rembang: Bukti-Bukti
Bioarkeologi Maritim” dikemukakan oleh Rusyad Adi Suriyanto dan Ashwin Prayudi. Makalah yang ditulis oleh
Yusuf Bilal Abdillah dengan judul “Similaritas DNA
Mitochondria Masyarakat Tengger dengan Temuan Rangka
Kedaton, Trowulan” tersebut diatas mengemukakan bahwa
sampai sekarang asal usul masyarakat Tengger belum
diketahui. Di sisi lain masyarakat Tengger percaya bahwa
mereka adalah keturunan masyarakat Majapahit yang
terdesak Ketika masa akhir Majapahit, dan mengungsi ke
wilayah Tengger. Tetapi menurut penelitian Glinka dan
Koesbardiati, masyarakat Tengger memiliki ciri
protomalayid yang besar. Oleh karena itu perlu diketahui
similaritas antara variasi haplotype masyarakat Tengger
dengan temuan rangka di Kedaton, Trowulan. Penelitian
tentang hal tersebut dilakukan dengan metode komparatif.
Adapun tujuannya adalah membuktikan asal usul
masyarakat Tengger yang dianggap berasal dari Majapahit.
Perbandingan data sekuens masyarakat Tengger di
Wonokitri dengan temuan rangka di Kedaton menunjukkan
similaritas di antara keduanya. Maka mungkin masyarakat
Majapahit di masa akhirnya bercampur dengan penduduk
asli Tengger.
Makalah berjudul “Kondisi Kesehatan Penduduk
Pesisir pada Sekitar Masa Akhir Majapahit di Caruban,
Lasem, Rembang: Bukti-Bukti Bioarkeologis Maritim” yang
ditulis oleh Rusyad Adi Suriyanto et.al. mengemukakan
bahwa di situs Caruban, Lasem, Rembang. Pada masa
Majapahit, Lasem yang ditetapkan sebagai tanah lungguh
Majapahit juga merupakan bandar yang ramai, serta tempat
membuat kapal-kapal dagang dan kapal perang. Setelah
runtuhnya Majapahit, Lasem berada dalam kekuasaankerajaan Demak. Di situs Caruban yang merupakan situs
peralihan dari masa Klasik menuju masa Islam, ditemukan
tiga rangka manusia. Berdasarkan temuan tersebut, para
penulis meneliti tentang penyakit dan kelainan fisik, serta
pengaruh aktivitas sosial-budaya pada masanya. Rangka I
berjenis kelamin perempuan, berumur sekitar 17 tahun;
rangka II berjenis kelamin laki-laki berumur sekitar 25–30
tahun; rangka III berjenis kelamin perempuan, berumur
sekitar 20 tahun. Ketiganya berafinitas Mongoloid, dan pada
rangka II serta III terdapat jejak mutilasi gigi. Rangkarangka tersebut menunjukkan adanya karies pada gigi
mereka, dan jejak pangur pada gigi. Selain itu, rangka II dan
III menunjukkan adanya tumor jinak. Mereka meninggal
dalam usia remaja awal sampai dewasa tengah, karena
terpapar beragam penyakit. Hal tersebut terkait dengan
dinamika lingkungan dan kebudayaan. Juga karena
persebaran penyakit serta kontak di antara populasi di
wilayah tersebut.
-----
Musyawarah sebagai cara untuk memutuskan
masalah telah dikenal sejak masa awal berdirinya Kerajaan
Majapahit pada abad ke-13. Pada masa itu musyawarah
telah menjadi sebuah cara yang dilakukan oleh menantu
raja untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Hal ini
menarik untuk diteliti, karena pada masa selanjutnya ketika
Kerajaan Majapahit telah berdiri, musyawarah masih tetap
digunakan oleh raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
untuk menyelesaikan permasalahan (Kartodirdjo 1993:37).
Di Jawa, termasuk di Kerajaan Majapahit, raja memiliki
kekuasaan tertinggi dan disamakan dengan dewa. Sebagai
contoh, naskah kesastraan Nagarakertagama pupuh I:3
menyebut Hayam Wuruk sebagai penjelmaan dewa;
prasasti Bendosari atau Manah i Manuk menyebut raja
mereka, Hayam Wuruk, sebagai Iswarapratiwimba atau
penjelmaan Siwa (Savitri 1993:65). Kekuasaan raja yang
sangat tinggi dalam sebuah pemerintahan itu dapat
menjadikan seorang raja memerintah secara mutlak dan
otoriter sebagaimana dijumpai pada negara-negara
kerajaan di Eropa (Moedjanto 1990:5). Namun, hal itu tidak
terjadi pada Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa. Data
prasasti dan naskah kesastraan yang menginformasikan
tentang adanya musyawarah membuktikan bahwa
pemerintahan pada masa Majapahit tidak dijalankan secara mutlak dan otoriter, namun secara demokratis.
Musyawarah sebagai salah satu cara untuk
menyelesaikan masalah pada masa lampau merupakan
topik yang menarik untuk diteliti. Akan tetapi, penelitian
dengan topik musyawarah pada kerajaan-kerajaan di
nusantara tidak banyak dilakukan. Hanya dua peneliti yang
melakukan penelitian dengan topik tersebut. Sebagai
contoh, Ardika (1985:584) melakukan penelitian tentang
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh raja-raja Bali
pada abad X-XI M. Selanjutnya, Savitri (1993) melakukan
penelitian terkait dengan musyawarah yang dilakukan oleh
Raja Hayam Wuruk di Jawa. Skripsi tersebut membahas
fungsi dan peran musyawarah serta hubungannya dengan
kekuasaan Raja Hayam Wuruk.
Penelitian tentang musyawarah yang dilakukan
oleh Savitri ini diperluas masa kajiannya, ruang lingkup
serta data yang digunakan. Perluasan fokus penelitian ini
tidak hanya pada masa Hayam Wuruk saja, namun juga
pada masa Majapahit sejak awal berdirinya kerajaan
tersebut pada abad 13 hingga abad 14 M atau masa
menjelang kemunduran Kerajaan Majapahit. Kemunduran
Majapahit dimulai pada abad 14 ketika pemerintahan
Kerajaan Majapahit ditinggalkan oleh patih atau menteri
tertingginya yang bernama Gajah Mada. Gajah Mada
memiliki keahlian yang luar biasa dalam menjalankan roda
pemerintahan.
Dalam hal ruang lingkup serta data yang digunakan.
Lingkup penelitian tidak hanya pada raja saja, namun juga
kerabat raja, bawahan raja, serta masyarakat yang tinggal di
pedesaan. Data yang digunakan tidak hanya berupa prasasti dan naskah kesastraan, namun juga relief yang ada pada
candi.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pelaksanaan musyawarah pada Kerajaan Majapahit pada
abad ke 13 hingga 14 M dari tingkat pusat pemerintahan
hingga masyarakat pedesaan. Hal tersebut berusaha
diungkap untuk membuktikan bahwa walaupun kerajaan
Majapahit bersifat otokratis, raja Majapahit tidak
memerintah secara otoriter; raja Majapahit memimpin
kerajaannya secara demokratis karena memberikan
kebebasan pada bawahannya maupun rakyatnya untuk
mengemukakan pendapat mereka melalui musyawarah.
Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi sejarah
Indonesia kuno terutama terkait dengan sejarah sosial dan
politik masa Majapahit.
Metode yang dilakukan untuk melakukan penelitian
ini adalah melalui studi pustaka, dengan cara
mengumpulkan data berupa alih aksara prasasti dari masa
Majapahit serta naskah kesastraan berupa
Nagarakertagama dan Pararaton yang mengindikasikan
adanya pelaksanaan musyawarah. Naskah lain yang
digunakan adalah Amertamathana sebagaimana terdapat
pada Mahabharata dan Kitab Mãnawa Dharmaçãstra.
Naskah-naskah ini merupakan naskah yang digunakan oleh
umat Hindu termasuk Kerajaan Majapahit sebagai salah
satu pedoman hidup mereka. Data lain yang digunakan
adalah yang ada pada miniatur candi yang ditemukan di
Ampel, Gading. Miniatur candi ini kini berada di Museum
Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Mojokerto.
Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis terhadap prasasti-prasasti serta naskah kesastraan
yang menceritakan tentang adanya proses pelaksanaan
musyawarah. Hal yang dianalisis adalah jenjang
pelaksanaan musyawarah, dari tingkat pusat kerajaan
hingga pedesaan, siapa saja yang berperan dalam
musyawarah serta hal apa saja yang dibahas pada saat
pelaksanaan musyawarah. Setelah dilakukakan analisis,
maka tahap berikutnya adalah interpretasi pelaksanaan
musyawarah di Kerajaan Majapahit abad ke-13-14 M untuk
membuktikan bahwa raja Majapahit memerintah
kerajaannya secara demokratis.
Pelaksanaan musyawarah pada prasasti dan naskah
kesastraan
Ada tiga prasasti yang mengindikasikan
pelaksanaan musyawarah pada masa Majapahit. Prasasti
yang menginformasikan tentang musyawarah sebagai
bentuk perundingan pada masa itu dapat ditemukan pada
prasasti Kudadu, Himad, dan Bendosari/Manah i Manuk.
Naskah kesastraan yang menyebutkan tentang pelaksanaan
musyawarah adalah Pararaton dan Nagarakertagama.
Musyawarah pada prasasti Kudadu, Himdad, dan
Bendosari/Manah i Manuk
Prasasti Kudadu
Prasasti Kudadu ditulis pada tahun 1216 Ç atau
1294 M. Prasasti ini menceritakan perjalanan Dyah Wijaya
atau Raden Wijaya ketika melarikan diri ke Desa Kudadu
serta menyusun strategi untuk merebut kembali kekuasaan
Kertanegara, raja Singhasari yang juga ayah mertua Dyah Wijaya, yang direbut oleh Jayakatwang (Yamin 1962:222).
Prasasti Kudadu menceritakan bagaimana Dyah Wijaya dan
Wiraraja berunding mengatur strategi untuk mendirikan
kerajaan baru (Yamin 1962:221). Bentuk solidaritas
Wiraraja yang lain kepada Dyah Wijaya adalah dengan
mengirimkan orang-orang Madura untuk menebang hutan
Tarik.
Prasasti Himad
Prasasti ini diperkirakan berasal dari sekitar tahun
1331 hingga 1364 M. Dasar perkiraan tersebut adalah
pengangkatan Gajah Mada sebagai Patih Mangkubumi
Majapahit hingga meninggal sebagaimana diberitakan pada
Nagarakertagama.
Prasasti Himad sebenarnya merupakan prasasti
peradilan, sebab prasasti tersebut berisi ketetapan dari
para pejabat kerajaan terkait dengan perselisihan antara
para rãma1
di Walandit dengan para dapur2
Himad. Hal yang
diperselisihkan adalah kedudukan Sang Hyang Dharmma
Kabuyutan3
dan status desa Walandit terhadap Himad.
1 Kata rãma merupakan Bahasa Jawa Kuno yang mengacu
pada sekumpulan pejabat desa (Permana 2016:297).
2 Kata dapur berasal dari Bahasa Jawa Kuno dan mengacu
pada wilayah dusun saat ini. Sebuah dapur dipimpin oleh
seorang tetua desa yang disebut dengan buyut.
3 Kabuyutan merupakan Bahasa Jawa Kuno yang mengacu
pada wilayah terkecil pada Kerajaan Majapahit (Suhadi
1993:114). Wilayah terkecil ini dapat disetarakan dengan
dusun, sebab wilayah yang lebih besar dari kabuyutan
adalah wanua/desa/thani. Dengan demikian maka Sang
Hyang Dharmma Kabuyutan dapat dikatakan sebagai Perselisihan yang terjadi itu bermula dari timbulnya
kesadaran para rãma Walandit yang menuntut hak mereka
terhadap Sang Hyang Dharmma Kabuyutan. Para rãma
Walandit memiliki bukti berupa prasasti dari zaman Sindok
yang menetapkan bahwa Sang Hyang Dharmma Kabuyutan
berstatus sīma4
. Berdasarkan bukti tersebut, para rãma
Walandit mengemukakan bahwa Sang Hyang Dharmma
Kabuyutan bukan merupakan daerah kekuasaan Himad,
melainkan berstatus swatantra. Desa Walandit mendapat
kewajiban untuk melakukan pemujaan di Dharmma
Kabuyutan dan memeliharanya serta mengawasi orangorang yang mandi dan mengambil air suci di tempat
tersebut.
Kejadian di atas menunjukkan bagaimana para
rãma Walandit mengajukan gugatannya. Oleh karena
masalah tersebut adalah masalah bersama dari para rãma,
maka dapat dipastikan bahwa ada proses musyawarah
sebelum gugatan diajukan.
Prasasti Bendosari/Manah i Manuk
Prasasti Bendosari/Manah i Manuk merupakan
prasasti peradilan yang dikeluarkan pada masa Majapahit
(Nastiti 1985:564). Penanggalan prasasti ini tidak diketahui
secara pasti karena tidak dicantumkan pada prasasti
tersebut. Hanya saja, berdasarkan nama Hayam Wuruk dan
gelar yang digunakan oleh para pejabatnya, maka prasasti
tersebut kemungkinan ditulis pada tahun 1272-1287 Ç atau
sekitar tahun 1350-1365 M
Prasasti Bendosari/Manah i Manuk memberikan
informasi mengenai adanya sengketa yang ada di desa
Manah i Manuk. Sebelum sengketa diajukan pada
pengadilan, maka orang-orang yang bersengketa seperti
Aki Santana Mapañji Sarana dan kawan-kawannya yaitu Ki
Karnna Mapañji Manakara, Ajaran Reka, Ki Siran, dan Ki
Jumput tentunya berunding atau bermusyawarah terlebih
dahulu. Mereka bermusyawarah tentang hal-hal yang
mereka tuntut kepada samasanak dari Sima Tiga dengan
ketuanya Apañji Anawung Harsa. Aki Santana Mapanji
Sarana dan kawan-kawannya menggugat samasanak dari
Sima Tiga karena mereka merasa memiliki tanah di Manah
i Manuk dan tempat lain seluas 67 lirih sejak tahun 919 Ç
atau 997 M (Nastiti 1985:565). Selain itu, mereka juga
menyatakan bahwa tidak ada sawah-sawah milik
samasanak Sima Tiga yang terletak melewati batas desa
Pakandanan.
Musyawarah pada naskah kesastraan: Pararaton dan
Nagarakertagama
Musyawarah pada Pararaton
Pararaton adalah naskah kesastraan berbentuk
prosa yang ditulis pada abad ke-16. Naskah ini
menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa
Kerajaan Singhasari dan Majapahit (Hardjowardojo
1965:5). Musyawarah yang diceritakan dalam naskah ini
terkait dengan keinginan Raden Wijaya sebagai turunan
laki laki paling akhir dari keluarga Rajasa dari Kerajaan
Singhasari atau menantu Raja Kertanegara yang datang ke
kediaman Adipati Wiraraja di Sungeneb. Sungeneb ini
disamakan dengan Sumenep saat ini yang ada di Madura.
Raden Wijaya dan Adipati Wiraraja pada waktu itu
membahas strategi untuk membalas dendam terhadap Raja
Jayakatwang. Jayakatwang adalah raja Kadiri yang telah
mengalahkan ayah mertua Dyah Wijaya (Yamin 1962:222).
Musyawarah pada Nagarakertagama
Naskah kesastraan lain yang menginformasikan
adanya musyawarah adalah Nagarakertagama yang
dikarang oleh Prapanca. Nama sebenarnya dari naskah ini
adalah Deçawarnana yang artinya uraian mengenai desadesa (Atmodjo 1979:5). Nama ini diberikan karena naskah
tersebut banyak menceritakan perjalanan Hayam Wuruk
dari desa ke desa ketika melakukan kunjungan ke
pertapaan maupun candi-candi tempat persemayaman
leluhur raja. Deçawarnana yang ditulis pada 1287 Ç atau
1365 M ini menceritakan kehidupan sehari hari atau
kejadian di sekeliling penulis naskah tersebut (Robson
1995:8). Berbagai aspek kehidupan dari masa Majapahit
diceritakan dalam naskah yang digubah dalam bentuk karya
sastra, termasuk ketika menceritakan secara detail
pelaksanaan musyawarah di kerajaan tersebut. Oleh karena
itu, maka naskah kesastraan dari masa Majapahit ini
dianggap sebagai sastra sejarah dan dapat dijadikan sebagai
sumber sejarah Kerajaan Majapahit yang penting (Sutjipto
1977:120).
Pelaksanaan musyawarah pada Nagarakertagama
terdapat pada pupuh LXXI:2. Pupuh tersebut menceritakan
bahwa raja bermusyawarah dengan kerabatnya untuk
mencari pengganti patih atau perdana menteri Majapahit
yang bernama Gajah Mada yang meninggal pada tahun 1286
Ç. Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan tidak
akan mengganti posisi Patih Gajah Mada, sebab tidak ada
seorang calonpun yang layak menggantikan kedudukan
patih tersebut. Keputusan lain yang diambil adalah memilih
enam orang menteri yang dianggap dapat menjalankan
tugas-tugas kerajaan.
Musyawarah tidak hanya dilaksanakan oleh raja
beserta kerabatnya saja, namun juga dilakukan oleh para
bawahan raja. Nagarakertagama pupuh VIII:3 menyatakan
bahwa para bawahan raja yang bermusyawarah adalah
para pendeta Siwa dan Buddha. Mereka bermusyawarah
untuk membahas upacara gerhana bulan pada bulan
Phalguna di sebelah timur Balai Wanguntur (Robson 1995:
29).
Pelaksanaan musyawarah tidak hanya terungkap
dari keberadaan prasasti dan naskah kesastraan sejarah
saja, namun juga dari cerita mitos sebagaimana terdapat
pada relief Amertamathana sebagaimana terdapat pada
miniatur candi di Ampel.
Musyawarah pada Relief Amertamathana
Relief Amertamathana yang dipahatkan pada bagian bawah miniatur Candi di Ampel, Gading5
erat
kaitannya dengan cerita tentang musyawarah yang
dilakukan oleh para dewa. Amertamathana merupakan
cerita Hindu tentang pencarian air kehidupan yang disebut
dengan amerta. Air kehidupan tersebut apabila diminum
oleh seseorang, maka ia dapat terhindar dari tua dan
kematian (Soekmono 1985:43).
Kitab Amertamathana menceritakan, pada zaman
dahulu ketika dunia belum dihuni oleh manusia, hanya
dihuni oleh para dewa dan daitya6
(Soekmono 1985:43).
Para dewa yang mewakili kebaikan berjumlah hanya
sedikit dan mereka ini diceritakan tinggal di atas atau di
kahyangan. Sebaliknya, para raksasa yang mewakili
kejahatan jumlahnya sangat banyak dan mereka tinggal di
dunia bawah. Dewa dan daitya tidak bisa hidup bersama
secara damai. Mereka selalu bertengkar sehingga Dewa
Brahma khawatir apabila dunia dikuasai oleh kejahatan
maka dunia akan hancur. Untuk mengatasi hal tersebut,
para dewa berunding di puncak Gunung Meru dan
memutuskan melakukan pengadukan samudra supaya
keluar amerta dari pusatnya sehingga para dewa akan
terhindar dari kematian (Soekmono 1985:43).
Aspek kesejarahan dari kejadian yang diuraikan di
atas sulit untuk dicari, apakah dewa-dewa itu benar-benar
ada atau benar-benar bermusyawarah. Fakta atau tidaknya
cerita mitos tersebut tidak perlu diperdebatkan, sebabapabila itu merupakan kejadian fiktif, maka cerita itu
diciptakan berdasarkan pola-pola pikiran dan perasaan
yang hidup pada masyarakat yang ditulis oleh penulis
naskah kesastraan (Sutjipto 1977:121). Dengan demikian,
maka hal terpenting yang perlu dipahami dari cerita itu
adalah bahwa raja yang diidentikkan dengan dewa juga
bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang
dihadapi pada waktu itu.
Musyawarah pada masyarakat Majapahit: dari kaum
elite kerajaan hingga masyarakat pedesaan
Musyawarah dalam Bahasa Jawa Kuno disebut
dengan istilah pulung tandas, pulung rahi dan höm
(Zoetmulder 2006:349). Musyawarah didefinisikan sebagai
bentuk pembahasan bersama dengan maksud untuk
mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama;
perundingan; perembukan
(https://kbbi.web.id/musyawarah diakses 27 Desember
2019). Musyawarah dilaksanakan untuk memperoleh hasil
keputusan yang disepakati bersama karena menyangkut
kepentingan bersama (Savitri 1993:4). Musyawarah
dilakukan agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh
semua pihak atau ada kompromi dalam pelaksanaannya
(Budiardjo 1982:55).
Hal yang menarik dari adanya musyawarah adalah
adanya kerja sama dari orang-orang yang melakukan
perundingan. Logsdon (1978:95) menyatakan bahwa
pelaksanaan musyawarah menunjukkan adanya semangat
kerja sama. Pelaksanaan musyawarah pada Kerajaan
Majapahit ini menunjukkan bahwa kerjasama yang menjadi
salah satu ciri khas bangsa Indonesia ini telah ada sejak
masa lampau.
Berdasarkan data prasasti dan naskah kesastraan
upaya untuk menyelesaikan masalah secara bersama
berupa musyawarah pada masa Majapahit tidak hanya
dilakukan di tingkat pusat pemerintahan oleh para kerabat
raja saja, namun juga para tokoh agama, maupun
masyarakat di pedesaan.
Musyawarah pada kaum elite kerajaan di pusat
pemerintahan
Pelaksanaan musyawarah pada kalangan elite
kerajaan yang terdiri dari raja beserta kerabatnya telah
dimulai pada saat pembentukan Kerajaan Majapahit.
Berdasarkan prasasti Kudadu dan naskah Pararaton
diketahui bahwa Raden Wijaya, menantu Raja Kertanagara
dari Singhasari yang dikalahkan oleh Jayakatong atau
Jayakatwang dari Daha, bermusyawarah dengan Arya
Wiraraja, mantan pegawai Raja Kertanagara yang dijadikan
bupati di Sungeneb yang terletak di Madura Timur
(Hardjowardojo 1965:36). Mereka bermusyawarah untuk
menghasilkan strategi yang tepat agar Raden Wijaya dapat
naik tahta dan mendirikan kerajaan di Desa Tarik7
. Strategi
tersebut berhasil diterapkan dengan baik oleh Raden
Wijaya, sebab terbukti dapat memberikan kemenangan
bagi Raden Wijaya hingga berhasil mendirikan kerajaan
baru yang diberi nama Majapahit.
Selanjutnya, pada saat Kerajaan Majapahit telah
berdiri, musyawarah tampaknya menjadi cara yang sering
digunakan oleh masyarakat Majapahit untuk
menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sebagai contoh,
pada kalangan elite kerajaan, musyawarah dilakukan oleh
para kerabat raja yang tergabung dalam sebuah dewan yang
disebut dengan Bhatara Sapta Prabhu. Keberadaan dewan
ini diketahui dari Prasasti Singosari 1273 Çaka dan naskah
kesastraan Nagarakertagama. Dewan yang bertugas
menjadi penasihat dan pemberi pertimbangan kepada raja
pada masa Majapahit ini mulai dikenal pada masa
pemerintahan Tribhuwanottunggadewi (Savitri 1993:39).
Pada musyawarah yang dilaksanakan para kerabat
raja yang tergabung dalam Bhatara Sapta Prabhu ini, raja
bertindak sebagai ketua atau pemimpin musyawarah.
Sebagai contoh, Tribhuwanottunggadewi adalah raja
Majapahit ke-3 setelah Jayanagara dan ibu dari Hayam
Wuruk yang bertindak sebagai ketua Bhatara Sapta Prabhu.
Hal itu disebutkan dalam prasasti Singosari (1273 Çaka atau
1351 M). Prasasti tersebut menyebutkan bahwa
Tribuwanottunggadewi yang menjadi raja pada waktu itu,
juga bertindak sebagai ketua Bhatara Sapta Prabhu (Savitri
1993:39). Pada masa berikutnya, ketika Hayam Wuruk
menjadi raja, ketua Bhatara Sapta Prabhu berpindah tangan
kepada Hayam Wuruk. Kedudukan raja sebagai ketua
Bhatara Sapta Prabhu itu kemungkinan besar terkait
dengan kedudukan raja sebagai penguasa tertinggi kerajaan
dan konsep dewaraja yang dianut oleh Kerajaan Majapahit.
Terkait dengan jumlah anggota Bhatara Sapta
Prabhu, jumlahnya bertambah pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk. Prasasti Prapancasarapura
memberikan keterangan, pada mulanya ketika
Tribhuwanottunggadewi menjadi raja, ada lima orang yang
tergabung dalam Bhatara Sapta Prabhu; mereka itu adalah
Raja Tribhuwanottunggadewi, suami raja yaitu Çrî
Bhathara Kertawarddhana, dua orang saudara raja yang
bernama Dyah Wiyat Rajadewi, dan Çrî Bhatara
Wijayarajasa serta putra mahkota yang bernama Hayam
Wuruk.
Ketika Hayam Wuruk menjadi raja, jumlah para
kerabat yang bermusyawarah pada waktu itu bertambah
menjadi sembilan orang dan hal tersebut dapat diketahui
dari Naskah Nagarakertagama pupuh LXXI:2 (Robson
1995:77). Pupuh tersebut menjelaskan bahwa mereka itu
adalah Raja Hayam Wuruk, Putri dari Pajang, Lasem, Daha,
dan Jiwana dan suami-suami mereka yaitu Pangeran dari
Paguhan, Matahun, Wengker, dan Singasari (Pigeaud
1963:214). Bertambahnya jumlah anggota Bhatara Sapta
Prabhu merupakan bukti semakin luasnya wilayah
kekuasaan Majapahit dengan semakin banyaknya anggota
keluarga yang menjadi penguasa di beberapa daerah di
wilayah Majapahit.
Hal yang dibahas atau dibicarakan pada
musyawarah yang dilakukan oleh Bhatara Sapta Prabhu
terkait dengan upaya mempertahankan kelangsungan
pemerintahan kerajaan Majapahit. Hal ini dapat diketahui
dari Nagarakertagama pupuh LXXI:2. Pupuh tersebut juga
menjelaskan lebih lanjut bahwa musyawarah yang
dilakukan tersebut untuk menentukan siapa yang akan
menggantikan Patih Gajah Mada yang meninggal pada tahun 1364 M. Hal tersebut penting dibahas secara
bersama, karena kepergian Patih Gajah Mada untuk
selamanya itu sangat mempengaruhi kehidupan politik di
Majapahit. Patih Gajah Mada adalah tokoh besar yang
berkat kemampuannya Majapahit berhasil menjadi
kerajaan yang besar dan kuat (Savitri 1993:38).
Pelaksanaan musyawarah pada waktu itu tidak
selalu berjalan lancar. Pupuh LXXI:2 menyatakan bahwa
para kerabat raja berdebat lama untuk menghasilkan
keputusan yang disetujui semua pihak. Namun, keputusan
yang diharapkan oleh semua pihak tetap tidak dapat
memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan
karena adanya perbedaan pendapat diantara para kerabat
raja yang bermusyawarah (Robson 1995:77). Perbedaan
pendapat biasa terjadi pada sebuah musyawarah, oleh
karena itu perlu adanya kesepakatan dari semua pihak yang
bermusyawarah atau kompromi.
Dalam sebuah musyawarah, aspek kompromi
merupakan hal penting sebelum keputusan diambil. Hal itu
sesuai dengan pendapat Logsdon (1978:95) yang
menyatakan bahwa ada proses kompromi dalam
bermusyawarah. Hal tersebut dapat terjadi karena ada
kepentingan umum yang diperhatikan pada saat
bermusyawarah (Logsdon 1978:95). Hal ini juga terjadi
pada musyawarah yang dilakukan oleh raja Majapahit
beserta para kerabatnya. Pada saat terjadi kemacetan pada
pelaksanaan musyawarah, maka diperlukan adanya
kompromi diantara peserta musyawarah. Akhirnya, dengan
adanya kompromi itu maka dicapailah keputusan untuk
tidak menetapkan pengganti Patih Gajah Mada. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat
menggantikan kedudukan Patih Gajah Mada (Robson
1995:77).
Ketika keputusan untuk tidak mengganti posisi
Patih Gajah Mada ditetapkan, pimpinan musyawarah
bertanggung jawab atas hasil musyawarah. Demikian pula
yang terjadi pada Hayam Wuruk. Sebagai seorang raja dan
pemimpin musyawarah, Hayam Wuruk menunjukkan rasa
tanggung jawabnya terhadap keputusan yang telah diambil
secara bersama itu. Hal tersebut ditegaskan pada Naskah
Nagarakertagama pupuh LXXI:3 yang menyatakan bahwa
raja bertanggung jawab apabila ada pihak pihak tertentu
yang merasa keberatan atas hasil yang telah diputuskan
secara bersama (Robson 1995:77).
Musyawarah yang dilakukan oleh Bhatara Sapta
Prabhu tersebut tidak hanya menyangkut pemilihan
pengganti Patih Gajah Mada, namun juga lainnya.
Nagarakertagama pupuh LXXII menyatakan bahwa pada
waktu itu Bhatara Sapta Prabhu juga mengangkat Pu Tandi
sebagai wrddamantri8
Pu Nala sebagai tumenggung
mancanegara dan Patih Dami sebagai yuwamantri9
(Robson 1995:77).
Prosedur pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh raja pada masa Majapahit dapat diketahui secara lebih
jelas pada Kakawin Ramayana XIII: 20-9710. Dalam kakawin
tersebut diceritakan tentang musyawarah yang dilakukan
oleh Rawana. Mula-mula Rawana diceritakan
mengumpulkan para patihnya untuk dimintai pendapatnya
tentang cara melawan Rama. Rawana yang memimpin
pertemuan tersebut juga menyampaikan beberapa
tindakan Rama yang merugikan Rawana diantaranya
membunuh perwira dan prajurit raksasa Kerajaan Lengka,
membunuh Bali sahabat Rawana, dan membunuh anak
kesayangan Rawana yang bernama Sang Aksa. Setelah
Rawana mengemukakan masalahnya, para patih kemudian
mengajukan pendapatnya masing-masing (Savitri
1993:71).
Musyawarah pada masa Majapahit tidak hanya
dilakukan oleh kaum elite kerajaan saja, namun juga
dilakukan oleh tokoh agama. Di bawah ini adalah
pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh
agama.
Musyawarah yang dilakukan oleh tokoh agama
Informasi mengenai musyawarah yang dilakukan
oleh tokoh agama atau pendeta Siwa maupun Buddha
diketahui dari naskah kesastraan Nagarakertagama.
Naskah Nagarakertagama tersebut menceritakan bahwa
musyawarah dilakukan oleh para pendeta tersebut di
bangsal depan keraton (Robson 1995:29). Pada masa
Hayam Wuruk, para pendeta Siwa dan Buddha
bermusyawarah untuk membahas penyelenggaraan
upacara gerhana bulan pada bulan Phalguna. Hal itu disebut
dalam Nagarakertagama VIII:3 yang menyatakan:
“…nggwan para sewa bodda mawiwada mucap aji
sahopakara wki sok, prayascita ri kalaning grahana
Phalguna makaphala haywaning sabhuwana…”
Upacara gerhana tersebut merupakan hal penting
bagi kerajaan Majapahit dan hal itu ditunjukkan dengan
besarnya perhatian Hayam Wuruk sebagai raja pada waktu
itu. Kebesaran dan kemeriahan upacara tersebut sebagai
upacara kerajaan perlu diselenggarakan sebagai salah satu
bukti besarnya kekuasaan raja (Moedjanto 1990:104).
Selain itu, upacara itu juga penting dilakukan untuk
mencapai keselamatan seluruh dunia. Oleh karena itulah
maka Hayam Wuruk memberikan kepercayaan kepada para
pendeta Siwa dan Buddha, sebab mereka dianggap lebih
memahami pelaksanaan ritual tersebut. Para pendeta Siwa
dan Buddha melaksanakan perintah raja tersebut dengan
baik dan hal itu dibuktikan dengan melaksanakan
musyawarah untuk membahas segala hal terkait dengan
pelaksanaan upacara tersebut (Savitri 1993:40).
Musyawarah pada waktu itu dilaksanakan di wanguntur,
halaman utama keraton, sebuah bangunan luas yang
terletak di bagian depan keraton. Stutterheim dalam
Pigeaud (1963:13) menyatakan bahwa wanguntur
sebagaimana halnya keraton-keraton Jawa lainnya
dilengkapi dengan sitihinggil. Musyawarah yang dikenal dan dilaksanakan di
Majapahit tidak hanya dikenal pada kalangan elite kerajaan
dan para tokoh agama. Masyarakat pedesaan juga
melaksanakan musyawarah diantara mereka. Berikut ini
disampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan
musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat di
pedesaan.
Musyawarah pada masyarakat desa
Data prasasti secara implisit menunjukkan bahwa
ada proses musyawarah pada masyarakat pedesaan.
Indikasi adanya musyawarah pada masyarakat pedesaan di
Majapahit terdapat pada prasasti Himad dan
Bendosari/Manah I Manuk.
Berdasarkan informasi pada prasasti Himad
diketahui bahwa para rãma Walandit bermusyawarah
terlebih dahulu sebelum mengajukan tuntutan kepada
masyarakat desa Himad. Mereka bermusyawarah tentang
hal-hal apa saja terkait dengan tuntutan yang akan diajukan
kepada pihak lawan, para dapur Himad, terkait dengan
status sīma atau swatantra desa mereka.
Status sīma berupa anugerah istimewa dari raja
membawa perubahan bagi masyarakat desa. Perubahan itu
berupa kebebasan dalam hal pembayaran pajak atau
pengurangan pajak (Suhadi 1993:3). Status istimewa
tersebut tentu saja menggembirakan masyarakat desa, oleh
karena itu mereka merasa perlu memperjuangkan status itu
secara bersama (Suhadi 1993:3).
Para dapur Himad tersebut kemudian melakukan
musyawarah sebelum memberikan keterangan terkait dengan keberadaan Sang Hyang Dharmma Kabuyutan yang
dipermasalahkan para rãma Walandit. Mereka
menyatakan bahwa kundi thãni11 yang ditempatkan di
Walandit berasal dari Himad. Para dapur Himad juga
menyatakan bahwa bahkan merekalah yang memberi tahu
para rãma Walandit tentang kerusakan yang ada pada Sang
Hyang Dharmma Kabuyutan.
Keputusan terhadap masalah yang menjadi
sengketa masyarakat dua desa itu kemudian dikeluarkan
oleh para pejabat kehakiman kerajaan seperti samget i
jamba, samget i pamwatan, pu andawan, rakryan apatih
mpu mada, dan sang aryya rajadhikara. Para pejabat
kehakiman itu menetapkan keputusan setelah
mendengarkan keterangan para saksi, mempelajari kasuskasus yang pernah terjadi sebelumnya serta kitab-kita
hukum, berpegang teguh pada kita Kutaramanawadi, serta
mengikuti kebiasaan sang pendeta dalam memutuskan
suatu perkara (Nastiti 1985:564). Mereka memutuskan
bahwa bukti-bukti yang dikemukakan oleh para rãma
Walandit dianggap lebih kuat sehingga akhirnya mereka
memenangkan sengketa ini. Adapun pejabat kehakiman
kerajaan yang mengesahkan keputusan tersebut adalah
sang wangsadhipati pamget tiruan. Berdasarkan
keterangan yang ada pada prasasti tersebut, maka prasasti
Himad ini dapat pula dikatakan sebagai prasasti peradilan
dari masa Majapahit.
Contoh musyawarah lainnya yang melibatkanmasyarakat desa dapat dijumpai pada prasasti
Bendosari/Manah i Manuk. Samasanak Sima Tiga yang
digugat, sebagaimana diceritakan pada prasasti
Bendosari/Manah i Manuk, tentu juga bermusyawarah
terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Aki Santana
Mapañji Sarana dan kawan kawannya karena hal yang
digugat itu menyangkut kepentingan bersama. Para
samasanak Sima Tiga ini bermusyawarah untuk
mengajukan pembelaan dengan menyatakan bahwa tanah
seluas 67 lirih itu dahulu digadaikan kepada canggahnya
seharga satu setengah taker12 perak.
Persengketaan itu akhirnya diselesaikan oleh
pejabat kehakiman kerajaan yang tergabung dalam
kelompok pejabat rakryan ring pakirakiran. Mereka
menetapkan keputusan terhadap sengketa tersebut
berdasarkan kitab-kitab hukum, pendapat umum, serta
kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, Aki Santana Mapanji Sarana
dimenangkan dan mereka mendapat surat jayasong untuk
melindungi hak mereka (Nastiti 1985:565).
Musyawarah yang diselenggarakan oleh penduduk
desa untuk menuntut hak mereka itu menunjukkan bahwa
mekanisme jalannya pemerintahan masa Majapahit itu
tidak hanya dari atas ke bawah saja, namun juga dari bawah
ke atas (Savitri 1993:69). Mereka bermusyawarah diantara
mereka terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan
kepada pihak kerajaan. Apabila masalah yang dihadapi tidak juga dapat diselesaikan di tingkat desa, maka diajukan
kepada tingkat pusat kerajaan. Pada tingkat yang lebih
tinggi ini, masalah diselesaikan oleh raja beserta pejabat
yang dianggap kompeten dalam bidangnya, misalnya
pejabat kehakiman, atau raja beserta para kerabatnya yang
tergabung pada dewan pertimbangan kerajaan yang
disebut dengan Bhatara Sapta Prabhu.
Berdasarkan interpretasi terhadap data prasasti
maupun naskah kesastraan, terbukti bahwa pada masa
Majapahit abad ke 13 hingga 14 M telah dikenal cara
penyelesaian masalah dengan cara musyawarah.
Musyawarah ini dilakukan dari kaum elite yang terdiri dari
para kerabat raja, tokoh agama, serta penduduk desa.
Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan masalah
secara bersama dan kompromi.
Musyawarah pada masa Majapahit: bukti adanya
kepemimpinan demokratis pada sebuah kerajaan
Dalam sebuah pemerintahan, ada tiga jenis
kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hargie, Saunders,
dan Dickson (1994:309). Ketiga jenis pemimpin itu adalah
otokratis, demokratis dan laissez faire. Diantara tiga jenis
itu, dua jenis kepemimpinan yaitu otokratis dan demokratis
yang dibahas dalam tulisan ini, karena jenis kepemimpinan
tersebut yang sangat terkait dengan topik bahasan tulisan
ini. Pada kepemimpinan otokratis atau kerajaan,
pemimpinnya cenderung untuk memimpin secara otoriter.
Hal ini dapat terjadi karena pemimpin tersebut memiliki
wewenang dan kekuasaan yang terkonsentrasi dalam
dirinya yang sangat besar. Masyarakat pada pemerintahan dengan jenis pemimpin otoriter cenderung bersifat
pesimistis dan negatif karena pemimpinnya tidak
mendukung masyarakat untuk berinisiatif dan maju. Para
pemimpin jenis ini juga tidak mendukung komunikasi yang
aktif diantara para anggotanya (Northouse 2021). Hal ini
berbeda dengan yang terjadi pada pemimpin yang
demokratis. Para pemimpin demokratis mendukung
anggotanya untuk berinteraksi. Pemimpin yang demokratis
memberikan efek positif pada masyarakat. Mereka memiliki
inisiatif dan tanggung jawab atas kemajuan mereka (Hargie,
Saunders, dan Dickson 1994:309).
Pemimpin pada Kerajaan Majapahit adalah seorang
raja yang tidak bertindak secara otoriter walaupun
memiliki status sosial tertinggi di wilayah kekuasaannya
(Savitri 2015:23). Status dan kekuasaan yang tinggi itu
diperoleh karena raja dikultuskan sebagai dewa dengan
cara menganggapnya sebagai titisan dewa atau bahkan
dewa itu sendiri (von Heine-Geldern 1942:22; Kartodirdjo
1969:18; Savitri 1993:3). Hal ini diperkuat dengan
pernyataan pada Manawa Dharmmaçastra VII:13 dan
Manawa Dharmaçastra VII:6 sebagai kitab undang-undang
Majapahit terkait dengan perilaku raja. Undang-undang
tersebut menyatakan bahwa raja berhak mengeluarkan
undang-undang, menghukum orang yang melanggar
undang-undang, dan berhak menghukum orang yang
menentangnya.
Kekuasaan raja yang sedemikian tinggi itu ternyata
tidak menjadikan raja bertindak tak terbatas. Manawa
Dharmmaçastra sebagai undang-undang Kerajaan
Majapahit tidak hanya mencantumkan hak-hak seorang raja saja, namun juga kewajiban yang harus dilakukan oleh
seorang raja. Kewajiban itu dituntut untuk dilakukan oleh
seorang raja untuk mengimbangi dan membatasi
kekuasaan raja yang begitu tinggi itu. Hal itu terbukti dari
Manawa Dharmmacastra VII:140 yang menyatakan bahwa
dalam menjalankan pemerintahan, seorang raja dituntut
untuk mempertimbangkan setiap persoalan yang dihadapi
dan hendaknya bertindak tegas dan bijaksana, karena raja
yang bersikap demikian itu sangat disegani oleh semua
orang. Pelaksanaan musyawarah pada Kerajaan Majapahit
juga menjadi bukti bahwa raja Majapahit tidak
menggunakan haknya tanpa batas. Raja Majapahit juga
bertindak bijaksana dan demokratis karena bersedia
mendengarkan orang lain sebelum menetapkan suatu
keputusan.
Sikap demokratis raja berimbas pada kebijakannya
pada seluruh wilayah kerajaan, dari tingkat pusat hingga
desa. Hal itu memberikan dampak positif pada rakyatnya.
Rakyat bebas untuk menyatakan pendapatnya dalam
sebuah musyawarah. Inisiatif masyarakat pedesaan untuk
bermusyawarah ini sekaligus merupakan bukti bahwa
masyarakat tidak bertindak secara pasif. Mereka aktif
berkomunikasi dan berpendapat secara interaktif dalam
sebuah musyawarah dengan pihak lain untuk kemajuan
mereka.
Musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat
Majapahit dari tingkat pusat hingga pedesaan menunjukkan
bahwa Kerajaan Majapahit tidak dipimpin oleh raja yang otoriter, namun dipimpin oleh raja yang demokratis. Kitab
Manawa Dharmmaçastra sebagai undang-undang pada
Kerajaan Majapahit tampaknya efektif untuk membatasi
kekuasaan raja yang tak terbatas sebagaimana terdapat
pada konsep dewaraja yang menganggap rajansebagai
titisan dewa.
Pelaksanaan musyawarah pada segala lapisan
masyarakat itu membuktikan bahwa musyawarah telah
dilaksanakan secara aktif pada waktu itu. Hal ini sekaligus
menegaskan sikap demokratis raja yang tidak mengekang
rakyatnya untuk berpendapat. Kebebasan yang diberikan
raja kepada para kerabat, bawahan, dan masyarakat di
pedesaan untuk bermusyawarah itu menunjukkan bahwa
raja memberikan semangat kepada rakyatnya untuk
berkomunikasi secara aktif dan berinteraksi secara bebas
dengan pihak lain. Hal inilah yang semakin menegaskan
adanya pemerintahan demokratis dan tidak otoriter pada
Kerajaan Majapahit.
Trowulan, sebuah kawasan yang secara geografis
terletak di Jawa bagian timur, diyakini oleh banyak
sejarawan, arkeolog, dan para sarjana pernah menjadi kota
Raja Kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit mencapai masa
keemasannya, kota raja ini menjadi sebuah kota yang kaya
dan makmur. Banyak pendatang dari luar daerah datang ke
sini khususnya untuk urusan perdagangan dan diplomatik.
Para pendatang tersebut misalnya dari daerah lain di Jawa,
beberapa pulau di nusantara seperti Bali, Dompo,
Suwarnadwipa, dan juga orang–orang dari daerah yang
lebih jauh lainnya seperti Campa, Siam, Khmer, Birma dan
tentu saja Cina. Kondisi ini direkam oleh Prapanca dengan
baik dalam karyanya Desawarnnana atau yang lebih banyak
dikenal dengan Nagarakretagama13
.
Keruntuhan Kerajaan Majapahit pada awal abad
XVI, tidak serta merta menghilangkan memori kolektif
masyarakat pulau Jawa dan sekitarnya atas kejayaan yang
pernah dicapai beberapa abad sebelumnya tersebut. Hal ini
dapat dilihat dari berbagai karya sastra yang diproduksi
sejak abad XVII. Seperti dalam kitab Pararaton misalnya yang menjelaskan tentang para penguasa kerajaan tersebut
berikut para leluhurnya. Selain itu, dijelaskan pula berbagai
peristiwa yang terjadi sejak masa leluhur wangsa Rajasa
yang memerintah kerajaan Majapahit hingga keruntuhan
kerajaan tersebut. Naskah Pararaton yang tertua berasal
dari tahun 1613 Masehi atau sekitar 100 tahun pasca
keruntuhan Majapahit.
Selain Pararaton, berbagai karya sastra lainnya
tentang kejayaan Majapahit terus diproduksi dan
direproduksi khususnya dari kalangan istana baik di Jawa
maupun Bali. Kondisi tersebut terjadi karena para penguasa
mendapatkan manfaat baik dari ikatan darah dengan
Majapahit maupun penguasaan atas berbagai peninggalan
Majapahit. Memori masyarakat bumiputera tentang adanya
suatu kerajaan besar di masa lalu, rupanya menarik minat
dan perhatian bangsa Eropa untuk mengambil manfaat
seperti halnya kalangan bangsawan dan penguasa Jawa.
Meskipun demikian, pemanfaatan Majapahit dan
peninggalannya oleh bangsa Eropa tetap memiliki
perbedaan mendasar.
Pada masa setelah Inggris angkat kaki, Majapahit
dan warisannya kembali ke dalam kekuasaan Belanda. Pada
masa inilah kemudian dikembangkan penelitian yang lebih
memadai terkait bekas Kotaraja Majapahit di Trowulan,
Jawa Timur. Tulisan ini akan mengeksplorasi beberapa
sumber-sumber terkait khususnya bagaimana para
penguasa kolonial baik Inggris maupun Belanda
memandang dan memanfaatkan Majapahit beserta
peninggalannya dimulai sejak masa Raffles berkuasa hingga
awal abad keduapuluh. Beberapa temuan baru dari sumber-sumber ini antara lain peran dari Bupati Mojokerto R.T
Kromo Adinegoro dalam pelestarian warisan Majapahit di
wilayahnya yang kerap tertutupi oleh kontribusi besar
pendahulunya. Selain itu, interpretasi arca terakota yang
sering diidentifikasi sebagai Gajah Mada juga telah populer
di masa tersebut, jauh sebelum Muhammad Yamin
mengklaimnya.
Majapahit dalam Kekuasaan Inggris
Meskipun telah ditinggalkan sejak keruntuhannya,
kota Majapahit di Trowulan masih memiliki magnet bagi








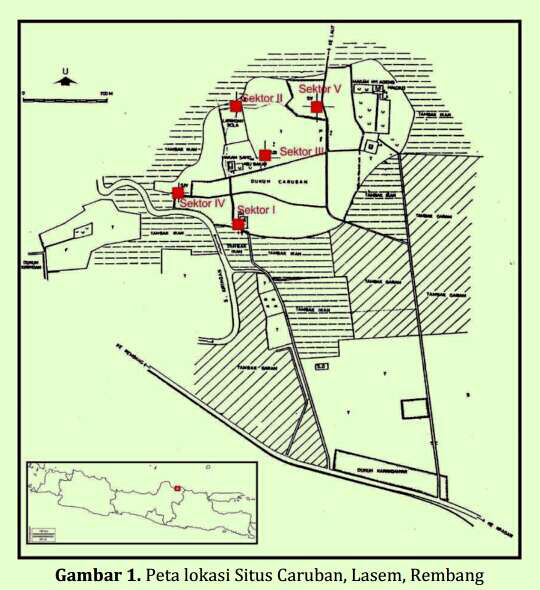

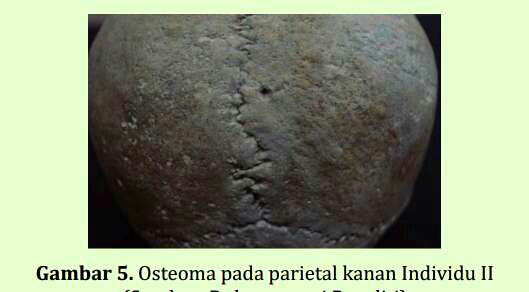
.jpg)









