Kamis, 15 Juni 2023
jakarta 3
By Lampux.blogspot.com Juni 15, 2023
2) Wajib memelihara objek kerja sama dan barang hasil
kerja sama; dan
3) Dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan
sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang
diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian
dimulai (clawback).
Berdasarkan Pasal 54, BMN/Barang Milik Daerah yang tidak
diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan
negara/daerah dapat dipindahtangankan.
Pemindahtanganan BMN/Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. Penjualan;
b. Tukar Menukar;
c. Hibah; atau
d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
Pasal 55 ayat (1) mengatur juga persyaratan persetujuan DPR
untuk Pemindahtanganan BMN untuk:
a. tanah dan/atau bangunan; atau
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
D. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Pemindahan
dan Pembangunan IKN
Walaupun RUU IKN tidak mengatur tentang teknis
pemindahan dan pembangunan IKN, namun ketentuanketentuan pokoknya akan diatur. Karenanya, RUU IKN akan
bersinggungan dengan beberapa Peraturan Perundangundangan, mulai dari UU No. 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum dan Kerangka Pengaturan seputar Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha, seperti Perpres 38 Tahun 2015
dan peraturan pelaksana di bawahnya.
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 6 jo. Pasal 7 menetapkan kerangka dasar
penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum berada
pada wewenang pemerintah pusat yang harus sesuai dengan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
c. Rencana Strategis; dan
d. Rencana Kerja setiap instansi (lembaga negara,
kementerian dan lembaga nonkementerian, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan
Hukum Milik Negara (BHMN)/BUMN yang mendapat
penugasan khusus pemerintah pusat) yang
memerlukan tanah.
Maka dapat dilihat bahwa pengadaan tanah dilakukan
dengan sistem perencanaan yang harmonis dengan rencanarencana lainnya untuk memastikan arah pengadaan tanah
tetap berada pada jalur perencanaan yang sudah ditetapkan
sebelumnya.
Pasal 10 menjabarkan pengadaan tanah digunakan untuk
pembangunan
a. Pertahanan dan keamanan nasional;
b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api,
stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. Waduk, bedungan, bendung, irigasi, saluran air
minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan
bangunan pengairan lainnya;
d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi
listrik;
g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
pusat;
h. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
i. Rumah sakit pemerintah pusat/pemerintah daerah;
j. Fasilitas keselamatan umum;
k. Tempat pemakaman umum pemerintah
pusat/pemerintah daerah;
l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka
hijau publik;
m. Cagar alam dan cagar budaya;
n. Kantor pemerintah pusat/pemerinta daerah/desa;
o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau
konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah
pusat/pemerintah daerah;
q. Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah;
dan
r. Pasar umum dan lapangan parkir umrum.
Pasal 10 ayat (1) mewajibkan pemerintah pusat untuk
melaksanakan pengadaan dari jenis-jenis peruntukan di
atas yang tanahnya selanjutnya dimiliki oleh pemerintah
pusat atau pemerintah daerah. ayat (20 menjelaskan juga
bahwa bila instansi yang memerlukan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum adalah BUMN, maka tanahnya
menjadi milik BUMN ini .
Meski seakan-akan terpisah, namun Pasal 12 ayat (1)
mengatur bahwa pemerintah pusat dapat bekerja sama
dengan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau
badan usaha swata, sehingga memungkinkan fleksibilitas
opsi pelaksanaan pengadaan tanah menggunakan skema
kerjasama untuk membantu pelaksanaan pembangunan
infrastruktur yang dibangun di atas tanah yang
direncanakan ini .
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria
Penyelenggaraan pemberian hak atas tanah diatur
berdasarkan ketentuan Pasal 2 yang mana negara
memiliki hak menguasai yang diwujudkan dengan
pemberian wewenang untuk :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air
dan ruang angkasa;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan
ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan
hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Hak menguasai ini dapat dikuasakan kepada daerah
dan masyarakat-masyarakat hukum adat yang
peruntukannya tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional. Dengan demikian pada hakikatnya hak
menguasai negara adalah nafas dari hak yang nantinya
akan diatur secara spesifik dalam peraturan perundangundangan selanjutnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tenntang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah
Hak pengelolaan dikenal melalui peraturan ini yang
didefinisikan sebagai:
“hak menguasai dari negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegangnya.”
Jadi hak pengelolaan bila dikatikan dengan Pasal 2 ayat
(4) Undang-Undang Nomo. 5 Tahun 1960 adalah
penitikberatan pada tujuan hak menguasai negara dan
melindungi kepentingan nasional, sehingga pengaturan
mengenai hak pengelolaan perlu untuk dirinci.
Wewenang pemegang hak pengelolaan dalam pengaturan
ini antara lain:
a. pemberian usul kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang agrarian atau
pejabat yang ditunjuk atas Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai yang dimohonkan atas tanah hak
pengelolaan (Pasal 22 ayat (2), Pasal 42 ayat (2));
b. Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan
Pasal 26 ayat (3)) dan pemberian usul atas
perpanjangan atau pembaharuan Hak Pakai (Pasal 46
ayat (2));
c. Pembatalan Hak Guna Banguna dan Hak Pakai (Pasal
35 ayat (1) huruf b, Pasal 55 ayat (1) huruf b); dan
d. Peralihan Hak Guna Banguna sebab pewarian (Pasal
34 ayat (6)) dan peralihan Hak Pakai (Pasal 54 ayat (9)).
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan
Hak Pengelolaan
Peraturan ini menjelaskan bahwa pada dasarnya hak
pengelolaan dapat dibangun untuk:
e. Hak Guna Bangunan (Pasal 21); dan
f. Hak Pakai (Pasal 41);
Pasal 67 mengatur bahwa pihak-pihak yang dapat
menerima hak pengelolaan antara lain:
a. Instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah;
d. PT. Persero;
e. Badan Otorita;
f. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang
ditunjuk pemerintah.
Yang mana pemberian hak pengelolaan ini dilakukan
sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
berkaitan dengan pengelolaan tanah.
Yang mana dalam aturan ini disebutkan bahwa
permohonan hak pengelolaan diajukan kepada Menteri
yang menyelenggarakan urusan di bidang agrarian melalui
kepala kantor pertanahan yang daerah kerjanya meliputi
letak tanah yang bersangkutan (Pasal 70), dengan ini
pengaturan di rancangan undang-undang perlu untuk
menjelaskan hak pengelolaan yang diberikan kepada
Otorita Ibu Kota Negara sehingga adanya kepastian adanya
perwujudan perlindungan kepentingan nasional yang
secara akarnya sudah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.
Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur
Pasal 5 mengatur mengenai jenis infrastruktur ekonomi
dan infrastruktur sosial dapat dilakukan dengan skema
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),
antara lain:
a. Infrastruktu transportasi;
b. Infrastruktur jalan;
c. Infrastuktur sumber daya air dan irigasi;
d. Infrastruktur air minum;
e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
i. Infrastruktur ketenagalistrikan;
j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi
terbarukan;
k. Infrastruktur konservasi energi;
l. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
m. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga,
serta kesenian;
o. Infrastruktur kawasan;
p. Infrastruktur pariwisata;
q. Infrastruktur kesehatan;
r. Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan
s. Infrastruktur perumahan rakyat.
Pasal 6 mengatur bahwa menteri/kepala lembaga/kepala
daerah bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama (PJPK), serta Pasal 8 memungkinan BUMN
bertindak sebagai PJPK, dengan demikian dalam konteks
ini dapat dikatakan bahwa KPBU berdasarkan prakarsa
pemerintah/pemerintah daerah/BUMN dapat
dilaksanakan dengan pengaturan dan batasan jenis
infrastruktur yang ditetapkan dalam peraturan ini dan
wewenang bertindak sebagai PJPK melekat secara mutlak
kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN,
yang dalam peraturan ini BUMN bertindak sebagai badan
usaha yang sesuai dengan ketetapan berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenai BUMN dan
anggaran dasar dalam hal kuasa teknis pelaksanaan
tahapan KPBU. Namun perlu dilihat bahwa terdapat
pengecualian secara teknis dalam hal KPBU diajukan atas
prakarsa badan usaha, meski tetap pengajuannya kepada
menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai PJPK
berdasarkan peraturan ini. Peraturan Mengenai
Kedudukan Lembaga Negara, Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kedutaan
Besar/Perwakilan Diplomatik, dan Organisasi
Internasiona
Pemindahan Ibu Kota Negara juga berdampak pada
kedudukan lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Republik Indonesia yang diuraikan dalam
table di bawah ini.
Di samping kedudukan-kedudukan lembaga negara yang
disebutkan di atas yang secara tegas disebutkan
berkedudukan di Ibu Kota Negara, lembaga-lembaga
pemerintah non kementerian juga perlu ditegaskan
mengenai kedudukannya sehingga pengaturan di
rancangan undang-undang menjadi signifikan.
Kejelasan yang sama juga diatur kedudukannya terhadap
kedutaan besar/perwakilan diplomatik serta organisasi
internasional. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia menyatakan bahwa Provinsi DKI
Jakarta memiliki peran yang salah satunya sebagai
tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta
pusat/perwakilan lembaga internasional, sehingga
dengan demikian apabila keduataan besar/perwakilan
diplomatik dan organisasi internasional memiliki opsi
untuk memindahkan kedudukan yang dapat dikecualikan
apabila diatur secara tegas agar juga ikut pindah dalam
rancangan undang-undang.
E. Undang-Undang yang Terdampak RUU IKN dalam
Kaitannya dengan Omnibus Law
Bagian ini menganalisis Peraturan Perundang-undangan
yang terdampak dari diundangkannya RUU IKN, yakni
sejauh apa materi muatan yang akan diatur oleh RUU IKN
berdampak terhadap materi muatan peraturan
perundang-undangan lain. Dampak itu berkaitan
dengan penyebutan istilah Ibu Kota Negara yang disematkan
pada Jakarta dan juga dampak pengaturan dari RUU IKN
terhadap Peraturan perundang-undangan lain. Hal ini
nantinya akan berkaitan konsep "Omnibus Law" yang akan
digunakan di dalam RUU IKN.
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 399 Undang-Undang ini menyebut "Provinsi Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta" sehingga dengan
diundangkannya RUU IKN dan ditetapkannya
pemindahan IKN berdasarkan RUU a quo, maka perlu ada
perubahan terhadap Pasal ini.
2. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI
Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Sebagai Undang-Undang
yang mengatur Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, tentu
akan ada banyak dampak dari dari diundangkannya RUU
IKN terhadap Undang-Undang ini. Setidaknya ada 27
pasal yang berhubungan dengan Jakarta sebagai IKN.
Harus diadakan perubahan menyeluruh terhadap
Undang-Undang ini dengan diundangkannya RUU IKN;
3. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahDaerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dengan
diundangkannya RUU IKN, Undang-Undang ini harus
diubah sebab sebagian wilayah Provinsi Kalimantan
Timur dijadikan wilayah IKN.
4. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kutai
Kartanegara; Dengan diundangkannya RUU IKN, UndangUndang ini harus diubah sebab sebagian wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan wilayah IKN.
5. UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan diundangkannya RUU IKN, Undang-Undang ini
harus diubah sebab sebagian Kabupaten Penajam Paser
Utara dijadikan wilayah IKN.
6. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal
5 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa Bank
Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik
Indonesia. Pasal ini harus diubah mengingat rencana
bahwa Lembaga negara/Kementerian Negara/Lembaga
Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan tetap di
Jakarta.
7. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur
bahwa LPS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia. Pasal ini harus diubah mengingat rencana
bahwa Lembaga negara/Kementerian Negara/Lembaga
Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan tetap di
Jakarta.
8. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
keuangan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur
bahwa OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pasal ini harus diubah mengingat
rencana bahwa Lembaga negara/Kementerian
Negara/Lembaga Pemerintah di bidang ekonomi dan
keuangan tetap di Jakarta.
9. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Pasal 2 Undang-Undang ini mengatur bahwa Kementerian
Negara berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia. Pasal ini harus diubah mengingat rencana
bahwa Lembaga negara/Kementerian Negara/Lembaga
Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan tetap di
Jakarta
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun
2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi. RUU IKN mengatur pengelolaan aset
Pemerintah Pusat yang ada di Jakarta sebagai sumber
pembiayaan pembangunan IKN dan dikerjasamakan
dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan
aset ini akan mengubah kondisi zonasi di DKI
Jakarta pada tempat di mana adanya aset Pemerintah
Pusat sehingga peraturan perundang-undangan tentang
detail tata ruang dan zonasi di Provinsi DKI Jakarta harus
disesuaikan.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Dengan
diundangkannya RUU IKN, Undang-Undang ini harus
diubah sebab sebagian wilayah Provinsi Kalimantan
Timur dijadikan wilayah IKN. Dengan demikian, seluruh
peraturan-perundang-undangan di Kalimantan Timur
tentang tara ruang harus disesuaikan, sebab baik batas
wilayah dan peruntukannya berubah.
A. Landasan Filosofis
Berdasarkan Lampiran Angka 2 UU No. 12/2011, landasan
filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita
hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah
bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Dengan demikian, pada bagian ini, yang penting untuk diuji
adalah sejauh mana Rancangan Undang-Undang tentang Ibu
Kota Negara telah sesuai atau setidak-tidaknya tidak
bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945. Jelas, tidak ada satu pun dari uraian-uraian
dari Naskah Akademik ini pada bagian sebelumnya yang
melanggar Pancasila, yang ada justru usaha perwujudan silasila Pancasila. Tidak ada satu pun uraian yang melanggar
prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada satu pun uraian
yang melanggar prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip Persatuan
Indonesia, tidak ada satu pun uraian yang melanggar prinsip
Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan, dan akhirnya tidak ada satu
pun uraian yang melanggar prinsip Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia.
Justru, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu
Kota Negara ini adalah usaha untuk mewujudkan 2 dari 4
tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum.
Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur tentang tata
kelola pemerintahan Ibu kota Negara yang lebih baik, baik
dari segi pemerintahan maupun dimensi penataaan ruang
dan lingkungan hidup. Dari situ tentu akan dapat melindungi
warga negara Indonesia di wilayah Ibu Kota Negara dari
ancaman bencana ekologis, tindak kejahatan, korupsi
sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
akhirnya dapat memajukan kesejahteraan umum.
B. Landasan Yuridis
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada,
yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin
kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan
yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan
substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk
Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa
persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah
ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang
tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari UndangUndang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya
sudah ada namun tidak memadai, atau peraturannya memang
sama sekali belum ada.
Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan pada bagian
sebelumnya, sudah cukup jelas diuraikan bahwa Rancangan
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini akan mengisi
kekosongan hukum sebab hingga 75 tahun Indonesia
merdeka, Indonesia belum memiliki satu pun UndangUndang pokok yang mengatur tentang Ibu Kota Negara.
Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik
Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961
jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut,
berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta
sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 11
Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang
masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU No. No. 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 itu
sesungguhnya adalah Undang-Undang yang menetapkan
Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya
diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan
susunan pemerintahan di Jakarta menyesuaikan penetapan
ini . Materi muatan RUU yang akan disusun
berdasarkan Naskah Akademik ini akan menyusun kerangkat
utuh normatif tentang pengelolaan Ibu Kota Negara.
Di samping itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota
Negara ini akan mengatasi persoalan hukum berupa otonomi
khusus yang melekat pada pemerintahan Ibu Kota Negara.
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta sedang menyusun Naskah Akademik untuk
Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 dalam rangka
mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai
beberapa hal terkait urusan pemerintahan yang dalam
praktiknya menemui keruwetan akibat posisi Jakarta yang
berperan ganda, yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu
Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah
pusat. Dengan demikian, RUU yang disusun berdasarkan
Naskah Akademik ini akan mengatasi persoalan hukum
ini .
C. Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan
yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris
mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan
masyarakat dan negara.
Uraian pada BAB II telah menguraikan dengan rinci
bagaimana penerapan teori-teori, asas/prinsip, dan gagasangagasan mengenai tata kelola pemerintahan akan
menyelesaikan masalah yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam aspek ekonomi dan bisnis, penataaan
ruang, penatagunaan tanah, pemerintahan yang bersih dari
korupsi, lingkungan hidup yang lebih baik, ketahanan
terhadap bencana yang mumpuni, dan pencegahan kejahatan
yang lebih mantap.
Dari sisi negara, tentu tata kelola Ibu kota Negara yang akan
dituangkan di dalam RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi
kebutuhan yang mendesak agar seluruh administrasi
pemerintahan IKN dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan
efisien.
Seluruh materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang
Ibu Kota Negara sebagai satu kesatuan akan menyasar
tujuan-tujuan (objectives) dari kehidupan bernegara
sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
memajukan kesejahteraan umum.
Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur tentang tata
kelola pemerintahan Ibu kota Negara yang lebih baik, baik
dari segi pemerintahan maupun dimensi penataaan ruang
dan lingkungan hidup. Dari situ tentu akan dapat melindungi
warga negara Indonesia di wilayah Ibu Kota Negara dari
ancaman bencana ekologis, tindak kejahatan, korupsi
sekaligus dapat memajukan kesejahteraan umum.
Rancangan Undang-Undang ini akan menata kembali
berbagai benang kusut penataan perkotaan holistik dan
modern, tata kelola lingkungan hidup, penanggulangan
bencana, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik,
tangkas, dan berorientasi pada pemecahan masalah publik
serta pelayanan publik yang baik. Ibu Kota Negara
diharapkan dapat menjadi contoh baik untuk kota yang
modern, berteknologi tinggi, dengan tata kelola pemerintahan
sangat baik, dan berwawasan pembangunan berkelanjutan
baik di Indonesia maupun di dunia.
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Beberapa pokok-pokok yang akan diatur di dalam Rancangan
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara antara lain
meliputi: ketentuan tentang kedudukan, pembentukan,
fungsi, prinsip, dan cakupan wilayah, ketentuan tentang
pembagian wilayah, ketentuan tentang Kegiatan Pemindahan
Ibu Kota Negara; ketentuan tentang Bentuk, Susunan, dan
Urusan Pemerintahan Ibu Kota Negara; ketentuan tentang
kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan
perwakilan organisasi internasional, ketentuan tentang Tata
Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan
Bencana; dan ketentuan terkait Pendanaan dan pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja.
Sebagai Undang-Undang yang mengatur sesuatu secara
umum dan abstrak, maka nantinya diperlukan beberapa
peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana
dari Undang-Undang ini . Hal itu dikarenakan tidak
semua hal teknis akan dapat ditampung dan diatur secara
komprehensif di dalam materi-materi muatan pasal UndangUndang. Jenis peraturan perundang-undangan yang akan
menjadi peraturan pelaksana adalah peraturan presiden.
Di samping itu, kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara
dilakukan dengan mempertimbangkan kerja sama dengan
Pemerintah Daerah Ibu Kota Negara sebelumnya, yaitu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang
Materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota
Negara akan mencakup tiga hal, yaitu Ketentuan Umum,
Materi yang Akan Diatur, dan Ketentuan Peralihan. Ada pun
ruang lingkup dari materi muatan Undang-Undang Ibu Kota
Negara yaitu:
Bab I: Ketentuan Umum
Beberapa hal yang diatur di dalam Bab ini antara lain
pembatasan definisi terhadap beberapa istilah yang
digunakan di dalam Undang-Undang ini:
1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan
fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat
serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah Ibu Kota Negara sebelumnya, yaitu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang
Materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota
Negara akan mencakup tiga hal, yaitu Ketentuan Umum,
Materi yang Akan Diatur, dan Ketentuan Peralihan. Ada pun
ruang lingkup dari materi muatan Undang-Undang Ibu Kota
Negara yaitu:
Bab I: Ketentuan Umum
Beberapa hal yang diatur di dalam Bab ini antara lain
pembatasan definisi terhadap beberapa istilah yang
digunakan di dalam Undang-Undang ini:
1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan
fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat
serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara yang
selanjutnya disingkat KSN IKN adalah kawasan khusus
yang akan dan menyelenggarakan fungsi sebagai Ibu
Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan
Undang-Undang ini.
7. Ibu Kota Negara […] yang selanjutnya disebut sebagai
IKN […] adalah suatu wilayah di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang menjadi tempat kedudukan Ibu
Kota Negara dan menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota
Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan
Undang-Undang ini.
8. Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara […]yang
selanjutnya disebut sebagai Pemerintahan Khusus IKN
[…] adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus di
IKN […] yang diatur dengan Undang-Undang ini.
9. Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut
sebagai Otorita IKN adalah lembaga pemerintah
setingkat kementerian yang dibentuk untuk
melaksanakan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara yang baru, serta
penyelenggaraan Pemerintahan Khusus IKN […].
10. Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut
sebagai Kepala Otorita IKN adalah pimpinan Otorita IKN
yang berkedudukan setingkat menteri yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN
dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan
Pemerintahan Khusus IKN […].
11. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang selanjutnya
disebut sebagai Wakil Kepala Otorita IKN adalah wakil
pimpinan yang bertugas membantu Kepala Otorita IKN
atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN dalam
pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan
Khusus IKN […].
12. Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Negara adalah
dokumen perencanaan terpadu untuk melaksanakan
pembangunan, pemindahan dan pengelolaan Ibu Kota
Negara […] yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
13. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja
Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Bab II: Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan,
Fungsi, Prinsip, dan Cakupan Wilayah
Bab ini mengatur tentang Ibu Kota Negara berkedudukan di
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Bab ini juga akan
mengatur tentang pembentukan dan pemindahan status,
fungsi dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan
prinsip-prinsip pembangunan Ibu Kota Negara. Selanjutanya,
Bab ini juga mengatur tentang cakupan dan penataan
wilayah.
Bab III: Bentuk, Susunan, dan Urusan Pemerintahan
Bab ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Khusus oleh Otorita IKN beserta susunan pemerintahan di
bawahnya dan urusan yang menjadi kewenangangannya.
Bab IV: Pembagian Wilayah
Bab ini mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Khusus IKN [...], Kepala Otorita IKN memiliki kewenangan
untuk membagi wilayah IKN [...] menjadi wilayah-wilayah
yang bentuk, jumlah dan strukturnya disesuaikan dengan
kebutuhan, yang ketentuan pembagian wilayahnya ini
diatur dengan Peraturan Presiden.
Bab V: Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan
Belanja
Bab ini mengatur APB untuk Pemerintahan Khusus IKN.
Bab VI: Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup,
Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan
Bab ini mengatur secara umum tentang penataan Ruang,
Pertanahan, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana,
dan Pertahanan dan Keamanan di IKN.
Bab VII: Pemindahan Ibu Kota
Bab ini mengatur pengaturan umum tentang Pemindahan Ibu
Kota Negara.
Bab VIII: Ketentuan Peralihan
Bab ini mengatur bahwa Sejak Undang-Undang ini
ditetapkan sampai dengan tanggal penetapan status Ibu Kota
Negara), kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap
berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Di
samping itu, Otorita IKN yang menyelenggarakan
Pemerintahan Khusus IKN [...] berdasarkan Undang-Undang
ini melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita IKN
yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan sebelum Undang- Undang ini
ditetapkan. Selanjutnya, Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala
Otorita IKN yang diangkat berdasarkan peraturan perundangundangan sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini, pada
tanggal penetapan status Ibu Kota Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditunjuk dan diangkat
sebagai Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN yang
pertama oleh Presiden untuk menyelenggarakan
Pemerintahan Khusus IKN [...].
Bab IX: Ketentuan Penutup
Bab ini adalah materi Omnibus Law di mana sejumlah pasal
di dalam Undang-Undang lain akan diubah atau dicabut
melalui RUU IKN. Di samping itu, Bab ini juga
mengamanatkan penyesuaian-penyesuaian. Adapun
peraturan perundang-undangan ini yaitu:
1. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan
Timur disesuaikan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.
2. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara
disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
3. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur
dan Kota Bontang disesuaikan dengan ketentuan dalam
Undang- Undang ini.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) disesuaikan selambat- lambatnya 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini ditetapkan.
Di samping itu, Bab ini juga akan mengatur tentang
keberlakukan seluruh atau sebagian materi muatan pasal
RUU IKN.









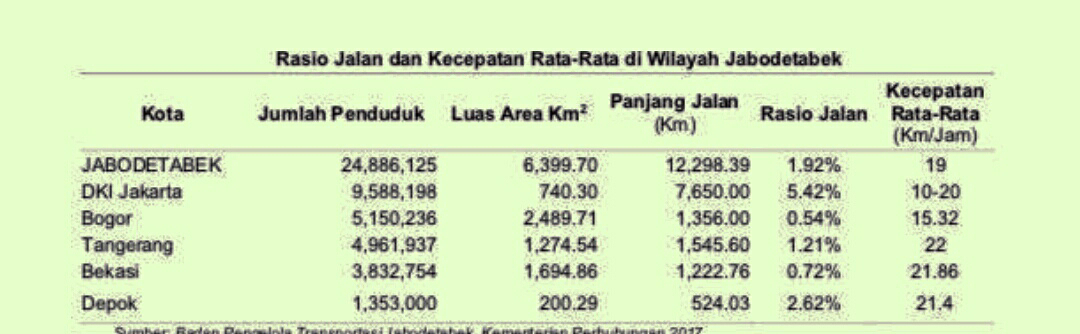



.jpg)









