Kamis, 15 Juni 2023
Home »
jakarta. 1
» jakarta 1
jakarta 1
By Lampux.blogspot.com Juni 15, 2023
awalnya merupakan penetapan yang bersumber pada kebiasaan
dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Jakarta sejatinya adalah
warisan dari VOC dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda buah
dari pengembangan kota pelabuhan ‘Jayakarta’ pada tahun 1619.
Pemilihan lokasi ibu kota Hindia Belanda ini didasari oleh
pertimbangan kepentingan administrasi dari VOC yang saat itu
memiliki hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial
di wilayah ini yang diberikan oleh Parlemen Belanda sejak
tahun 1602. Berdiri dan berkembangnya benteng serta
permukiman orang Belanda kemudian menjadi cikal bakal Jakarta
yang saat itu diberi nama Batavia. Secara resmi, pemerintah kota
Batavia (Stad Batavia) dibentuk pada 4 Maret 1621. Selama 8 tahun
kota Batavia sudah meluas 3 kali lipat. Pembangunannya selesai
pada tahun 1650. Sebagai pusat kegiatan orang-orang Belanda di
Hindia Belanda, Batavia kemudian dikenal dengan sebutan ‘Queen
of the East’ yang merepresentasikan kepentingan Belanda terkait
perdagangan.
Di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia
diubah oleh pemerintah militer Jepang menjadi ‘Jakarta’. Hal ini
dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menarik hati penduduk
Indonesia. Seiring dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta
sebagai ibu kota Republik Indonesia. Dalam perjalanannya sempat
terjadi perpindahan ibu kota sebab adanya perjanjian dengan
pihak penjajah Belanda serta sebab kondisi darurat selama masa
perang kemerdekaan 1945 – 1949. Namun kemudian Ibu Kota
kembali ke Jakarta untuk seterusnya seiring dengan penyerahan
kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949,
yang berlaku hingga saat ini. Perjalanan sejarah menunjukkan
bahwa penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota adalah kebiasaan dan
praktik pemerintahan de facto sepanjang sejarah.
Secara de jure baru sejak 1961, Jakarta ditetapkan sebagai
Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan
Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Setelah
itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan
Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No.
11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang
masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU No. No. 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun demikian, hingga kini, belum ada satupun undangundang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara.
Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 adalah
Undang-Undang yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota
Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal
mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di
Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan ini . Sehubungan
dengan itu, belakangan ini Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun Naskah
Akademik untuk Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 dalam rangka
mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal
terkait urusan pemerintahan yang pada praktiknya memunculkan
akibat peran ganda Jakarta, yakni sebagai daerah otonom khusus
Ibu Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Keperluan menyusun undang-undang yang mengatur secara
spesifik tentang Ibu Kota Negara ("IKN") juga bersesuaian dengan
momentum Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
pada 16 Agustus 2019 dan disusul dengan Pengumuman
Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019
di Istana Negara. Pemindahan itu didasarkan pada Kajian yang
telah dilakukan Bappenas, yang menyimpulkan bahwa performa
Provinsi DKI Jakarta sebagai IKN, DKI Jakarta sudah tidak lagi
dapat mengemban peran sebagai IKN dengan optimal dengan
semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali,
penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat
kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan
persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau
Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian, Naskah Akademik ini sangat mendesak
untuk disusun sebagai acuan untuk pembentukan Rancangan
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ("RUU IKN"), sebagai
Undang-Undang yang menjadi landasan hukum awal dari usaha
pemindahan Ibu Kota Negara. Naskah Akademik ini juga diperlukan
untuk menjelaskan dengan runut dari rinci mengenai argumentasi
pilihan kebijakan menjadi norma di dalam materi muatan pasal.
Pilihan kebijakan dan materi muatan pasal itu dijelaskan secara
rasional dengan prosedur yang ilmiah. Penjelasan itu harus dimulai
dari kajian teoritis, kajian terhadap Asas/Prinsip, kajian terhadap
praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, pemasalahan yang
dihadapi, serta perbandingan negara lain, kajian terhadap implikasi
terhadap sistem aru yang akan diatur dalam RUU terhadap aspek
beban keuangan negara dan kemanfaatan negara,
Selanjutnya, perlu ada evaluasi dan analisis peraturan
perundang-undangan terkait, mulai dari peraturan perundangundangan terkait Kegiatan pemindahan dan pembangunan Ibu
Kota Negara, peraturan perundang-undangan terkait bentuk dan
susunan pemerintahan Ibu Kota Negara, peraturan perundang-undangan terkait tata Ruang, infrastruktur, dan lingkungan hidup
Ibu Kota Negara, dan peraturan perundang-undangan terkait
keuangan IKN, dan peraturan perundang-undangan terkait
kegiatan pemindahan IKN. Selanjutnya, sebagai basis legitimasi
dari sebuah Undang-Undang, perlu ada penjelasan tentang
landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari RUU tentang Ibu
Kota Negara, sehingga sasaran, arah, jangkauan pengaturan, dan
materi muatan pasal dapat dirumuskan dengan efektif, efisien,
harmonis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, serta
dapat dilaksanakan dengan baik.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas, di dalam penyusunan
Naskah Akademik mengemuka 4 (empat) pokok masalah yang
harus terjawab pada keseluruhan BAB, yaitu:
1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Ibu
Kota Negara serta bagaimana permasalahan ini
dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Ibu
Kota Negara sebagai dasar pemecahan masalah ini
– yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam
penyelesaian masalah ini ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan UndangUndang tentang Ibu Kota Negara?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari
Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara?
C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan Latar belakang dan Tujuan di atas, Naskah
Akademik ini bertujuan untuk:
1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
terkait Ibu Kota Negara serta cara-cara mengatasi
permasalahan ini ;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi
sebagai alasan pembentukan Rancangan UndangUndang tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar hukum
penyelesaian atau solusi permasalahan dalam
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan UndangUndang tentang Ibu Kota Negara;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan
dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota
Negara.
Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah
sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.
D. Metode
Pendekatan penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan
pendekatan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
("UU No. 12/2011") tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya
merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode
penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian
hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan
melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode
yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.
Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka
yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan
Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak,
atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil
pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat
dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan
rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal
adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau
penelaahan terhadap Peraturan Perundang- undangan (normatif)
yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta
penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor
nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap
penyusunan RUU IKN.
A. Kajian Teoritis
Ibu kota, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
didefinisikan sebagai kota tempat kedudukan pusat pemerintahan
suatu negara atau tempat dihimpun unsur administratif eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Keberadaan ibu kota dalam suatu negara
biasanya menjadi simbol identitas bangsa yang membentuk negara
ini . Bartolini (2005) mengatakan bahwa ibu kota negara
merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas
nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau
merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai
titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta
kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu
kota negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting
dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan
ini .
Rossman (2017) menyatakan bahwa konsep ‘nation states’
kembali berkembang saat ini, dilihat dari usaha pemindahan Ibu
Kota di 40 negara yang menggambarkan masih kuatnya keterkaitan
antara negara dan rasa nasionalisme. Untuk negara-negara maju
khususnya di Barat, keberadaan ibu kota lebih dipandang sebagai
kebutuhan pengaturan administratif dan tata kelola negara. Namun
untuk negara-negara seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang
sedang dalam proses pembangunan bangsa dan negara,
keberadaan ibu kota menjadi hal yang sensitif dan dianggap sebagai
penguat bagi simbol-simbol kebangsaan, pemersatu, serta
pemerataan pembangunan fisik dan ekonomi wilayah suatu negara.
Pertimbangan lokasi dalam pemilihan suatu ibu kota secara
tidak langsung mencerminkan pola pikir para pengelola (atau
pendiri) negara. Spanyol memiliki Madrid yang terletak di tengah
negara, dimana pertimbangannya antara lain untuk kemudahan
kontrol wilayah negaranya. Nigeria membangun ibu kota baru pada
tahun 1991 di Abuja yang berada di tengah negara ini untuk
menggantikan Lagos yang berada di garis pantai ujung Barat Daya,
dengan alasan untuk menekankan persatuan negara yang memiliki
keragaman etnis dan agama ini . Brazil juga memindahkan ibu
kotanya dari kawasan pantai di Rio de Janeiro ke bagian tengah
benua Amerika pada tahun 1961, menjadi Ibu kota baru yang
disebut Brasilia, yang menurut sang perancang ibu kota, Oscar
Niemeyer, dibangun dengan tema "membawa kemajuan ke kawasan
pedalaman Brazil".
Ada juga pertimbangan kompromi politik yang mendasari
pemilihan suatu ibu kota negara. Amerika Serikat menetapkan
Washington DC sebagai ibu kotanya pada tahun 1790 sesuai
dengan hasil kompromi politik. Perbedaan pandangan mengenai
lokasi yang tepat antara negara-negara bagian di Utara dengan
negara-negara bagian di Selatan pada akhirnya diselesaikan oleh
George Washington yang memilih lokasi di sekitar perbatasan
negara- negara bagian yang terletak di tepi Sungai Potomac
sebagaimana dikenal sekarang.
Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang diharapkan adalah
Ibu Kota yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Negara
Indonesia yang berpenduduk sekitar 237 juta jiwa, memiliki
warisan kekayaan sekitar 1100 suku bangsa, 700 bahasa lokal, 300
gaya seni tari, 400 lagu daerah, dan 23 lingkungan adat, hidup
sebagai bangsa dan negara dalam berbagai keragaman dan
perbedaan yang berjalan baik selama ini, sebab didasari oleh
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, dan dibingkai
melalui Bhinneka Tunggal Ika.
Identitas dan karakter bangsa Indonesia telah ditorehkan
para bapak bangsa berdasarkan pemahaman sejarah panjang
bangsa Nusantara dalam membangun karakter Indonesia. Dalam
amanat Proklamasi, 17 Agustus 1956, Bung Karno mengingatkan
pentingnya bangsa yang berkarakter memiliki kepercayaan pada
nilai-nilai kepribadian dan kemandirian bangsa sendiri. Dimensi
moral sebagai tumpuan karakter kolektif yang dapat menopang
kemajuan peradaban bangsa ini adalah Pancasila. Kelima sila
yang menyatukan bangsa Indonesia, adalah yang memandu
perkembangan bangsa ke depan (Soekarno, 1958). Peran Pancasila
sebagai ideologi negara mampu menjadi payung pemersatu bagi
warganya yang majemuk. Makna Bhinneka Tunggal Ika bukan
hanya dimaknai mewakili keberagaman agama, tapi suku, bahasa
dan semua keberagaman di Indonesia.
Memperhatikan pentingnya aspek simbolisasi negara melalui
ibu kota ini, memunculkan kebutuhan rancangan Ibu Kota Negara
Republik Indonesia yang dapat merepresentasikan identitas dan
persatuan bangsa dalam kerangka nation and state building;
merefleksikan kebhinnekaan Indonesia; dan meningkatkan
penghayatan terhadap Pancasila.
Membangun dan menata kembali Ibu Kota Negara tentunya
memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka
panjang suatu bangsa. Pengembangan ibu kota baru biasanya
dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan
kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu
kota ini . Paradigma perencanaan dan pengembangan kota
baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting
dalam pengembangan ibu kota negara di lokasi yang baru.
Paradigma pembangunan kota baru yang berkembang pada abad
ini adalah kota modern dan berkelanjutan. Keduanya dapat
memiliki makna yang saling melengkapi.
A.1. Kota Modern
Konsep modern diartikan oleh berbagai ahli seperti Webber,
Harrod dan Domar, Rostow, Hoselitz, hingga Inkeles dan Smith,
sebagai suatu karakteristik yang lebih maju, berkembang, tidak
tradisional, maupun bentuk transisi: dari perdesaan ke perkotaan
dan dari pertanian ke industri1. Kota modern merupakan kota yang
secara sosiologis berkembang lebih maju, yang mendorong
warganya untuk turut berkembang lebih modern, global, dengan
suatu cita-cita bersama.
Karakteristik kota modern (modern city) adalah adanya
masyarakat modern di suatu kota yang memiliki tujuan masa depan
bersama yang berpikir jauh ke depan (forward thinking), yang
ditindak lanjuti dengan usaha -usaha inovatif melalui pemanfaatan
teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan kota, perancangan
dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi permasalahan
sosial perkotaan. Kota modern juga memiliki karakteristik sebagai
kota yang terencana, yang terukur dalam setiap tahap
pengembangan dan target pencapaiannya.
A.2. Kota Berkelanjutan
Paradigma kota modern memiliki keterkaitan yang erat
dengan paradigma kota berkelanjutan (sustainable city). Brundtland
Report dalam sidang PBB tahun 1987 mendefinisikan
pembangunan berkelanjutan sebagai proses pembangunan yang
berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan
kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Berkelanjutan juga
didefinisikan sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola
untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan,
sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem
lingkungan alami, terbangun, dan sosial (European Commission,
1996).
Agenda pembangunan berkelanjutan untuk perkotaan telah
dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals) 2030. Agenda pembangunan kota
dan permukiman dalam SDGs, bertujuan mewujudkan perkotaan
dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan
berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs untuk pembangunan kota
yang berkelanjutan, meliputi pembangunan perumahan,
mengedepankan transportasi umum, permukiman, perlindungan
warisan alam dan budaya, peningkatan mitigasi dan adaptasi
terhadap kebencanaan, membangun lingkungan kota yang bersih,
dan membangun ruang publik yang aman, inklusif, terjangkau.
Agenda Perkotaan Baru/New Urban Agenda (NUA),
merupakan agenda perkotaan yang melengkapi Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
(SDGs), merupakan kesepakatan kota-kota di dunia yang bertujuan
untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang memberikan
hak dan kesempatan yang sama, mendorong inklusivitas dan
memastikan setiap penduduk tanpa diskriminasi mampu
menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang
berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau,
berketahanan, dan berkelanjutan. Agenda Perkotaan Baru fokus
pada (1) Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Untuk Kohesi
Sosial, Inklusif, dan Mengakhiri Kemiskinan melalui penyediaan
perumahan, air bersih dan pengolahan limbah serta ruang-ruang
publik; (2) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Peluang
Peningkatan Kesejahteraan Secara Inklusif dan Berkelanjutan
melalui transportasi terpadu dan terintegrasi, listrik dan teknologi
telekomunikasi, energi terbarukan, serta (3) Pembangunan
lingkungan berkelanjutan dan kota yang berketahanan melalui
ruang terbuka hijau yang memiliki ketahanan terhadap
bencana, pengelolaan sumber daya air, limbah dan sampah yang
ramah lingkungan dan berjangka panjang, pelayanan dan
pemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur, permukiman,
industri, dan komersial, serta pengembangan teknologi untuk
mendukung semuanya
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
tahun 2015-2019, arahan kebijakan sangat jelas untuk
membangun Kota Berkelanjutan dan berdaya saing, dengan lima
kebijakan utamanya, yaitu: (1) perwujudan Sistem Perkotaan
Nasional (SPN), dengan kawasan metropolitan baru di luar Jawa
yang didorong sebagai pusat pertumbuhan melayani Kawasan
Timur Indonesia, dan kawasan metropolitan yang sudah ada untuk
menjadi pusat berskala global; (2) Percepatan pemenuhan Standar
Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk kota aman, nyaman, layak huni,
dengan menyediakan sarana prasarana dasar, ekonomi, kesehatan
dan pendidikan, permukiman dan transportasi publik; (3)
perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana,
dengan penataan ruang, penyediaan sarana prasarana berkonsep
hijau dan berketahanan; (4) Pengembangan kota cerdas yang
berdaya saing, berbasis teknologi, dan budaya lokal; serta (5)
peningkatan kapasitas tata kelola kota. Dengan misi pembangunan
perlunya pengurangan kesenjangan dan usaha pemerataan keluar
Jawa, maka Ibu Kota baru sebagai salah satu pusat pertumbuhan
baru diharapkan dapat membawa misi sebagai kota masa depan
yang berkelanjutan.
A.3. Kota Berkelas Internasional
Seiring dengan perkembangan paradigma kota modern dan
berkelanjutan, globalisasi juga telah menunjukkan adanya
paradigma kota-kota dunia untuk berkembang menjadi kota
berkelas internasional. Kota berkelas internasional adalah kota
yang memiliki infrastruktur dengan standar global dan terkoneksi
dengan kota-kota lain di dunia yang menjadi pusat bisnis, budaya,
teknologi, maupun politik secara global. Kota berkelas internasional
adalah kota yang memiliki peran yang berarti di dunia
internasional, sehingga kota-kota di negara lain memiliki keinginan
untuk terkoneksi dengannya.
Sedangkan Ibu Kota berkelas internasional pada umumnya
meliputi infrastruktur transportasi, taman dan ruang terbuka atau
taman hutan kota, kegiatan-kegiatan kebudayaan, obyek wisata,
monumen-monumen bersejarah dan museum, hotel dan akomodasi
berkelas internasional, kenyamanan sebuah kota yang
berkelanjutan, keterjangkauan ‘cost of living’, infrastruktur dan
kegiatan olahraga internasional, pusat-pusat konvensi dan
pameran berkelas internasional, dan lainnya.
Keanggotaan Indonesia dalam organisasi-organisasi
internasional dan regional, seperti anggota berbagai organisasi PBB,
anggota G-20, anggota Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia
Pasifik (APEC), anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan
ASEAN; serta keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam berbagai
perjanjian dan konferensi internasional dan regional, menuntut
Indonesia untuk memiliki Ibu Kota yang selalu siap dalam
penyelenggaraan berbagai even internasional.
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip
Asas/Prinsip dalam pembentukan norma untuk mengatur
Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa depan
bersumber dari 1) asas pembentukan peraturan perundangundangan sebagaimana yang tercantum di dalam UU 12/2011 dan
juga 2) asas perencanaan perkotaan yang bersumber dari berbagai
best practices pengembangan Ibu Kota Negara di berbagai belahan
dunia. Beberapa best practices pengembangan Ibu Kota yang
mengadopsi konsep pembangunan Ibu Kota tertentu, yang dapat
dipelajari di berbagai belahan dunia. Konsep-konsep itu antara lain
Beautiful City (Washington D.C), Radiant City (Brasilia), Garden City
(Canberra dan Abuja), Green City (Gaborono and New Kabul), serta
penerapan konsep Intelligent City (Putrajaya), Eco-city (Sejong), dan
Smart City (Rencana Ibu Kota Mesir).
B.1. Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011, seluruh peraturan
perundang-undangan, termasuk RUU IKN, harus dibentuk dengan
berdasarkan pada asas:
1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.
Di samping itu, berdasarkan Pasal 6 UU yang sama, materi muatan
di dalam RUU IKN harus mencerminkan asas:
1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
B.2. Asas/Prinsip Perencanaan Kota
B.2.1.Beautiful City
Konsep Beautiful City lebih dikenal dengan istilah City
Beautiful Movement, merupakan filosofi reformasi kota yang
berkembang di dunia arsitektur dan perencanaan kota
sebagaimana dikemukakan Daniel H. Burnham (1910) yang
menekankan pada perbaikan kota dengan mempercantiknya
(beautification). Perbaikan ditekankan pada sektor sanitasi, estetika
lingkungan, pembangunan civic centre, dan desain bangunan.
Burham dan Benetts (1909) menerapkan konsep ini di kota Chicago.
Sistem jaringan jalan dibangun secara diagonal dan melingkar yang
dirancang untuk memudahkan pengendara menghindar dari
kemacetan. Contoh penerapan konsep beautification pada
pengembangan ibu kota negara dapat dilihat di Amerika Serikat,
yang terjadi pada ibu kota Washington D.C3. Penekanan pada
keindahan kota adalah untuk membangun standar moral
masyarakat perkotaan melalui harmoni sosial dan kualitas hidup
masyarakat. Namun, dikritik sebab dianggap mengesampingkan
usaha reformasi sosial yang sesungguhnya.
B.2.2.Radiant City
Radiant City dikembangkan melalui pemikiran Le Corbusier
(1924) yang mengkombinasikan desain geometris dan efisiensi
ruang guna mewujudkan kota kompak yang terbagi/terseparasikan
secara tersusun dengan pola yang simpel dan rasional. Konsep ini
menekankan usaha untuk melakukan efisiensi ruang dan
pemanfaatan energi.
Contoh ibu kota negara yang menggunakan konsep ini adalah
Brasilia di Brasil, yang termasuk dalam daftar World Heritage dari
UNESCO. Brasilia dibangun dalam tempo 41 bulan sejak tahun
1956 hingga peresmian pada tahun 1960. Lokasinya di wilayah
relatif kosong dan dikembangkan untuk mendorong pengisian
ruang di bagian wilayah Brasil yang masih kosong (pemerataan
penduduk dan ekonomi). Desain kota dibentuk oleh struktur
jaringan jalan dan pengaturan lahan yang menyerupai pesawat
terbang. Pusat kota terdiri dari sejumlah blok dan sektor kegiatan
yang berbaur dan menciptakan efisiensi transportasi antar kawasan
fungsional. Konsep ini dikritik sebab lebih terfokus pada kawasan
pusat kota dan pertimbangan fisiknya, melupakan dampak
perkembangan perkotaan yang terjadi di kawasan pinggiran.
B.2.3. Gardern City
Konsep Garden City yang dirumuskan oleh Ebenezer Howard
(1876) memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep sebelumnya,
yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar
tempat tinggalnya. Prinsip utama konsep Garden City adalah
merancang sebuah kawasan menjadi kota yang hidup, energik dan
aktif, dihiasi oleh keindahan dan suasana kawasan desa (atau
pinggiran kota). Perbedaannya dengan konsep beautiful city dan
radiant city, konsep garden city mempertimbangkan pengembangan
wilayah pinggiran kota. Howard mencoba mengkombinasikan unsur
kota yang energik dengan unsur permukiman desa yang sehat dan
tentram. Tujuan utama perancangan adalah untuk memberi
kesempatan yang sama pada setiap penduduk kota untuk
mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat.
Konsep Garden City dalam pengembangan ibu kota telah
diterapkan antara lain di ibu kota Australia – Canberra. Rancang
kota Canberra mengarah pada penataan lingkungan dan akses
warga untuk dapat menikmati pergerakan dengan berjalan kaki
menuju pusat-pusat aktivitas, termasuk pusat pemerintahan. Tata
bangunan dan lingkungan sangat diperhatikan untuk menciptakan
visual kawasan yang menarik sekaligus memaksimalkan
pemanfaatan energi terbarukan seperti matahari dan udara untuk
pencahayaan dan meningkatkan kenyamanan penghuni. Seiring
perkembangan kota, pada era modern 1990-an dilakukan
intensifikasi lahan, dengan arah pengembangan kota difokuskan ke
pinggiran kota sebagai bentuk pemanfaatan lahan secara
berkelanjutan dan terencana.
Ibu kota Abuja di Nigeria adalah salah satu kota di dunia yang
mengembangkan planned city, atas dasar konsep garden city.
Perkembangan ibu kota yang terdiri dari fungsi-fungsi kegiatan
ditunjang oleh fasilitas ruang terbuka hijau (green area) dan fasilitas
rekreasi di setiap lingkungan (neighbourhood). Namun dalam
kenyataannya sebab kurangnya penegakan hukum, terjadi
konversi lahan dan pelanggaran penggunaan lahan yang
memicu rancangan garden city tidak tercapai.
B.2.4. Green City
Green city atau kota hijau merupakan suatu konsep
penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan pengembangan
kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya
air dan energi secara efisien, mengurangi limbah, menerapkan
sistem transportasi terpadu yang lebih efisien, menjamin kesehatan
lingkungan, serta mensinergikan lingkungan alami dan buatan.
Pembangunan kota diarahkan untuk meningkatkan kemampuan
kota dan warga kota dalam melakukan mitigasi dan adaptasi
terhadap ancaman bencana melalui keseimbangan aktivitas sosial
warga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta keberlanjutan
lingkungan alami. Green City dikenal juga sebagai konsep kota
ekologis (Eco City) dan kota sehat.
Contoh pengembangan ibu kota negara dengan konsep green
city terdapat di New Kabul (Kabul Baru) di Afghanistan. Prinsipprinsip pembangunan berkelanjutannya berusaha
menyeimbangkan aktivitas sosial dengan kebutuhan pelestarian
lingkungan melalui suatu proses adaptasi perilaku dalam
pemanfaatan energi dan penataan bangunan. Penerapan konsep ini
membutuhkan perencanaan dan manajemen pelaksanaan yang
tinggi, jauh di atas standar manajemen perkotaan yang umumnya
ada di negara berkembang.
B.2.5. Eco-City
Konsep eco-city dibangun dari prinsip hidup dalam
lingkungan alami. Tujuan utama dari pengembangan eco-city
adalah untuk mengurangi segala jenis polusi buangan gas karbon
(zero carbon activity), memproduksi energi sepenuhnya melalui
sumber energi terbarukan, dan untuk mempersatukan harmonisasi
kota dengan lingkungan alami. Eco-city juga memiliki tujuan untuk
mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan efisiensi serta peningkatan
kesehatan. Konsep ini memiliki prinsip yang sejenis dengan green
city.
Contoh ibu kota baru yang dikembangkan dengan konsep
eco-city adalah calon ibu kota Sejong di Korea Selatan.
Pembangunan kota baru Sejong seluas 73 km2 (7.300 ha), yang
diproyeksikan untuk menampung sekitar 500 ribu penduduk,
terletak di area yang sangat strategis di tengah Semenanjung Korea,
menghubungkan Seoul di Utara, Busan di Tenggara dan Gwangju
di bagian Selatan. Konsep kota ini modern dan berkelanjutan,
merupakan bentuk rancangan kota ideal di masa datang, terencana
dengan pertumbuhan yang terukur dan bertahap sehingga
mempermudah antisipasi perkembangan.
Namun demikian, kota Sejong dianggap sebagai kota yang terpisah
dari wilayah sekitarnya, menjadi kurang menarik untuk ditinggali,
serta dianggap memboroskan anggaran pembangunan di Korea
sebab ketergantungannya pada teknologi tinggi yang cukup mahal.
B.2.6. Smart City
Smart city atau kota cerdas merupakan konsep
pembangunan kota yang berusaha mengelola sumber daya dengan
efisien dan memberi pelayanan secara efektif melalui informasi yang
akurat dan dukungan infrastruktur yang dapat diakses
masyarakat. Secara umum smart city lebih dikenal sebagai konsep
pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan,
memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di
dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan
pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang
berkelanjutan. Konsep smart city ini masih terus berkembang
seiring dengan perkembangan pola pikir manusia terhadap
pengembangan kota yang semakin terintegrasi dengan pemanfaatan
teknologi.
Contoh ibu kota negara yang dikembangkan dengan konsep
ini adalah Ibu Kota baru untuk menggantikan Kairo. Diperkirakan
biaya pembangunannya akan menelan dana sebesar 90 miliar Dolar
AS. Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait masing-masing siap
menyediakan dana lima miliar Dolar AS buat membiayai rencana
ini.
Ibu kota baru akan menjadi pusat administratif Mesir, yang
terdiri dari kantor-kantor pemerintah, kantor diplomatik,
perumahan, universitas dan taman, serta jalan raya sepanjang 10
ribu kilometer. Jika ibu kota dipindahkan dari Kairo, semua gedung
pemerintahan Mesir dan kedutaan asing akan turut hijrah. Selain
menampung gedung-gedung pemerintahan, ibu kota baru ini
akan memuat sedikitnya 2.000 sekolah, kampus, dan 600 fasilitas
kesehatan.
B.2.7. Intelligent City
Intelligent city merupakan konsep smart city yang
ditambahkan dengan usaha untuk mengubah / mentransformasi
komunitas untuk menjadi lebih baik, lebih kreatif, dan terlibat
dalam proyek-proyek pengembangan komunitas pintar yang dapat
mendorong terciptanya suasana kota yang saling terkoneksi melalui
dukungan teknologi.
Salah satu contoh penerapan konsep ini adalah dalam
pengembangan ibu kota Malaysia di Putrajaya. Pembangunan kota
Putrajaya mengadopsi prinsip Islam terkait keseimbangan
hubungan manusia, yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan,
manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan manusia.
Karenanya, setiap segmen kawasan ibu kota dibangun dengan
pertimbangan kebutuhan yang saling melengkapi. Sebagai contoh,
pembangunan fasilitas perkantoran diimbangi dengan penyediaan
hunian baik dalam bentuk apartemen, townhouse, serta
kondominium yang diperuntukkan hanya untuk pegawai-pegawai
negeri mereka dengan fasilitas peminjaman yang sangat murah.
Pembangunan juga memperhatikan konsep pelestarian alam yang
terlihat dari banyaknya areal terbuka termasuk danau buatan yang
terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya, menghasilkan visual
kawasan yang menarik sekaligus memberi kenyamanan pada
lingkungan sekitar.
B.3. Asas/Prinsip Kelembagaan IKN
Aspek Kelembagaan yang perlu dipertimbangkan dalam
menyusun tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan Ibu Kota
Negara antara lain:
Aspek Pendekatan Pembangunan
§ Pembangunan ibukota baru tidak dapat secara efektif
dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah dengan
pendekatan sektor semata;
§ Bila pembangunan ibukota baru dilakukan secara sektoral
(seperti oleh Kementerian Pekerjaan Umum, atau
kementerian yang lain) akan memberikan beban koordinasi
sangat besar dan risiko tatap muka sangat tinggi
Aspek Cross Cutting Dan Kapabilitas
§ Ibukota baru merupakan wilayah kebijakan yang memiliki
Cross cutting issues sebab menyangkut lintas batas-batas
hukum, tugas dan fungsi Kementerian, Lembaga dan Daerah
§ Pengalaman ibukota baru merupakan pengalaman yang
langka bagi Indonesia, dan kapabilitas penggunaan
sumberdaya yang relatif besar.
Aspek Keunikan Nilai (Unique Value)
§ Pemindahan ibukota baru merupakan program unik terkait
infrastruktur , ekonomi, politik, birokrasi dan lain sebagainya
yang harus mampu mewujudkan nilai unik sebagai suatu
ibukota baru
§ Sumber daya pembangunan ibukota baru akan bersumber
dari cross funding antara nilai ( seperti nilai sosial , politik,
dan komersil, dll) dalam satu siklus manajemen.
Aspek Complex Public Financing
§ Pembangunan ibukota melibatkan skema pembiayaan yang
sangat kompleks dan rantai jenjang yang panjang dalam
jangka waktu yang cukup panjang.
§ Pengelolaan ibukota baru yang modern dan efektif
membutuhkan tata kelola pembiayaan yang memberikan
kepastian, fleksibilitas, dan menjamin tata kelola keuangan
yang baik.
Aspek Pengelolaan Aset Dan Resiko
§ Pengelolaan ibukota baru yang modern melibatkan
pengelolaan aset jangka panjang sesuai dengan siklus
organisasi dan kebijakan
§ Perlunya integrasi manajemen antara keuangan, pengaturan
kelembagaan pembangunan dan pengelolaan, teknis dan
kinerja masa depan berkaitan dengan risiko
Aspek Complex Organization
§ Pengelolaan ibukota baru membutuhkan organisasi publik
yang berotoritas khusus yang memiliki mandat dan
kewenangan tertentu.
§ Pengelolaan ibukota baru membutuhkan organisasi publik
yang mampu melakukan kerja sama dengan swasta, dan
berbagai pihak terkait.
Aspek Multiwindow Policy
§ Pengelolaan ibukota akan memproduksi kebijakan yang
melibatkan banyak pintu , banyak organisasi.
§ Pengelolaan ibukota membutuhkan mandat organisasi jangka
panjang dan status hukum yang jelas dan transparan.
Dari berbagai aspek pertimbangan diatas, maka kelembagaan
pembangunan ibukota yang baru membutuhkan kelembagaan yang
memiliki prinsip:
1. SATU GRAND DESIGN. Satu grand design untuk memastikan
interkonektivitas dari seluruh sistem pembangunan dan
pengelolaan ibukota baru.
2. SATU ORGANISASI. Satu organisasi untuk mempersiapkan
dan melaksanakan semua komponen proyek dan pengelolaan
ibukota baru.
3. SATU JADWAL PELAKSANAAN. Satu jadwal perencanaan,
dan pelaksanaan, untuk menghindari ketidaksesuaian dan
ketidaksinkronan antar kegiatan dan antara perencanaan
dan pelaksanaan.
4. TRANSAKSI FLEKSIBILITAS. Transaksi fleksibilitas untuk
memungkinkan pelayanan publik yang fleksibel, mudah
terjangkau, dan aliran dana antar proyek dan
menggabungkan skema pelibatan pemerintah pusat, daerah,
BUMN dan sektor swasta di bawah satu payung.
Adapun sifat kelembagaan pembangunan dan pengelolaan
Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah: (1) Berstatus lembaga
pemerintah non-kementerian (LPNK) untuk persiapan dan eksekusi
pembangunannya (2) Daerah otonomnya dikelola gubernur dan
Kawasan Khusus Pusat Pemerintahannya dikelola oleh wakil
Pemerintah Pusat (3) Memisahkan regulasi dan eksekusi, (4)
Memiliki tugas unik, dan khusus/diskresi, dan bersifat multisektor
(kolaboratif).
Sementara itu, peran dan kerangka struktur kelembagaan
dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN
tergambarkan dibawah ini:
Gambar diatas menunjukkan bahwa kelembagaan
pembangunan dan pengelolaan ibukota baru akan terdiri dari (1)
Steering Committee yang berperan sebagai pengarah dan
pengawasan, dan (2) Impementing Body yang berperan sebagai
regulator, perencana, penganggar, pendelegasi, dan pengendali,
disamping berfungsi antar lembaga seperti koordinasi, perijinan,
pendanaan, hubungan antar kelembagaan. Disamping organisasi
yang berfungsi sebagai Steering Committee, dan Implementing Body,
kelembagaan pembangunan dan pengelolaan ibukota juga
dilengkapi dengan Advisor (penasihat) kepada Implementing Body,
dan dilengkapi project implementation bila dibutuhkan, dan dapat
membentuk Special Purpose Company (SPC) untuk melakukan
kerjasama dengan pihak swasta dalam skema Public Private
Partnership (PPP).
Analisa tentang kebutuhan, tugas dan peran kelembagaan
pembangunan dan pengelolaan ibukota baru sebagaimana
diuraikan diatas akan mengarahkan pada pilihan jenis
kelembagaan yang layak sebagai pilihan. Bila memilah beberapa
alternatif lembaga yang didasarkan pada tingkat kewenangan akan
ada 4 alternatif lembaga. Alternatif lembaga ini adalah (1)
lembaga yang berbentuk badan otonomi yang disebut Badan Otorita
Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibukota Negara, (2)
lembaga yang berbentuk badan koordinasi dan pengendalian
strategis, (3) menjadikan kementerian / lembaga tertentu sebagai
koordinator pengembangan ibukota baru, dan (4) pengembangan
ibukota baru dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi
kementerian / lembaga yang ada selama ini.
Bila beberapa alternatif lembaga ini dikaji dari aspek
implikasi, keunggulan dan kelemahannya maka perbandingan
antar lembaga ini dapat diuraikan oleh gambar dibawah ini:
Dari gambar ini pilihan lembaga yang sesuai dengan
kebutuhan, tugas dan peran kelembagaan pembangunan dan
pemindahan ibukota baru adalah lembaga yang berbentuk Badan
Otorita.
Badan Otorita adalah badan otonom yang memiliki
keunggulan untuk kemampuan bertindak cepat, dan kemampuan
mengintegrasikan permasalahan lintas sektor. Hal ini sesuai
dengan kebutuhan, tugas dan peran dimana lembaga dapat
mengelola anggaran secara penuh secara otonom, dan memiliki
kewenangan mengonsistenkan antara perencanaan, penganggaran
dan pelaksanaan.
Untuk pembagian tugas dan tanggung jawab dalam otoritas
badan ini maka pembagian tugas dalam Badan Otorita akan
tergambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut:
Struktur badan otoritas akan dipimpin oleh seorang ketua
badan, dan dibantu oleh 8 wakil ketua badan yang masing- masing
1 untuk sekretaris korporat, 1 untuk departemen audit, dan 6
untuk pelayanan operasional. Bila mengacu pada struktur ini ,
maka pengelolaan ibukota dikelola oleh lembaga yang profilnya
berbeda dengan profil pemerintah daerah pada umumnya bahkan
pemerintahan DKI Jakarta saat ini. Untuk itu struktur
kelembagaan pembangunan dan pengelolaan membutuhkan dasar
hukum berupa UU yang memberikan diskresi pada pemerintahan
daerah bentuk khusus. Adapun tujuan dari BO IKN adalah:
1. Melakukan pengelolaan ibukota negara yang maju, profesional,
modern, cerdas, dan inovatif,
2. Menjalankan fungsi otoritas dalam wilayah ibukota negara yang
diatur oleh UU khusus ibukota baru
3. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan
mengelola serta mengadministrasikan
wilayah ibukota negara
Adapun fungsi BO IKN:
1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan & pengusahaan di
daerah ini
2. Mempromosikan, menstimulasi, memfasilitasi dan melakukan
pembangunan komersial, infrastruktur dan
perumahan di daerah ini
3. Mempromosikan, menstimulasi dan melakukan pembangunan
ekonomi dan sosial di daerah ini
4. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kinerja kegiatan di daerah
ini .
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang
ada, pemasalahan yang dihadapi, serta perbandingan
negara lain
Bagian ini akan menguraikan tentang praktik
penyelenggaraan IKN yang hingga sebelum RUU IKN berlaku
dijalankan oleh Provinsi DKI Jakarta. Dari uraian tentang
penyelenggaraan existing ini, diharapkan penyusunan materi
muata RUU IKN dapat mengambil pelajaran sehingga dapat
mengatur dengan lebih baik. Di dalam uraian ini juga akan
dibahas kondisi yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta selama ini.
Dengan begitu, pada bagian berikutnya, dapat diadakan
perbandingan bagaimana membangun dan mengelola IKN di
berbagai negara.
C.1. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan
yang Dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota
Negara
Bagian ini akan mengkaji bagaimana sejauh ini praktik
penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang
dihadapi oleh Ibu Kota Negara yang hingga saat ini diemban oleh
Jakarta pada sektor penataan ruang, penatagunaan tanah,
pengendalian bencana, pengendalian penduduk, isu lingkungan
hidup, manajemen pengairan, serta birokrasi, tata pemerintahan,
dan mengenai sumber daya manusia.
Undang-Undang No. 29 tahun 2007 menetapkan bahwa
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta dalam
kedudukannya sebagai Ibu Kota NKRI dan sekaligus berfungsi
sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi selalu berhadapan
dengan berbagai permasalahan diantaranya urbanisasi, keamanan,
transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan
masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan
masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Permasalahan
ini muncul sebab Jakarta tidak hanya menjadi pusat
pemerintahan akan namun juga menjadi pusat semua aktivitas
antara lain pusat perdagangan, pusat jasa keuangan, pusat jasa
perusahaan, pusat jasa pendidikan, dan apabila dilihat melalui
konteks Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek) menjadi pusat
industri pengolahan.
Posisi Kota Jakarta saat ini sebagai pusat segalanya menjadi
daya tarik yang begitu besar bagi masyarakat dari seluruh
Indonesia. Kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan,
pendidikan dan berbagai fasilitas lengkap lainnya menjadi magnet
yang kuat bagi masyarakat luar kota untuk datang ke Jakarta.
Akibatnya, jumlah penduduk Wilayah Metropolitan Jakarta
(Jabodetabekpunjur) terus mengalami peningkatan setiap
tahunnya, baik dipicu pertumbuhan alami maupun faktor
migrasi.
Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017
telah mencapai 10.277.628 jiwa, dan jumlah penduduk dalam
kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur mencapai 32.775.966
jiwa, menunjukkan dominasi penduduk di Jakarta dan kawasan
metropolitan Jabodetabekpunjur terhadap kota-kota lain (Gambar
1.2). Berdasarkan data United Nations tahun 2013, jumlah
penduduk Kota Jakarta menempati ranking ke 10 kota terpadat di
dunia (Gambar 1.3), yang kemudian pada tahun 2017 meningkat
menjadi kota terpadat ke 9 di dunia (WEF, 2017).
Dengan tingginya tarikan faktor pemerintahan, ekonomi, dan
politik memicu tingginya urbanisasi yang perlu diimbangi
dengan kemampuan kota dalam memfasilitasi kebutuhan semua
penduduknya. Seiring bertambahnya penduduk berarti bertambah
pula kebutuhan akan ruang dan sarana prasarana. Kebutuhan
akan tempat tinggal, prasarana dan sarana seperti transportasi dan
air bersih merupakan kebutuhan yang semakin sulit dipenuhi di
Jakarta, dan pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin tidak
terbendung.
Bertambahnya jumlah penduduk di kawasan
Jabodetabekpunjur, dan bertambahnya jumlah kendaraan di DKI
Jakarta, maupun di kawasan permukiman di sekitar kota inti DKI
Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek),
meningkatkan tekanan pergerakan ke kota inti DKI jakarta dari
kawasan di sekitarnya seperti yang ditunjukkan pada gambar
berikut ini.
Berdasarkan kajian Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek tahun 2015, total jumlah perjalanan di wilayah
Jabodetabek tahun 2015 mencapai 47,5 juta perjalanan orang per
hari, yang terdiri dari pergerakan dalam kota DKI sebesar 23,42 juta
orang per hari, pergerakan komuter sejumlah 4,06 juta orang per
hari, sementara pergerakan yang melintas DKI Jakarta atau
internal Bodetabek mencapai 20,02 juta orang per hari. Tingginya
mobilitas penduduk dan barang di ibukota ini belum
diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum yang aman,
nyaman dan memadai.
Rasio infrastruktur jalan di wilayah DKI Jakarta hanya 5,42%
dari luas wilayah, sementara yang ideal seharusnya 15% dari luas
wilayah. Kapasitas jalan yang tidak mampu menampung beban lalu
lintas dari wilayah Bodetabek ke pusat kota, menimbulkan
kemacetan sangat tinggi, memicukecepatan rata-rata hanya
mencapai 10-20 km per jam dalam wilayah Jakarta atau 16 km per
jam pada jam sibuk (peak hour), dan hanya 19 km per jam dalam
wilayah Jabodetabek
Kemacetan di Jakarta menempati ranking ke 4 sebagai kota
terpadat didunia pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Jakarta masih
menempati peringkat ke 7 sebagai kota dengan tingkat kemacetan
tertinggi di dunia, dengan tingkat kemacetan sebesar 53% (Hasil
Survei Tomtom Traffic Index, 2018)
Kondisi kemacetan (gridlocks) Kota Jakarta merupakan yang
terburuk dengan 33.240 stop start index (Pantazi, 2015). Dampak
kemacetan di Jabodetabek saat ini menimbulkan kerugian
ekonomi, lingkungan, dan sosial yang tidak sedikit. Kerugian
ekonomi akibat kemacetan di Jakarta pada tahun 2013 sebesar Rp
56 Triliun (PUSTRAL UGM 2013). Sedangkan pada tahun 2017
kerugian akibat kemacetan di Kota Jakarta mencapai Rp 65 Triliun
(World Bank, 2017).
Tingkat kemacetan yang tinggi di Kota Jakarta menimbulkan
pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Tercatat bahwa
Jakarta berada pada rangking 1 sebagai kota dengan kualitas udara
terburuk di dunia berdasarkan Air Quality Index Value (AirVisual,
2019). Kualitas udara yang tidak sehat ini berpotensi
memberikan dampak berupa peningkatan penyakit ISPA, mata,
bahkan jantung dan stroke. Masalah depresi, stress dan gangguan
kesehatan juga meningkat sebagai akibat kemacetan dalam
komuting yang dapat berakibat pada tingkat produktivitas yang
menurun.
Keterbatasan Suplai Air Baku dan Penurunan Muka Tanah.
Kondisi sumber air baku yang tercemar di Jakarta memicu
terbatasnya suplai air baku untuk berbagai aktivitas masyarakat.
Diketahui bahwa 61% air sungai, 57% air waduk dan 12% air tanah
sudah tercemar berat sehingga berbahaya bagi kesehatan
masyarakat. Keterbatasan suplai air baku di Jakarta memicu
sebanyak 40% masyarakat Jakarta menggunakan sumur bor untuk
mendapatkan air baku.
Pengambilan air tanah yang dilakukan sebagian besar
penduduk Kota Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
memicu terjadinya penurunan tanah di daerah utara Kota
Jakarta sebesar rata-rata 7,5 hingga 10 cm per tahun. Dalam kurun
waktu tahun 2007 sampai tahun 2017 total terjadi penurunan
tanah sebesar 35 hingga 50 cm. Titik terparah penurunan tanah
terdapat di wilayah Cengkareng sebesar 69 cm dan Penjaringan
(Pluit) sebesar 94 cm.
Jakarta sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim
dipicu posisi geografisnya pada bagian utara pantai Jawa,
sehingga rawan terpapar banjir dan naiknya muka air laut. Kondisi
ini di perburuk dengan pengambilan air tanah secara
berlebihan dan pencemarannya.
Jakarta merupakan muara dari 2 kanal utama yaitu Kanal
Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur serta 13 sungai, dan hampir
73% kelurahan di Jakarta dilalui sungai, memicu nya potensi
tinggi terhadap banjir. Banjir hampir selalu terjadi pada musim
penghujan, dan banjir besar terjadi pada tahun 2002, 2007 dan
2013 . Banjir terbesar tahun 2007 menenggelamkan 40% kota,
membunuh 80 orang, dan mengungsikan sekitar 350.000 orang
(Brinkman and Hartman, 2010). Sekitar 50% wilayah Jakarta
memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan, jauh dari
kondisi ideal untuk kota besar yaitu minimum 50 tahunan.
Wilayah Jakarta yang rawan banjir sebagian besar terletak
pada bagian utara yang merupakan pesisir Kota Jakarta. Daerah
yang rawan banjir ini tergolong ke dalam klasifikasi rawan
banjir tinggi dengan jumlah rata-rata pengungsi lebih dari 500 jiwa.
Selain daerah yang berada di pesisir, daerah lainnya yang tergolong
ke dalam daerah rawan banjir adalah pada sekitar Daerah Aliran
Sungai
Salah satu faktor penyebab banjir di Jakarta adalah
penurunan tanah, yang memicumuka air laut lebih tinggi
daripada muka air aliran sungai. Berdasarkan studi penurunan
permukaan tanah yang telah dilakukan ITB (2016), menurunnya
permukaan tanah khususnya di kawasan pesisir Jakarta telah
terjadi sejak tahun 1975, dan secara signifikan pada tahun 2010–
2016 penurunan tanah sudah terjadi sebanyak 3–18 cm/tahun,
dan khususnya di Jakarta Utara penurunan muka tanah telah
terjadi rata-rata 7,5 cm/tahun. Pada tahun 2016, lebih dari 70%
lahan di Jakarta Utara sudah berada di bawah permukaan laut,
termasuk tanggul laut dan sungai. Pengambilan air tanah yang
berlebihan dipicu pesatnya pembangunan permukiman,
gedung tinggi serta kawasan industri, dan memicu ekstraksi
air tanah secara besar–besaran, menjadi penyebab utama dari
penurunan tanah ini .
Potensi Ancaman Gempa di Jakarta. Potensi gempa di
Indonesia berasal dari 2 sumber antara lain gempa yang dipicu
oleh oleh aktivitas tektonik dan gempa bumi yang dipicu oleh
aktivitas vulkanik. Sebagai daerah “Ring of Fire”, Indonesia memiliki
banyak gunung berapi. Di dekat Kota Jakarta terdapat ancaman
aktifitas Gunung Api Krakatau dan Gunung Gede yang dapat
memicu gempa vulkanik. Kedua gunung berapi ini saat
ini statusnya masih aktif, dan yang terbaru meletus adalah Gunung
Anak Krakatau pada tahun 2018. Kota Jakarta juga memiliki
potensi gempa tektonik dan Tsunami Megathrust selatan Jawa
Barat dan Selat Sunda. Selain gempa akibat aktivitas tektonik di
laut, Jakarta juga berpotensi mengalami gempa aktivitas tektonik
di daratan yaitu sesar baribis, sesar lembang, dan sesar cimandiri.
Berdasarkan permasalahan dihadapi DKI Jakarta dan
Wilayah Jabodetabek yaitu seperti laju urbanisasi yang tinggi,
kemacetan tinggi yang berimplikasi pada kualitas udara yang tidak
sehat, keterbatasan suplai air baku, banjir tahunan, dan
penurunan muka tanah serta ancaman potensi gempa.
Sehunbungan dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa daya
tampung, daya dukung lingkungan sudah sangat berat serta
adanya keterbatasan pengembangan lahan maka tidak
memungkinkan lagi wilayah DKI Jakarta menjadi Ibu Kota Negara
yang efisien dan efektif serta dapat bersaing dengan Ibu Kota negara
lain baik saat ini maupun masa depan. Untuk itu pemindahan Ibu
Kota Negara ke wilayah lain menjadi keniscayaan.
Birokrasi dan Penataan Aparatur Sipil Negara. Dalam hal
penataan aparatur sipil negara, dasar kebijakan terkait dengan
organisasi pengelolaan aparatur sipil negara yang tersedia saat ini
adalah: 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –2025; dan
2) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Regulasi ini memberikan landasan terbentuknya
organisasi aparatur sipil negara yang profesional dalam
memberikan pelayanan publik, birokrasi yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme, dan Peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk menuju pemerintahan yang
efektif, perintah Indonesia terus mendorong reformasi birokrasi
untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif.
Berkaitan dengan hal ini , maka bila memakai
pengukuran Government Effectiveness Index, Pemerintah Indonesia
masih perlu usaha keras untuk memperbaiki efektivitas kinerja
pemerintah. hal ini bisa dilihat dari gambar grafik yang
membandingkan indeks efektivitas pemerintah diantara negaranegara Asia Pasifik. Grafik ini , menempatkan bahwa indeks
efektivitas pemerintahan Indonesia masih dibawah negara
Singapura, Malaysia, China, dan Thailand. Pemindahan Ibu Kota
dapat menjadi momentum untuk perbaikan kinerja pemerintahan
yang diawali dari pemerintah pusat.
Pemindahan dan pembangunan Ibu Kota negara baru
diharapkan dapat memberikan dampak terhadap (1) perbaikan
kinerja ekonomi, seperti tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi
baru, node baru pusat infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan
pembangunan wilayah, dan (2) meningkatkan perbaikan fungsi
administrasi pemerintah dengan mewujudkan sistem administrasi
pemerintahan yang lebih efektif. Berkaitan dengan hal ini
maka bab ini akan fokus membahas aspek perbaikan fungsi
administrasi pemerintah.
Sebuah institusi birokrasi yang mematuhi peraturan dan
kebiasaan yang ketat dalam melakukan sesuatu dianggap bukan
pemerintah yang modern. Administrasi birokratisnya tidak memiliki
prasyarat untuk inovasi, yaitu pemikiran kreatif, eksperimen
gagasan dan kreativitas1. Menanggapi berbagai tuntutan ekonomi,
politik dan ideologis, maka struktur dan proses pemerintahan
berubah dan dimodernisasi. Pelayanan publik tradisional
seharusnya mengembangkan cara-cara kreatif untuk mengatasi
hambatan fiskal dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
yang efisien. Administrasi publik yang berorientasi proses
konvensional seharusnya memberi jalan kepada manajemen publik
berfokus pada hasil; dan pemerintah daerah berkolaborasi dan
bekerja secara horizontal untuk mengatasi hegemoni lembaga
pusat. Mengingat perkembangan ini , maka inovasi dan
perubahan sistem yang lebih baik telah menjadi tantangan di
pemerintahan.
Keberhasilan pemerataan pembangunan regional (balanced
regional development) melalui pembangunan Ibu Kota negara baru
tergantung pada dukungan kebijakan pemerintah yang dapat
menangani dan mengakomodasi perubahan dalam sistem
pembangunan daerah (Lee, Choi, Park, 2005). Untuk itu model
sistem administrasi baru merupakan salah satu bagian kebijakan
pemerintah untuk meningkatkan fungsi administrasi pemerintah
dalam rangka optimalisasi peran pemerintah pusat di Ibu Kota
negara baru. Model sistem administrasi baru akan mendorong
kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara nanti di Ibu Kota
negara baru. Sehingga kebijakan sistem administrasi baru dapat
mendukung Ibu Kota Negara yang berciri smart city, green city, dan
bertaraf internasional (smart-green-international). Ciri utama smart
city adalah transportasi antar moda terintegrasi dengan baik (smart
mobility), tata bangunan terencana secara efisien dan efektif (smart
building), dan teknologi komunikasi/internet tersedia dengan
kecepatan tinggi.
Pengembangan administrasi baru merupakan bagian dari
intervensi yang dilakukan para pimpinan diantaranya adalah
melakukan strategi penyehatan lembaga atau sering disebut
turnaround strategy atau corporate recovery (lihat misalnya:
Chowdhury, 2002; Hofer, 1986; Slater, 1974; Suwarsono, 2007).
Sementara itu usaha yang lebih operasional bisa dilakukan melalui
beberapa tindakan seperti: reengineering (Hammer and Champy,
1993); business process reengineering (Davenport and Short, 1990);
organization restructuring (Tomasko, 1992); reorganizing (Marshall
and Yorks, 1994);` resizing (Koys et.al, 1990); rejuvenating (Stopford
& Baden-Fuller, 1990); downsizing (Budros, 1999; Freeman, 1994)
atau rightsizing (Ziffane and Mayo, 1994, 1995; Davison, 2002).
Model sistem administrasi baru yang akan dibahas lebih
menekankan pada hard factors terutama aspek sistem yang akan
menjadi dasar penentuan strategi, struktur dan sistem yang akan
dibangun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagai ibu kota
baru. Aspek struktur akan dibahas didalam penentuan struktur
lembaga pengelola Ibu Kota. Sedangkan Soft Factors akan menjadi
pembahasan di aspek aparatur sipil negara.
Pengembangan sistem administrasi baru akan banyak
dipengaruhi oleh pergeseran paradigma pemerintah dan
manajemen publik. Benington dan Hartley (2001) telah mencirikan
tiga paradigma pemerintahan dan manajemen publik yang
menerapkan pelayanan dan melaksanakan perubahan. Masingmasing paradigma berisi konsepsi dan asumsi tertentu tentang sifat
permasalahan, dan peran politisi, manajer dan struktur penduduk.
Tiga paradigma ditunjukkan pada gambar di bawah. Dua
paradigma yang pertama mungkin akrab dengan administrasi
publik 'tradisional' dan 'New Public Management' (NPM), sementara
paradigma ketiga didasarkan pada bukti pola pemerintahan dan
pemberian layanan yang muncul, yang mana kita sebut
'pemerintahan yang berpusat pada warga' (citizen-centred
governance), atau 'pemerintahan berbasis pada jaringan'
(Networked Government).
Salah satu pelajaran yang paling konsisten dari proyek
pengembangan ibu kota baru adalah kecenderungan untuk
menghabiskan biaya yang jauh lebih besar daripada anggaran yang
telah direncanakan. Tabel berikut memperlihatkan biaya besar yang
dihadapi enam contoh kasus pengembangan ibu kota negara.
Terdapat banyak variasi waktu yang diperlukan dalam proses
pemindahan ibu kota baru, mulai dari 134 tahun seperti di
Washington DC hingga hanya 12 tahun di Putrajaya Malaysia. Tabel
berikut memperlihatkan variasi waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan suatu usaha pemindahan ibu kota baru dari mulai
break-down project hingga operasional penuh ibu kota pusat
pemerintahan.
Beberapa aspek yang mempengaruhi jangka waktu pemindahan ibu
kota negara adalah:
a. Dukungan dan niat politik dari para pemangku
kepentingan, sehingga dalam beberapa kasus,
pengembangan ibu kota baru menjadi berlarut-larut.
b. Aspek eksternal yang mempengaruhi implementasi
perencanaan, seperti kasus depresi ekonomi di
Canberra dan perang sipil Amerika di Washington DC.
c. Hambatan fisik antara lokasi ibu kota baru dengan
pusat ekonomi eksisting. Kondisi ini terjadi di
Washington DC., Canberra, dan Brasilia. Contoh kasus
dengan jangka waktu yang paling singkat di Putrajaya
terjadi sebab lokasi yang berdekatan dengan
Kualalumpur sebagai Ibu Kota lama sekaligus pusat
ekonomi negara.
Strategi pemindahan ibu kota dengan membangun ibu kota
baru dapat menunjukkan keberhasilan dalam mendukung
pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional yang lebih baik.
Beberapa catatan dari keberhasilan perkembangan negara setelah
pemindahan ibu kota baru antara lain terciptanya negara yang
memiliki kekuatan sosial dan simbol kebangsaan yang kuat dalam
jangka panjang dan mengurangi tensi konflik sosial yang terjadi
pada beberapa kasus ketegangan kekuatan politis dan ekonomi di
negara studi kasus.
Di sisi lain, terjadinya kegagalan atau kurang berhasilnya
pemindahan ibu kota baru dalam mendorong negara ke arah
pembangunan yang lebih baik, yaitu antara lain tidak berhasil
mengatasi masalah kepadatan penduduk akibat lemahnya
manajemen penduduk dan lahan di wilayah yang sudah terlanjur
berkembang; kegagalan dalam mewujudkan pemerataan
pembangunan ekonomi di wilayah yang sebelumnya kurang
terbangun, akibat ketergantungan ekonomi yang terlanjut
mengakar; serta kegagalan dalam mengalihkan kecepatan
pertumbuhan perkotaan dari wilayah ibu kota lama ke ibu kota
baru dan wilayah sekitarnya.
C.2. Perbandingan dengan Negara Lain
Pemindahan, pembangunan, dan penataan ulang tata kelola
Ibu Kota Negara adalah fenomena umum yang telah dilaksanakan
oleh banyak negara. Dalam 100 tahun terakhir, tercatat lebih dari
31 Negara sukses memindahkan Ibu Kota negaranya.Selain itu,
tercatat lebih dari 35 negara di berbagai wilayah berbeda telah aktif
membahas rencana untuk memindahkan Ibu Kota
negaranya.Sejarah mencatat, pemindahan Ibu Kota Negara terjadi
setiap 2-3 tahun terjadi. Bahkan, akhir-akhir ini berlangsung setiap
2 tahun sekali. Berikut daftar negara yang telah sukses
memindahkan Ibu Kota Negaranya dan Negara-negara yang masih
dalam tahap pembahasan untuk memindahkan Ibu Kota.
Motivasi negara untuk memindahkan Ibu Kota Negaranya
sangat beragam.Namun, secara garis besar keputusan untuk
memindahkan Ibu Kota diambil untuk mengatasi permasalahan
politik, ekonomi, maupun budaya di negara ini .Terdapat
empat motivasi utama yang memicu pemindahan Ibu Kota di
banyak negara.Berikut kumpulan motivasi beberapa Negara yang
telah berhasil memindahkan Ibu Kota negaranya.
Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar pemindahan
Ibu Kota negara didasari oleh permasalahan di Ibu Kota
sebelumnya.Permasalahan ini dapat berupa kemacetan,
banjir, kepadatan penduduk, dll.Motivasi lainnya yang mendasari
pemindahan Ibu Kota adalah usaha untuk memeratakan
pebangunan nasional, penguatan identitas bangsa, dan isu sosial
politik/ketahanan. Secara lebih rinci, dibawah ini akan membahas
best practice negara yang telah berhasil memindahkan Ibu Kota
Negaranya, serta pelajaran yang dapat diambil untuk pemindahan
Ibu Kota Negara di Indonesia.
BRASILIA, BRAZIL
Overview
Pemindahan Ibu Kota Negara ke Brasilia adalah usaha untuk
menciptakan kebanggaan nasional masyarakat Brasil dengan cara
membangun Ibu Kota Negara yang modern di abad 21. Konsep ibu
kota baru di pedalaman Brasil telah dipertimbangkan pada akhir
abad ke-18 oleh para pejuang kemerdekaan negara. Ibu kota-kota
brazil sebelumnya terletak di pantai Atlantik di tempat konsentrasi
kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor dan ditandai oleh
dominasi Portugis. Terdapat beberapa hal penting dalam memulai
project ini, salah satunya adalah keinginan untuk
mengintegrasikan negara secara ekonomi, politik, dan
sosial.29Pembangunan Ibu Kota Negara baru juga merupakan salah
satu dari rencana untuk membangun interior wilayah yang
dinamakan cerrado di wilayah Amazon untuk membangun
interkonektivitas antar wilayah dan untuk memindahkan pusat
gravitasi ekonomi dan politik dari wilayah pesisir ke tengah wilayah
Brasilia.30Tujuan utama pemindahan Ibu Kota adalah untuk
mengintegrasikan negara dalam hal ekonomi dan spolitik dan
menciptakan pusat pertumbuhan di tengah wilayah negara.
Ide dan realisasi. Pembangunan tahap awal Brasilia
dilaksanakan dengan relatif cepat sebab adanya desakan politik
untuk memindahkan Ibu Kota Negara dalam satu periode
pemerintahan Presiden (5 tahun), yang pada saat itu berada
dibawah pemerintahan Presiden Juscelino Kubitschek. Lokasi Ibu
Kota baru berjarak 600 mil atau 934 km sebelah barat dari Rio de
Janeiro dengan luas: 5,814 km2 atau 581.400 Ha. Lokasi Brasilia
dipilih sebab wilayah ini relatif aman dari bencana alam,
tidak ada polusi, dan memiliki iklim yang cukup baik. Aspek
perencanan kota dibuat oleh Lucio Costa, dan desain kota dibuat
oleh arsitek bernama Oscar Niemeyer. Konsep Brasilia dibuat
berdasarkan ide modernis dari Le Corbusier tentang potensi
transformasi sosial yang terkandung di konsep kota. Kota terencana
harus harus menjadi blueprits bagi transformasi sosial dan katalis
pembangunan negara.Fungsi Kota Brasilia direncanakan sebagai
pusat administrasi pemerintahan yang inklusif dan terbuka bagi
seluruh lapisan masyarakat. Namun, realisasi nya kota ini tidak
dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
Brasilia dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan budaya di Brazil
yang menegaskan elemen khas Brazilia kedalam gaya arsitektur
kota. Arsitektur di desain melengkung dan ruang terbuka yang
menghasilkan feeling of freedom, flight, and suppleness. Ikonografi
(ilmu tentang seni dan membuat arca) dan topografi dibuat dengan
menegaskan dekolonisasi dan moderenitas. Master Plan kota ini
dibuat dengan bentuk pesawat terbang yang melambangkan
representasi Brasilia sebagai “the capital of the airplane”, Brasilia
merupakan tempat pertama yang dibangun dengan akses Jet, hal
ini kontras dengan Ibu Kota terdahulu yang lebih menekankan
akses kapal laut yang merupakan Ibu Kota peninggalan.
Pemindahan Ibu Kota adalah misi untuk menyusun dan
menstimulasi teknologi dan inovasi.
Banyak pengamat yang melihat bahwa permasalahanpermasalahan di Brasilia yang ada saat awal pemindahan telah
diselesaikan dan diperbaiki. Brasilia berhasil menyeimbangkan
kehidupan ekonomi dan politik dan telah berhasil mencapai misi
untuk membangun pedalaman di Negara Brazil. Pembangunan di
cerrado telah mengubah Brazil dari negara pengimpor makanan
menjadi salah satu negara “breadbasket” terbaik di dunia.
Pembangunan di Brasilia juga telah meningkatkan konektivitas
transportasi dan mendorong munculnya pusat ekonomi sekunder
di bagian utara yang kurang berkembang. Program jalan nasional
sukses menghubungkan Ibu Kota baru dengan Ibu Kota negara
bagian dan pusat penduduk dan ekonomi lainnya. Pemindahan Ibu
Kota ke Brasilia dikenal sebagai proyek yang terorganisir dengan
sangat baik. Pembangunan kota menghadirkan semangat
eksperimental, spontanius, dan improvisasi.
Perkembangan Kota Brasilia saat ini terlihat dari
pertumbuhan penduduk dan tingkat GDP per kapitanya, sebagai
berikut:
a. Populasi terus meningkat dari awal pemindahan. Tahun
1960: 136.643 orang; Tahun 2000: 2.931.823 orang;
Tahun 2019: 4.558.991 orang
b. Brasilia menjadi kota terbesar ketiga di Brazil setelah Rio
de Janeiro dan Sao Paulo
c. GDP per capita tertinggi di Brazil R$ 64.653, sebagai
perbandingan Rio de Janeiro hanya R$ 31.064
Durasi Pembangunan. Periode pembangunan selama 5 tahun
dimulai pada akhir tahun 1956 hingga tahun 1961. Tema
pembangunan Kota Brasilia adalah Modernist City, dengan
infrastruktur yang dibangun meliputi fungsi pemerintahan,
perumahan, sport center, taman, botanical garden, kebun binatang,
bioskop, teater, restoran, pusat kebudayaan, perbankan, industri
lokal kecil. Konsep perencanaan memiliki dua sumbu utama
berpotongan sumbu dan sumbu perumahan. Pada titik temu antar
sumbu terdapat area komersial dan pusat kebudayaan.
Biaya. Skema Pembiayaan konstruksi awal pembangunan
Brasilia menggunakan biaya APBN sebesar $8.1 Milyar untuk
infrastruktur dasar dan bangunan- bangunan penunjang penting
seperti pemerintahan dan tempat tinggal pegawai. Selanjutnya,
pada tahap pengembangan skema pembiayaan menggunakan Land
Value Capture dengan cara menjual tanah di Brasilia dengan tetap
ditopang oleh APBN.
Lesson Learned. Terdapat beberapa catatan penting yang
dapat menjadi pembelajaran dari pemindahan Ibu Kota Negara di
Brazil, antara lain:
• Ruang terbuka hijauyang luas dapat menjadi acuan pembangunan
IKN baru. Lebih dari 50% wilayah Brasilia merupakan ruang
terbuka hijau meliputi: Park, Green Spaces, Zoo, Botanical Garden,
dan Sport Complex. Proporsi ruang Terbuka Hijau yang besar serta
konsep pengembangan kota yang hijau, ramah lingkungan dan
berkelanjutan penting mengingat pembangunan Brasilia di wilayah
hutan Amazon yang menjadi paru-paru dunia.
• Perlunya perencanaan yang matang terkait infrastruktur, dan
intergrasinya terhadap konsep pembangunan yang diharapkan.
Jarak antar zona peruntukan di Brasilia terlalu jauh, dan desain
kota berfokus pada kendaraan pribadi sehingga tidak ramah
terhadap pejalan kaki.
• Pembangunan Ibu Kota baru tidak boleh meremehkan risiko politik
– pemindahan Ibu Kota membutuhkan kepastian hukum untuk
meminimalisir risiko politik kedepannya.
• Proses pembangunan awal relatif singkat selama 5 tahun (1956-
1961), menjadikan Brasilia sebagai katalis pertumbuhan ekonomi.
• Pentingnya investasi di infrastruktur nasional – infrastruktur dapat
memberikan dampak positif terhadap pemerataan pembangunan
dan mempercepat arus ekonomi.
CANBERRA, AUSTRALIA
Overview
Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota di Australia dibuat
pada tahun 1908.Tantangan saat itu adalah bagaimana mencari
lokasi yang yang bersifat netral dan tidak memberikan special
privilege terhadap daerah manapun. Pada saat itu, keputusan yang
diambil adalah memindahkan Ibu Kota ke lokasi yang berjarak
sama ke kedua kota terbesar di Australia yaitu Sydney dan
Melbourne. Pembangunan Ibu Kota yang baru dimulai pada tahun
1913, namun sempat ditunda sebab perang dunia I dan masalah
keuangan di Australia.
Desain Ibu Kota dikompetisikan secara internasional pada
tahun 1911 dan menghasilkan 137 skema yang diajukan.Desain
yangmemenangkan kompetisi saat itu adalah desain Walter Burley
Griffin dariyang berasal dari Amerika.Desain Griffin menggunakan
bentuk segitiga sebagai struktur kunci desain perkotaan. Segitiga
parliamenter dibentuk dengan tiga poros yang membentuk
segitiga.Kota ini dibangun di tiga bukit yang membentuk struktur
kunci dari rencana arsitektur perkotaannya. Gedung pemerintahan
terletak di sekitar danau buatan, dan pemukiman memiliki area
terbuka yang luas.Konsep garden-city dipilih untuk
diimplementasikan di Canberra sehingga masyarakat Australia
menyebut Ibu Kota baru sebagai “the bush capital”.
Nama dan lokasi yang dipilih memiliki arti khusus.Lokasi
Canberra mengutamakan keserasian lansekap, topografi, dan
keindahan alam.Nama Canberra diserap dari lokal “Kambera” yang
memiliki arti “tempat berkumpul (the meeting place)”. Pada zaman
dahulu, lokasi ini merupakan tempat berkumpul orang aborigin
dari berbagai suku untuk pertemuan seremonial. Banyak nama
jalan di Canberra diambil dari Aborigin, dan Museum Nasional
Australia memamerkan koleksi artefak kebudayaan Aborigin.
Lokasi Canberra berada di wilayah inland 280 Km selatan barat
daya Sydney dengan luas 814 km2. Konstruksi Canberra dimulai
pada tahun 1911 dan membutuhkan waktu pembangunan selama
50 tahun sampai benar-benar selesai.
Durasi Pembangunan
Pembangunan Infrastruktur Dasar
• 1920 – 1930: Jalan dan sewerage dibangun, penanaman
pohon dimulai, dan - 59 - Parlemen dibangun. Pertokoan,
kantor, hotel, dan perumahan diselesaikan untuk 1,100
orang pegawai.
• 1927: - 59 - legislatif pindah ke Canberra.
• 1935 – 1945: Pembangunan terhambat akibat great
depression dan WWII
Percepatan Pembangunan dan perkembangan daerah satelit
melalui Y Plan
• 1960an: Canberra tumbuh cepat sesuai pemindahan fungsi
pemerintahan dan permukiman baru.
• 1962: pertumbuhan kota satelit Woden Weston Creek
berjarak 12 km dari pusat perkantoran.
• 1967: Y Plan menjadi dasar perkembangan kota satelit
sebagai kota, namun tetap terhubung melalui sistem
transportasi yang komprehensiE.
• 1971: Kebijakan pemilikan lahan untuk dikuasai pemerintah
memicupemerintah membayar ganti rugi sebesar
USD 1,8 miliar kepada swasta.
Kemandirian kota dan Perkembangan Kapital pada era 100
tahun Canberra. 1989: Struktur baru pemerintah, melibatkan dua
tingkat sistem perencanaan yaitu Australian Capital Territory (ACT)
dan pusat yang bertanggung jawab untuk - 60 - strategis untuk
pemerintahan pusat.
Biaya. Tabel dibawah ini merupakan estimasi biaya konstruksi dan
pengambilalihan lahan dari periode 1954 sampai 1987. Estimasi ini
tidak termasuk kategori lain seperti gaji National Capital
Development Commision (NCDC) atau yang sekarang disebut
National Capital Authority (NCA), subsidi bagi penduduk Canberra,
atau pengeluaran lain dari periode 1911 sampai 1953.
• Waktu implementasi yang panjang rentan terhadap risiko
internal
• dan eksternal. Proses konstruksi infrastruktur dasar
terhambat oleh proses politik dan birokrasi serta faktor
sosial-ekonomi secara eksternal (Great Depression dan WWII).
• Penguasaan lahan oleh pemerintah memudahkan koordinasi
rencana dan pembangunan pada tahap selanjutnya.
• Pentingnya membentuk Badan Otorita. Tahapan akhir
pembangunan Canberra berhasil setelah dikelola oleh Komisi
independenNational Capital Development Commission
(NCDP) untuk mengelola perencanaan, pengembangan, dan
konstruksi mampu mempercepat proses pembangunan
dengan tetap berpedoman pada “Y Plan”
• Perencanaan konsep Garden City di Canberra dapat menjadi
contoh konsep pembangunan IKN dengan konsep forest city
dengan mengintegrasikan bentang alam yang terdiri dari
kawasan berbukit dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan
struktur topografi.
WASHINGTON DC, USA
Overview. Pemindahan Ibu Kota ke Washington.D.C., adalah
produk dari kompromi politik sebagai solusi untuk mendapatkan
tempat permanen bagi Pemerintah Federal AS. Sebagai bagian dari
kebijakan keuangan pada era Hamilton (Sekertaris
pembendaharaan pertama AS era Presiden George Washington),
Kongres mendukung Bank Amerika Serikat untuk bertempat di
Philadelphia, dan sebagai gantinya, the special District of Columbia
diberikan ke Kongres (Pemerintah) untuk dibangun pusat
pemerintahan di sekitar Sungai Potomac. Kebijakan Hamilton
mendorong konsolidasi kekuatan ekonomi di tangan para, investor,
dan pedagang yang mendominasi di timur laut perkotaan, Ibu Kota
sebagai kekuatan politik harus berada di wilayah pertanian yang
lebih ke selatan dan terpisah dari para elit ekonomi.
Ide dan realisasi. Setelah lokasi untuk Ibu Kota seluas 177
km2 dipilih pada 1790, Presiden Washington menunjuk Pierre
Charles L’enfant, seorang insinyur Prancis dan mantan perwira
Angkatan Darat Kontinental untuk merancang dan merencanakan
Ibu Kota baru. Konsep Master Plan yang dibuat saat itu adalah
magnificent city, worthy of the nation, free of its colonial origins, and
bold in its assertion of a new identity. Rencana besarnya adalah
untuk memberi pride pada Capitol yang akan dibangun di sebuah
bukit yang menghadap dataran datar di sekitar Potomac. Sebuah
National Mall yang menghubungkan legislatif ke sungai dan akan
dibatasi oleh berbagai bangunan megah. Diluar wilayah dirancang
sejumlah jalan luas yang salah satunya akan terhubung dengan
rumah presiden. Banyak dari visi besar L’Enfant diabaikan selama
abad ke-19, namun mulai tahun 1922 desain nya mulai
diimplementasikan.
Durasi Pembangunan. Pembangunan Ibu Kota baru
membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk menjadi
kota yang sukses dan mandiri. Desain DC dirancang pada tahun
1791, namun baru diimplementasikan pada tahun 1922. Pada
tahap awal pemindahan, DC sangat bergantung pada dana dari
pemerintah federal selama 40 tahun, terlebih pembangunan DC
sempat terhambat sebab adanya perang tahun 1812 dan
kebakaran the White House, the Capitol Building, dan the Library
of Congress pada tahun 1814. Masalah sosial juga timbul dari
banyaknya budak dan meningkatnya angka populasi pada tahun
1960an. Tahun 1872 pemerintah distrik bangkrut sesaat setelah
runtuhnya Jay Cooke and Company (Perusahaan induk Bank
nasional pertama di New York dan pemegang 100% obligasi untuk
pekerjaan umum). Namun, setelah lebih dari 200 tahun
pembangunan, DC mulai menjadi pusat pemerintahan dengan GDP
yang tinggi dan populasi penduduk yang terus meningkat
Biaya. Untuk mengestimasi biaya pembangunan Ibu Kota
baru di AS cukup sulit karena:
a. Saat awal kemerdekaan AS posisi pemerintah negara bagian
lebih kuat dari pemerintah federal, dan negara-negara bagian
masih mengeluarkan mata uang sendiri.
b. Tanah yang digunakan diberikan oleh negara bagian
Maryland dan Virginia ke pemerintah federal tanpa biaya.
c. Tenaga kerja untuk awal pembangunan dilakukan oleh
budak. Diperkirakan biaya pembangunan Ibu Kota pada
tahap awal adalah 3 kali lipat dari Anggaran Pemerintah
Federal selama lebih dari 10 tahun pertama.
Lesson Learned. Pembangunan Ibu Kota negara baru
membutuhan waktu puluhan bahkan ratusan tahun, untuk
menjadi mandiri. Washington membutuhkan waktu 60 tahun
untuk menjadi pusat populasi yang berkembang, dan hingga saat
ini masih berusaha untuk menghasilkan sumber pendapatan
secara mandiri.
Pusat administrasi yang megah dan monumental
membutuhkan investasi secara bertahap. Rencana awal
pembangunan taman, dan di Washington belum rampung hingga
lebih dari 100 tahun, hingga diperlukan alokasi dana yang cukup
besar dari Kongres.
SEJONG, KOREA SELATAN
Overview. Pemerintah Korea Selatan menetapkan Sejong
sebagai Ibu Kota Negara pada tahun 2005 melalui Undang-undang
khusus.Pemindahan Ibu Kota Negara ini bertujuan untuk
merelokasi 2/3 instansi pemerintah dari Seoul.Kota Sejong berada
120 Km dari Seoul yang merupakan pusat perekonomian.Letaknya
yang berada di tengah wilayah Korea Selatan menjadikan Sejong
dipilih sebagai Ibu Kota untuk melaksanakan pemerataan
pembangunan dan mengurangi beban Seoul.
Kota Sejong dibangun sebagai pusat pemerintahan Korea
Selatan dan juga sebagai pusat riset dan high-tech industri.
Konstruksi pembangunan Kota Sejong dilakukan mulai tahun 2007
hingga pada tahun 2017, dalam kurun waktu 10 tahun ini
telah terbangun 40 instansi pemerintahan dan 15 lembaga
penelitian.
Rencana pembangunan Sejong mengedepankan
pengalokasian ruang terbuka hijau hingga seluas 50% dari total
luas area. Perwujudan konsep green city ini juga dilakukan dengan
pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan memperbanyak
penggunaan transportasi publik. Hal ini juga didorong oleh
Penanaman 40 juta pohon serta pembangunan jalur sepeda
sepanjang 350 Km. Desain Kota Sejong berbasis pada
pengembangan transportasi publik dan pedestrian dimaksudkan
untuk mengakomodasi kebutuhan publik. Pengembangan
transportasi publik ini menjadikan Kota Sejong menjadi pusat
sistem transportasi nasional yang terhubung dengan kota-kota
besar lainnya dalam waktu yang relatif singkat.
Durasi Pembangunan. Untuk mengelola pembangunan dan
pengembangan Kota Sejong, pemerintah membentuk MultiFunctional Administrative City Construction Agency
(MACCA).Badan ini memiliki wewenang untuk implementasi,
perizinan, perencanaan, dan konstruksi pada area pusat Kota
Sejong.Target pembangunan Kota Sejong bertujuan untuk
mencapai jumlah penduduk hingga setengah juta penduduk dalam
rentang waktu kurang dari 25 tahun.Pada tahun 2016, populasi
Kota Sejong sudah mencapai 250.000 jiwa dan pemindahan - 67 -
pemerintah hampir selesai.45Berikut merupakan alur perencanaan
dan pembangunan Kota Sejong.
Biaya. Perkiraan biaya pembangunan awal pada tahun 2005
sekitar $8 miliar namun pengembangan secara menyeluruh Kota
Sejong saat ini diperkirakan akan menelan biaya pemerintah
sebesar $22 miliar selama 30 tahun. Pembebasan lahan untuk kota
baru dilakukan melalui proses partisipasi publik yang melibatkan
pemilik tanah yang ada di pedesaan tempat Sejong akan dibangun.
Pemilik tanah bersedia untuk bernegosiasi, sebab telah
mendukung rencana pengembangan kota baru sejak awal.
Lesson Learned
• Pentingnya kesepakatan politik dari berbagai pihak. Pada
awal perencanaan, Sejong perlu mengkompromikan berbagai
hal dalam menghadapi oposisi politik. Perdebatan terus
berlanjut terkait bagaimana tentang mengatasi
ketidakefisienan pemerintahan yang terpisah antara Seoul
dan Sejong.
• Perekonomian kota membutuhkan waktu puluhan tahun
untuk berkembang secara keseluruhan. Jarak yang terlalu
dekat membuat Sejong lebih lama untuk berkemban se










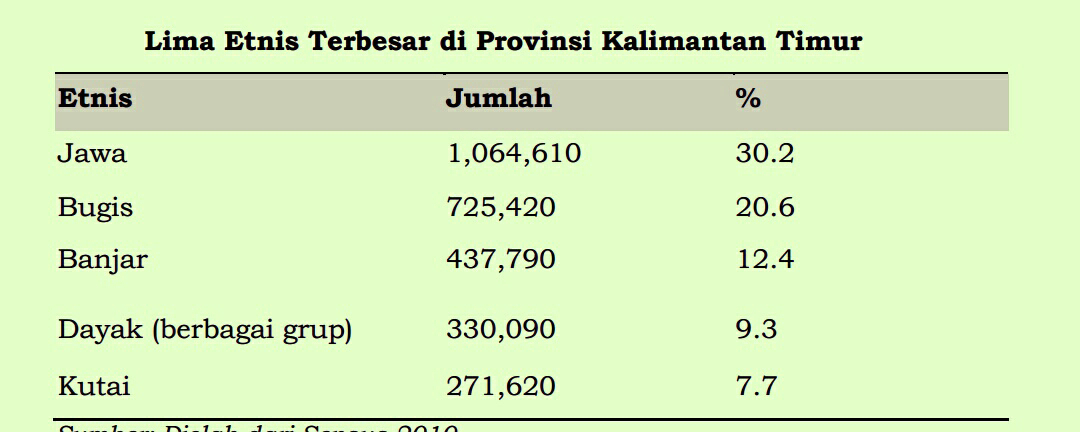
.jpg)









